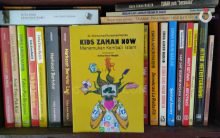Dari Yogya Mencari Apa yang Benar

Judul Buku : Apa yang Benar, Bukan Siapa yang Benar
Penulis : Emha Ainun Nadjib
Tahun : Agustus, 2020
Penerbit : Bentang Pustaka, Yogyakarta
Ada hal apa di balik Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dicirikan sebagai kota pelajar dan budaya? Mengapa provinsi ini dianggap unik secara administatif? Adakah kaitannya dengan peran ganda Sri Sultan sebagai raja sekaligus gubernur? Benarkah Yogya dianggap sebagai “pusat kebudayaan” Jawa setelah Perjanjian Giyanti (1755) berlaku? Bagaimana nasib Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada tahun 1946 bila tak ada kebesaran hati sang Raja Yogya?
Membincang Yogya maka sudah semestinya membincang apa saja. Melalui buku berjudul Apa yang Benar, Bukan Siapa yang Benar (2020) karya teranyar Cak Nun ini kita diajak menggembara ke tiap sudut ke-Yogyakarta-an. Dari spektrum sabda luhung ratu pandhita (hlm. 37) di balik dinding keraton sampai ketasawufan Mbah Wongso (hlm. 70) sang penjaja nasi kucing ala angkringan di barat perempatan Wirobrajan selatan jalan.
Sejumlah 73 esai di buku ini membuktikan Cak Nun—meminjam istilah Romo Iman—“terus mlaku lan tansah lelaku…” Spesifikasi lelaku yang ia catat seakan mengelana ke luar, menembus batas-batas peristiwa dari, ke, dan melalui Yogya, namun pada titik tertentu ia kembalikan ke diri sendiri. Langgam-liris buah tulisannya terkadang menggugat, namun seringnya menguraikan untuk merefleksikan.
Sebagaimana penggembaraan ke sebuah tempat, Cak Nun terasa dekat mendampingi, bahkan beberapa kali menunjuk sebuah kondisi atau lokasi. Bukan hanya keluar, melainkan ke dalam diri. Kondisi atau lokasi luar maupun dalam yang ia tunjuk, sepanjang alur tulisannya, acap kali menyisakan tanda tanya tersendiri bagi pembaca.
Memang tanda tanya ini menjadi bentuk keasyikan tersendiri bagi sidang pembaca yang tak bermotif mencari “siapa” tapi “apa” yang cenderung luas, dinamis, dan bahkan interpretatif. Hidup memang tak sekaku mencari tahu sang subjek, sosok, atau identitas. Aneka multidimensi hidup dan kehidupan memang lebih berharga bila digali dengan kata tanya “apa”—apalagi yang dicari adalah benar serta kebenaran itu sendiri.
***
Mengapa Yogya? Bagi Cak Nun Yogya tak ubahnya sebuah ruang (pengalaman) batin setiap orang yang terkadang terasa jauh tapi tak jarang pula terasa dekat. Ia menyebut Yogyakarta adalah rumah keduanya setelah Jombang. Di kota ini ribuan tulisan ia hasilkan dan bisa terlacak sejak era 70-an. Tiap tulisan yang dibukukan di sini pun punya riwayat sejarah khusus.
Semua tulisan telah tersiar di Koran Kedaulatan Rakyat (KR) antara 2016 hingga 2017. Terbit tiap Selasa setiap minggu. Harian terkenal di Yogya ini meminta khusus kepada Cak Nun untuk rutin mengisi kolom khusus bernama Wedang Uwuh. Sebelum itu, kita tahu, dua nama kolumnis kawakan seperti Umar Kayam dan Bakdi Soemanto juga mengisi ruang serupa. Keduanya telah berstatus mendiang.
Kendati menyiarkan tulisan di koran sama, gaya penulisan ketiganya jelas berbeda. Sebab periode publikasinya terpaut jauh. Pak Kayam tahun 90-an, sedangkan Pak Bakdi mulai 2007. Namun, saya kira punya kemiripan. Antara lain di tulis dengan bahasa yang enak. Juga, bahasa Jawa ngayogyakartan cukup dominan.
Efek macam apa yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa “lokal” semacam itu bagi langgam esai populer? Tentu saja kedekatan, kemesraan, dan klop. Terlebih percakapan antartokoh cenderung ditonjolkan, sehingga kentara efek intrinsiknya seperti alur, plot, setting, dan lain sebagainya. Maka perbedaan antara esai dan cerpen tak lagi kaku. Tulisan Cak Nun di buku ini berada di kotak tersebut.
Sepintas pendekatan esai berbasis dialog ini terlihat mudah, namun sesungguhnya ia paling sukar dalam penceritaan. Ada dua sebab setidaknya. Pertama, penokohan harus kuat. Tanpa karakter (khas) sang tokoh, maka dialog tak ubahnya seperti monolog. Kita tahu Cak Nun sangat kuat di sini. Hampir keseluruhan esainya berisi dialog. Sisanya prolog dan epilog. Bahkan kedua hal itu kebanyakan diawali dan diakhiri dengan dialog!
Saya tertarik mengapa dialog menjadi titik sentral bagi tulisan Cak Nun. Selain segi nonteknis tulisan seperti pola pendekatan untuk pembaca luas di KR (khususnya di Yogya) ada alasan lain: misalnya secara sosiologis. Bukankah masyarakat kita lebih dekat dengan tradisi oral dan bebrayan? Membincangkan sesuatu, bahkan bisa berjam-jam, adalah bagian inheren dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
Tentu saja ada perbedaan yang mencolok antara berbincang, berdiskusi, dan apalagi ngrasani. Semuanya masuk ke dalam tradisi oral. Namun, di antara ketiganya, manakah yang paling menunjukkan ciri khas? Sekali lagi, saya di sini tak mencari siapa yang benar tapi kalau bisa apa yang benar.
Itu pun perlu ditambah keterangan empan papan. “Pengetahuan tidak bisa diketahui kebenarannya kalau tidak terletak pada koordinat ruang dan waktu yang tepat. Orang Yogya menyebutnya patrap.” (hlm. 4).
Kita ingat tokoh-tokoh di dalam tulisan Cak Nun seperti Cak Markesot maupun Cak Kartolo. Saking seringnya dipakai, keduanya sampai “ikonis” dan menyisakan pertanyaan bagi pembaca: apakah tokoh-tokoh ini berperangai sebagaimana adanya?
Apakah ia faktual ataupun fiksional? Timbulnya pertanyaan demikian menandakan betapa karakter tokoh yang dikonstruksi Cak Nun sangatlah kuat. Sampai-sampai susah dibedakan “mana bayangan, mana kasunyatan, mana khayalan.” (hlm. 2).
****
Cak Nun menggunakan tiga tokoh imajiner bernama Gendhon, Pèncèng, dan Beruk untuk semua esainya di buku ini. Sebetulnya ada tokoh satu lagi sebagai aku-lirik yang bernama Simbah. Kita bisa menganggap tokoh simbah ini tiada lain dan tiada bukan adalah Cak Nun sendiri.
Sementara Gendhon, Pèncèng, dan Beruk, oleh tokoh Simbah disebut sebagai anak-cucunya. Meskipun begitu, kalau kita hendak pakai pendekatan psikologi pengarang, semua tokoh-tokoh fiktih tersebut merupakan hasil dari konstruksi imajiner sang empunya tulisan.
Bagi saya pribadi, ketiga tokoh ini bukan saja unik, melainkan mengingatkan saya kepada karya Cak Nun berjudul Gerakan Punakawan Atawa Arus Bawah (1994). Kalau di buku tersebut empat tokohnya disebut punakwan (Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong) yang tiap karakternya mempunyai kekhasan tersendiri: Bagong sisi lain dari Ismaya Badranaya, Petruk serupa pengamat, Gareng dengan pikiran reflektifnya, dan Semar selalu berwibawa karena menjaga keseimbangan.
Sementara karakter Gendhon, Pèncèng, dan Beruk hampir senada, yakni “tidak pandai, tidak hebat, tidak juga lantip. Namun, mereka selalu bersungguh-sungguh, tekun, dan—ini yang terpenting dan membuat saya mengambil mereka sebagai anak-anak—setia.” (hlm. 2).
Di luar ujaran Sang Simbah di situ, saya juga mendapati ketiga tokoh ini sangat “milenial” karena selain keluguan dan antusiasme khas generasi kiwari, mereka juga supel. Apalagi dengan simbahnya sendiri. Tata krama yang kerap membatasi relasi di antara tokoh yang terpaut perbedaan usia, pada kasus hubungan Simbah dan Gendhon, Pèncèng, serta Beruk, hampir tak begitu berlaku. Bahkan beberapa kali nranyak dengan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang berani.
***
Saya sendiri suka esai bertajuk Ki Gedé Kadisobo (hlm. 198). Sang Simbah terheran-heran dengan pertanyaan anak-cucunya. Apalgi isi pertanyaan tersebut jauh lebih tua ketimbang usia mereka. “Simbah dulu teman dekatnya Mbah Linus?” begitu tanya Beruk. Lalu direspons, “Tentu saja Simbah terheran-heran. Kok Beruk kid zaman now ini tahu lumayan detail tentang tokoh-tokoh Yogya masa silam. Pasti ada sesuatu di balik pertanyaannya itu.”
Dialog berlangsung hangat. Apalagi tokoh Simbah menjelaskan cukup rinci. Seperti mengenang peristiwa yang telah lewat melalui tuturan yang mengucur deras tersebut kita sontak ingat bagaimana hubungan Simbah dan Linus di era 70-an.
Mereka bersahabat sejak bersama-sama di sebuah komunitas sastra di Malioboro. Sewaktu keduanya naik daun di jagat kepenyairan, pada akhir 80-an mereka “dipertengkarkan” hanya karena perbedaan agama. Simbah Islam, Linus Katolik. Beruk memberondongkan pertanyaan. “Simbah bersaing dengan Mbah Linus?” (hlm. 200).
“Mustahil saya berani menyainginya. Saya pasti kalah. Ketika Simbah ke Iowa satu tahun atas undangan Pemerintah Amerika Serikat, Simbah usulkan yang harus diundang tahun berikutnya adalah Linus Suryadi AG…” jawab Simbah seraya menguraikan bagaimana adu domba itu terjadi di kalangan sastrawan.
Perbedaan cara pandang dalam memahami kredo kesenian, kesusastraan, bahkan agama wajar terjadi di masyarakat heterogen. Namun, ia makin memanas bukan dikarenakan oleh pihak yang dianggap berseteru, melainkan dari pihak eksternal. Media massa bisa ikut serta. Terlebih waktu itu koran menjadi medium berbalas pantun.
Tokoh Simbah di sini secara tak langsung menampik dan ber-tabbayun apa yang sebenarnya terjadi. “Lho, saya tidak pernah konflik dengan Mbah Linus, Ruk!” Simbah menyangkal keras. Terlepas kebenaran faktual isi esai ini, saya kira penting melihat betapa pola kesinambungan (intertekstual) dalam tubuh tulisan.
***
Di awal sudah dipaparkan bahwa buku Cak Nun ini jamak mengulas memori sosial yang terjadi di Yogyakarta. Sementara tokoh Simbah dan ketiga anak-cucunya adalah penyampai-penutur kisah itu. Cerita yang disampaikan tak lagi penting ditelisik benar dan salahnya, apalagi siapa di belakang tokoh atau peristiwa yang dibicarakan.
Di sini kita mencoba menerima semua kemungkinan, memosisikan jalin-kelindan peristiwa yang diusung apa adanya. Dengan begitu semua esai-cerita yang ditulis Cak Nun bukan sekadar menarik diikuti, melainkan juga mengajarkan kita untuk mengapresiasi dinamika hidup serta kehidupan manusia Yogya secara telanjang-setelanjangnya. Buat teman-teman yang ingin memiliki buku Cak Nun bisa klik: terusberjalan.id.