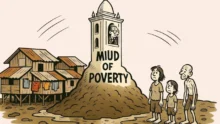Kabar Duka Dari Jerman dan Negeri Ini

Dunia ini seolah-olah adalah sebuah panggung wayang. Di atasnya, tokoh-tokoh dari berbagai penjuru muncul silih berganti: ada Jerman yang jauh di Eropa sana, ada Indonesia dengan segala keanekaragamannya, Jawa yang sarat filosofi dan budaya, hingga sebuah dusun kecil yang bersandar tenang di kaki Gunung Merapi. Tak satu pun dari mereka hadir tanpa peran. Semua menjadi bagian dari lakon yang terus bergulir, tanpa jeda, tanpa kepastian akhir.
Cerita pun dimulai dengan irama yang menentramkan — kemakmuran, harmoni, dan kemandirian. Desa-desa hidup dari tanahnya sendiri, masyarakat mengenal arah dan jati diri, dan kehidupan bergulir dalam kesadaran akan makna dan keberlangsungan. Namun, sebagaimana dalam kisah wayang, lakon bisa berubah sewaktu-waktu. Kemakmuran digantikan oleh duka, kejayaan berakhir dalam pengusiran, dan desa-desa yang dulu mandiri pelan-pelan menjadi bagian dari kawasan industri yang tak lagi menumbuhkan jiwa, hanya menyisakan suara mesin dan langkah-langkah buruh yang kehilangan arah.
Kita yang menjadi penonton sekaligus pelaku di atas panggung itu pun terpana. Kita bertanya dalam hati: benarkah semua ini adalah takdir? Ataukah ada skenario besar yang sedang dijalankan dengan cermat oleh para dalang tak kasat mata — mereka yang tak tampil di depan layar, tapi menentukan arah cerita dari balik bayang-bayang?
Narasi ini bukan sekadar kisah perubahan. Ia adalah ajakan untuk membuka mata, untuk menyadari bahwa di balik setiap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, mungkin saja ada tangan-tangan tak terlihat yang menyusun naskah dan menentukan peran. Kita hanya bisa bertanya dan terus mencari jawab, agar tak selamanya menjadi wayang yang digerakkan, melainkan menjadi manusia yang sadar akan cerita yang sedang dijalani.
Mari kita tengok Jerman, sebuah negeri yang dahulu dielu-elukan sebagai simbol negara kesejahteraan kelas dunia. Negeri ini pernah berdiri tegak sebagai lambang kejayaan teknologi dan industri modern. Pabrik-pabrik baja yang berdiri megah di pinggiran kota menjadi ikon kemajuan, sementara jaminan sosial yang kokoh menjadi kebanggaan bersama. Rakyatnya hidup dengan rasa percaya diri dan bangga terhadap pencapaian kolektif yang dibangun dari kerja keras dan solidaritas sosial.
Namun hari ini, narasi itu perlahan memudar. Di banyak penjuru negeri, terutama di desa-desa kecil, sunyi mulai mengisi ruang yang dahulu penuh kehidupan. Rumah-rumah kosong berdiri bisu, pertanda generasi muda telah berpindah ke kota, mengejar peluang yang tak lagi tersedia di tanah kelahiran mereka. Pabrik-pabrik yang dulu menjadi pusat denyut ekonomi mulai menutup pintu, tak sanggup bersaing di tengah pusaran globalisasi dan otomasi.
Krisis identitas pun menyusup ke relung masyarakat. Mereka yang dahulu hidup berkecukupan, kini merasa kehilangan arah. Mereka yang dulu bekerja dengan penuh makna dan rasa memiliki, kini harus berhadapan dengan sistem yang dingin — mengatur manusia seperti angka, dan menggantikan empati dengan efisiensi. Hidup menjadi rutinitas mekanis, bukan lagi ruang bagi pertumbuhan jiwa.
Transformasi ini bukan hanya tentang ekonomi atau demografi. Ia adalah pergolakan batin sebuah bangsa yang dulu tahu siapa dirinya, namun kini tengah bertanya kembali: ke mana arah yang harus dituju, dan nilai apa yang masih bisa dipegang? Di panggung besar bernama dunia, Jerman pun tengah memainkan lakonnya — dari kejayaan menuju kegamangan — sebuah fragmen dari cerita global yang lebih besar dan lebih dalam dari yang tampak di permukaan.
Anehnya, kisah yang terjadi di Jerman tadi terasa begitu akrab. Seakan-akan lakon yang sama sedang dipentaskan di negeri ini, hanya berbeda panggung dan bahasa. Lihatlah desa-desa di Negeri ini yang dahulu hidup dalam harmoni dengan alam — menggantungkan hidup pada ladang, hutan, dan sawah. Mereka bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang mengakar dalam kebudayaan, spiritualitas, dan rasa memiliki yang dalam terhadap tanah leluhur.
Namun kini, semua itu perlahan tergerus oleh proyek-proyek besar yang membawa nama “pembangunan” — sebuah kata yang terdengar mulia tapi kerap menyembunyikan maksud yang muram. Hutan-hutan yang dulu rindang ditebang habis, bukit-bukit dikeruk demi mineral, dan tanah-tanah warisan leluhur dijual murah kepada investor yang menjualnya kembali dengan harga berkali lipat. Penduduk asli pun perlahan kehilangan tempat berpijak. Mereka yang dulu berdaulat atas tanah kini berubah menjadi buruh di tanahnya sendiri. Yang dirampas bukan hanya hak milik, tapi juga martabat dan kebudayaan.
Untuk memahami akar dari semua ini, kita perlu menengok ke belakang, ke akhir abad ke-19 — sebuah titik balik ketika dunia mulai berubah secara drastis. Bukan kecerdasan buatan atau internet yang mengguncang peradaban kala itu, melainkan bangkitnya ekonomi ekstraktif yang berlandaskan logam, batu bara, dan sistem kolonial. Di Eropa, revolusi industri menyeret jutaan orang desa ke dalam kota, menjadikan mereka roda dalam mesin produksi yang tak mengenal henti. Sementara di Jawa, tanam paksa menjadikan petani sebagai buruh tanpa hak, mengabdi pada sistem yang menolak mereka sebagai pemilik tanah, bahkan sebagai manusia seutuhnya.
Sistem yang dibangun pada masa itu bukan hanya menjarah sumber daya alam, tetapi juga menyusun struktur relasi sosial yang menempatkan sebagian besar manusia sebagai alat, bukan sebagai subjek. Dan benih-benih dari sistem itulah yang kini tumbuh menjadi kesengsaraan yang kita saksikan hari ini — baik di Jerman yang dahulu gagah, maupun di negeri kita yang kaya tapi terpinggirkan.
Kita hidup dalam babak lanjutan dari sebuah lakon panjang yang naskahnya ditulis sejak berabad silam. Kini, pertanyaannya adalah: apakah kita akan terus membiarkan diri menjadi figuran dalam cerita yang sama, atau mulai menulis lakon baru yang lebih adil dan berpihak pada kehidupan?
Sejarawan Peter Carey pernah mengungkapkan sebuah fakta yang menggugah kesadaran sejarah kita: seandainya Belanda kalah dalam Perang Jawa (1825–1830), ekonomi global saat itu bisa saja kolaps. Mengapa? Karena Belanda telah menggelontorkan utang dalam jumlah besar untuk membiayai perang yang panjang dan melelahkan melawan Pangeran Diponegoro. Dengan kata lain, perlawanan Diponegoro tidak semata-mata soal tahta, intrik istana, atau perebutan kekuasaan di lingkup lokal. Perang Jawa sejatinya adalah perlawanan terhadap sebuah sistem global yang sedang tumbuh — sistem kapitalisme awal yang rakus dan eksploitatif.
Dalam sudut pandang ini, Perang Jawa menjadi jauh lebih dari sekadar konflik kolonial. Ia adalah medan laga antara dua pandangan hidup: satu yang memuliakan tanah, spiritualitas, dan keharmonisan; dan satu lagi yang menghitung bumi dan manusia sebagai komoditas, sebagai angka di neraca kas yang harus terus bertumbuh. Ketika Diponegoro melawan, yang dihadapinya bukan hanya pasukan Belanda, tapi juga seluruh kekuatan ekonomi-politik dunia yang menopang kolonialisme dan bernafsu menguras sumber daya tropis demi keuntungan para pemegang modal di Eropa.
Perang ini memperlihatkan betapa dalam akar persoalannya. Ia tidak lahir dari konflik sesaat, tetapi dari ketimpangan mendasar antara kehidupan yang mengakar di bumi dengan sistem ekonomi yang menganggap tanah sebagai objek, bukan ruang hidup. Dalam perang ini, kita menyaksikan benturan antara kemanusiaan dan sistem kapitalisme global yang hendak memeras hidup dari bumi demi laba.
Kini, hampir dua abad kemudian, kita kembali menghadapi persoalan yang serupa, meski dalam wujud yang berbeda. Kapitalisme telah berganti rupa — mengambil nama pembangunan, modernisasi, atau investasi. Tapi esensinya tetap sama: mengorbankan kehidupan demi pertumbuhan yang tak henti-henti. Maka, mengenang Perang Jawa bukanlah sekadar membaca sejarah masa lalu. Ia adalah cermin untuk menilai masa kini, sekaligus panggilan untuk mempertanyakan ke mana arah masa depan kita sebagai bangsa dan sebagai umat manusia.
Jerman pun, meski terletak jauh dari Jawa, mengalami lakon yang tak kalah getir. Ketika para petani meninggalkan ladang-ladang mereka untuk bekerja di industri baja, ketika manusia mulai diukur bukan dari kebijaksanaan atau kontribusinya pada komunitas, melainkan dari seberapa banyak ia dapat hasilkan di hadapan mesin, maka sesungguhnya Jerman tengah bergerak menuju keterasingan. Desa-desa yang dulunya menjadi pusat kehidupan — tempat orang mengenal tanah, musim, dan satu sama lain — perlahan kehilangan fungsinya. Tak hanya sebagai penghasil pangan, tetapi juga sebagai ruang ekologis, sosial, dan spiritual yang memberi makna dan kedalaman pada kehidupan.
Dalam sunyi, Jerman memasuki perang yang sama dengan yang pernah meletus di tanah Jawa: perang melawan sistem nilai yang menghancurkan rasa keterhubungan manusia dengan bumi dan sesamanya. Hanya saja, jika di Jawa perangnya berlangsung dalam dentuman senapan dan kuda perang, di Jerman perang ini berlangsung diam-diam, dalam bentuk keterasingan, krisis identitas, dan kekosongan makna yang membayangi kehidupan modern.
Maka jelaslah bahwa ini bukan sekadar kisah Jerman atau Jawa. Ini adalah fragmen dari sebuah kisah global yang lebih besar — tentang bagaimana manusia, di berbagai belahan dunia, telah dijauhkan dari akar kehidupannya oleh sistem yang memuja pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir. Sistem yang menggantikan gotong-royong dengan kompetisi individual, yang menukar spiritualitas desa dengan efisiensi produksi, dan yang mengabaikan pangan lokal demi makanan instan yang dikemas rapi dalam logistik global.
Dalam dunia seperti ini, kehidupan terasa cepat namun dangkal. Manusia bergerak, bekerja, dan membeli tanpa tahu lagi untuk apa. Mereka tidak lagi menanam, tidak mengenal musim, dan tidak mengenali wajah-wajah di sekeliling mereka. Di balik segala kemajuan yang diagungkan, tersembunyi kehilangan yang tak terucap: kehilangan rumah dalam arti yang paling dalam — sebagai tempat untuk merasa utuh, terhubung, dan bermakna — mungkin, inilah saatnya untuk bertanya: apakah benar kita sedang membangun masa depan, atau justru sedang berjalan menjauh dari apa yang membuat kita menjadi manusia?
Sudah saatnya kita bangun dari mimpi kesejahteraan palsu — mimpi yang menjanjikan kenyamanan melalui angka-angka pertumbuhan dan subsidi, tapi diam-diam menggerus makna sejati kehidupan. Baik di Jerman, di Jawa, maupun di sudut-sudut dunia lainnya, kita menyaksikan jejak yang sama: masyarakat yang perlahan kehilangan daya hidupnya, ketika tanah, air, dan tubuh manusia sendiri menjadi alat bagi mesin ekonomi global.
Kini saatnya kita merancang ulang gagasan tentang negara kesejahteraan. Bukan sebagai negara konsumtif yang menggaji rakyatnya untuk diam dan patuh, yang mengukur keberhasilan dari seberapa banyak belanja atau betapa tinggi konsumsi rumah tangga. Tapi sebagai sebuah ruang hidup — hidup dalam arti yang utuh: ekologis, spiritual, sosial, dan kultural. Ruang di mana manusia bukan hanya diberi makan, tetapi juga diberi kesempatan untuk merawat, mencipta, dan terlibat dalam arah hidup bersama.
Negara yang sejati bukanlah pabrik birokrasi atau pasar raksasa. Negara yang sejati adalah tanah yang memberi tempat bagi manusianya untuk tumbuh menjadi subjek pembangunan — bukan sekadar objek statistik ekonomi. Ia memberi tempat bagi pertanian berkelanjutan, bagi kebudayaan yang hidup dari bawah, bagi solidaritas sosial yang tak bisa dibeli, dan bagi keberanian untuk bertanya: ke mana kita menuju?
Karena kesejahteraan bukan sekadar kenyamanan fisik. Ia adalah perasaan terhubung, bermakna, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Dan itulah yang perlu kita perjuangkan kembali — bukan hanya dengan kebijakan, tapi juga dengan kesadaran dan keberanian untuk merajut ulang hidup dari akar yang nyaris terlupa.
Semua ini sebenarnya sudah sangat jelas. Tapi sering kali, dalam hiruk pikuk mengejar kemajuan, kita justru tersesat. Terlalu sibuk meraih target dan ambisi, hingga lupa pada hal-hal sederhana namun justru menyelamatkan: ladang yang subur yang mengajarkan kesabaran dan syukur; sawah yang hijau yang menenangkan mata dan menumbuhkan kehidupan; sungai yang mengalir jernih yang menghidupi desa-desa dan menyuarakan alam; serta masyarakat yang hidup rukun tanpa harus saling menjatuhkan demi status dan kekuasaan.
Kita melupakan bahwa peradaban besar tidak dibangun dari menara beton, gedung pencakar langit, atau jalan tol semata. Peradaban besar tumbuh dari cara manusia menjaga relasinya — dengan tanah, dengan sesama, dan dengan nilai-nilai yang memberi arah hidup. Ia lahir dari kesadaran bahwa kemajuan tidak selalu berarti lebih cepat, lebih besar, atau lebih keras, tapi lebih bijak, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.
Jika kita terus mengabaikan yang sederhana dan menyelamatkan ini, kita bukan sedang membangun masa depan — melainkan mempercepat keruntuhan. Maka mari kita kembali belajar dari yang nyaris terlupakan: dari tanah yang mengajarkan keseimbangan, dari air yang mengajarkan aliran, dan dari komunitas yang mengajarkan saling menjaga. Sebab hanya dari sanalah, masa depan yang utuh dan manusiawi bisa benar-benar tumbuh.[]
Nitiprayan, 19 Mei 2025