Ngerti, Ngroso, Nglaku
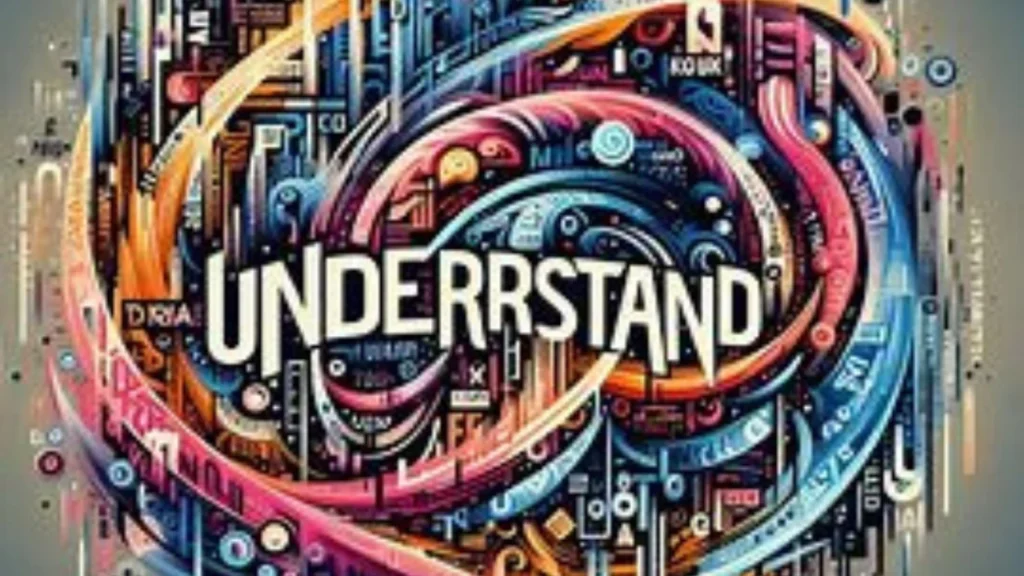
Sekolah-sekolah itu berdiri seperti katedral modern—menjulang, berkilau, dan sibuk memamerkan keagungan yang direka dari brosur dan lomba antar-instansi. Di fasadnya, slogan-slogan memantul seperti doa yang kehilangan makna: “Mencetak Generasi Emas.” “Menyiapkan Pemimpin Masa Depan.” Kata-kata yang ingin terdengar mulia, tetapi terasa getir ketika bersentuhan dengan kenyataan di dalamnya.
Di ruang kelas yang dinginnya seperti ruang tunggu rumah sakit—steril, rapi, tetapi tanpa denyut kehidupan—anak-anak duduk berjajar, rapi seperti deretan angka statistik. Mereka bukan tidak cerdas; hanya saja kecerdasan mereka dikurung dalam format-format baku: slide presentasi, buku paket, dan kertas ulangan. Mereka disuruh mengerti—menghafal rumus sampai bibirnya kering, mengulang teori sampai kepala terasa seperti gudang yang terus dijejali, bukan ladang yang diajak tumbuh. Pengetahuan dijadikan benda mati, bukan tubuh yang bernafas.
Ki Hadjar dulu mengajarkan tiga kata yang kini terdengar seperti mantra dari zaman yang kalah: ngerti, ngroso, nglaku Tiga jalan untuk menjadi manusia yang utuh. Tapi kita hanya memungut ngerti, lalu membiarkannya berkarat oleh ambisi ranking dan kurikulum yang tak sabar. Ngroso dibuang seperti serpihan yang tak efisien, karena empati dianggap bukan kompetensi. Nglaku—melakukan, menghayati—direduksi menjadi tugas rumah yang dicentang guru, bukan pengalaman yang menggugah batin.
Di kota yang bising dan makin asing bagi warganya sendiri, sekolah-sekolah itu berdiri seperti pulau kecil yang terputus dari realitas. Di luar temboknya, ketidakadilan tumbuh lebih cepat daripada gedung-gedung tinggi; tetapi di dalam, anak-anak diajari untuk menjawab soal, bukan menjawab panggilan zaman. Mereka dipoles menjadi “pemimpin masa depan”, tetapi lupa diajarkan cara mendengar tangis yang paling dekat: tangis mereka sendiri ketika merasa tak utuh, tak didengar, tak diberi ruang untuk bertanya lebih jauh dari halaman buku.
Kadang aku membayangkan: bagaimana jika salah satu anak itu diam-diam menggambar di pinggir bukunya—bukan diagram sel atau grafik ekonomi, tetapi wajah seorang ibu yang kelelahan, atau rumah kontrakan yang sebentar lagi digusur? Bagaimana jika itu bukan sekadar coretan, melainkan cara ia memanggil dunia agar lebih adil kepadanya? Mungkin guru akan menyuruhnya kembali fokus ke pelajaran. Padahal gambar kecil itu adalah pelajaran paling jujur hari itu—tentang hidup, tentang takut, tentang harapan yang belum punya bahasa.
Bukankah itu inti pendidikan yang pernah dibayangkan para pendiri gagasan merdeka? Pendidikan yang membuat manusia bertumbuh, bukan sekadar lulus. Pendidikan yang menajamkan rasa keadilan, bukan hanya ketepatan jawaban. Pendidikan yang menyentuh yang paling halus dalam diri manusia—yang membuat kita lebih peka terhadap luka orang lain, bukan makin tangkas menyembunyikan statistik ketimpangan.
Di tengah slogan-slogan yang semakin megah dan gedung yang semakin tinggi, mungkin kita perlu kembali pada sesuatu yang sederhana: bahwa manusia tak tumbuh dari hafalan. Ia tumbuh dari rasa, dari pengalaman yang menyapa, dari keberanian untuk mempertanyakan, dari kesempatan untuk keliru dan kemudian bangkit. Dari ruang yang memberi napas, bukan ruang yang meredam. Sebab generasi emas bukan dicetak. Ia didengarkan. Ia ditemani. Ia dipercayai untuk menjadi manusia sepenuhnya.
Tiga kata itu—ngerti, ngroso, nglaku—adalah semacam doa purba yang kita ucapkan tanpa lagi memahami sacinya. Dahulu ia adalah trilogi kemanusiaan: akal yang jernih, rasa yang halus, dan tindakan yang berani. Kini, ia tinggal seperti inskripsi usang di dinding sekolah: dipajang, tetapi tidak dihirup. Kita berhenti di kepala, seolah manusia hanya lahir dari definisi, bukan dari pergulatan batin dan pengalaman yang melukainya.
Sekolah-sekolah kita menjelma industri informasi: rapi, efisien, dan gemar menghitung capaian, tetapi kering dari hidup. Di dalamnya, lorong-lorong bercahaya lampu LED tak pernah mengenal debu sawah atau aroma cat mural yang baru kering. Guru seni menyerahkan jam pelajaran demi “mata pelajaran inti”, seperti seorang penjaga hutan yang dipaksa menebang pohon-pohon rindang agar jalan aspal tampak lebih lurus. Musik dipinggirkan, olahraga dipangkas, dan pendidikan karakter—yang mestinya lahir dari teladan dan laku—dikurung dalam rubrik penilaian yang justru mematikan denyutnya. Seakan rasa bisa diringkas menjadi skor, seakan empati bisa diuji dengan pilihan ganda.
Ironi itu pahit: ketika anak-anak berhenti merasakan, mereka berhenti bertindak. Mereka duduk dengan tubuh yang semakin patuh tetapi jiwa yang semakin retak. Di papan tulis, keberhasilan didefinisikan sebagai kemampuan meniru; kreativitas dianggap penyimpangan kecil yang sebaiknya diluruskan. Sekolah, yang dulu diimpikan sebagai taman bagi tumbuhnya manusia, berubah menjadi jalur perakitan: cetak, nilai, naik kelas, lulus. Mesin sertifikasi yang sibuk menumpuk data tetapi lupa menyalakan nyala hidup.
Lihatlah bagaimana negara—dengan wajah serius dan retorika yang megah—merespons krisis moral dengan menambah jam pelajaran Pancasila. Seolah nilai lahir dari hafalan; seolah kejujuran tumbuh dari PowerPoint; seolah solidaritas bisa dicetak seperti modul bimbingan teknis. Pancasila kehilangan tubuhnya. Ia berdiri kaku di upacara hari Senin, sementara nadinya hilang di rapat-rapat birokrasi yang lebih sibuk memoles laporan daripada memulihkan luka publik.
Namun pendidikan sejati—yang merawat rasa dan memanggil tindakan—tidak pernah mati. Ia hanya berpindah, mencari ruang-ruang yang tak diakui negara. Ia hidup di bengkel kecil tempat anak muda belajar mengubah kayu bekas menjadi meja makan keluarga. Ia tumbuh di sanggar pinggir kota, di mana anak-anak menggambar mural tentang mimpi dan kemarahan mereka tanpa takut salah. Ia bernafas di ladang, ketika seorang petani muda menakar musim dengan tangannya sendiri, meraba tanah seperti meraba nadi ibunya.
Di tempat-tempat itu, pengetahuan tak lagi dingin. Ia punya tubuh. Ia punya suara. Ia punya nyawa yang menyapa. Anak-anak belajar bukan untuk nilai, tetapi untuk hidup—untuk meraba adil dan tidak adil, untuk mengenali dirinya sendiri, untuk memahami bahwa pengetahuan yang tidak dijalankan hanyalah bayangan.
Di situlah kita harus kembali bertanya: pendidikan seperti apa yang ingin kita wariskan? Pendidikan yang memahat manusia, atau sekadar memproduksi lulusan? Pendidikan yang menghidupkan, atau yang menumpulkan? Sebab manusia yang utuh tak cukup hanya mengerti. Ia harus merasakan. Ia harus melakukannya. Hanya di persilangan tiga jalan itulah, bangsa ini bisa kembali menemukan nadinya.
Ki Hadjar Dewantara pernah menanam tiga benih yang mestinya tumbuh menjadi pohon besar peradaban: ngerti, ngroso, nglaku. Di tangan beliau, tiga kata itu bukan jargon, bukan poster, bukan kutipan di ruang kepala sekolah. Ia adalah ritus menjadi manusia. Tapi kini, yang tersisa hanya ngerti—itu pun ngerti yang ringkih, yang kering, yang direduksi ke slide PowerPoint dan pilihan ganda. Pengetahuan tak lagi berdenyut sebagai pengalaman; ia berubah menjadi angka-angka yang harus dicapai sebelum rapat evaluasi triwulan.
Sementara itu, proses belajar sejati—yang selalu organik, selalu bergerak, selalu bersinggungan dengan hidup—perlahan membeku di tabel administrasi. Padahal belajar mengikuti ritme alamiah: mengalami, membaca, menulis, bicara. Anak belajar pertama-tama dengan meraba dunia: menyentuh tanah yang pecah oleh kemarau, mengamati perut ibu yang naik turun ketika tidur, mendengar desir angin yang membawa kabar dari gunung. Lalu membaca, bukan hanya buku, melainkan tanda-tanda yang terhampar luas: langit yang murung, pasar yang sepi, wajah tetangga yang berubah karena duka.
Menulis datang sebagai upaya menata segala yang berjejal di dada—keluh, tanya, dan temuan kecil yang menggetarkan. Dan bicara, akhirnya, menjadi kepulangan: menyampaikan kebenaran yang ditemukan melalui pengalaman. Siklus ini bukan administrasi; ia spiritual, ia internal, ia hidup.
Dalam dirinya laten siklus yang lain: bukti–cari–tegak–sebar. Bukti adalah tindakan yang membumi, cari adalah pencarian makna, tegak adalah keberanian menyatakan posisi, dan sebar adalah kemurahan hati untuk membagi kebenaran. Dua siklus ini—belajar dan kebenaran—hanya menyala jika dijaga oleh karakter yang tak bisa ditanam lewat lembar kerja: amanah, jujur, cerdas, peduli. Karakter adalah api, bukan kurikulum.
Namun sekolah hari ini perlahan kehilangan nyala itu. Ia menjadi pabrik sertifikasi, merakit tenaga kerja yang patuh tetapi tak mengenal dirinya sendiri. Guru, yang dahulu penuntun perjalanan batin, kini direduksi menjadi operator kurikulum. Seorang eksekutor silabus. Di ruang guru, keluhan yang sunyi sering terdengar: “Anak-anak sekarang sulit diatur.” Tapi mungkin masalahnya bukan pada anak-anak. Barangkali sekolahlah yang telah kehilangan relevansi, seperti jam tua yang berdetak tetapi tak lagi menunjukkan waktu yang benar.
Dunia berubah terlampau cepat: teknologi merayap ke segala arah, menggantikan guru sebagai sumber pengetahuan. Mesin pencari memberi jawaban sebelum seorang anak sempat bertanya. Di kelas, kurikulum masih terengah-engah mengejar abad ke-20, sementara murid telah hidup di wilayah tanpa peta, di mana identitas, kerja, dan masa depan terus dipertanyakan ulang setiap hari. Jika sekolah tak berani berubah, ia akan menjadi museum abad ke-21, tempat guru menjadi fosil yang masih mengajarkan cara membaca atlas di era ketika dunia sudah diproyeksikan dalam realitas virtual.
Ivan Illich pernah memperingatkan tentang perlunya deschooling society: membebaskan masyarakat dari mitos bahwa sekolah adalah satu-satunya pintu menuju pengetahuan. Sebab pengetahuan milik siapa saja yang berani mengalami dunia, membaca tanda-tandanya, menulis maknanya, dan berbicara tentang kebenaran hidupnya sendiri.
Pendidikan sejati adalah kegiatan spiritual: bukan ritual ujian nasional, melainkan doa panjang untuk memahami kehidupan. Ia lahir dari perjumpaan manusia dengan alam dan dirinya sendiri. Alam adalah kitab yang tak pernah selesai dibaca; Tuhan adalah esensi yang bersembunyi di balik setiap peristiwa kecil: embun yang menggantung enggan, daun yang jatuh tepat pada waktunya, langkah kaki yang menyisakan jejak di tanah basah.
Mungkin di masa depan, pendidikan tak lagi berwujud gedung dengan pagar tinggi dan seragam yang seragam. Ia menjadi jaringan-jaringan kecil pembelajar yang saling berbagi makna. Mereka berguru pada kehidupan, bukan pada sistem; pada pengalaman, bukan pada modul. Mereka membuktikan iman mereka lewat karya—karena belajar sejati selalu menuntut tindakan sebagai penjelasan terakhir.
Dan barangkali, suatu hari ketika dunia cukup sunyi untuk didengarkan kembali, kita akan sadar: sekolah hanyalah rumah singgah. Pendidikan sejati adalah perjalanan pulang menuju diri sendiri. Di sana, ngerti, ngroso, nglaku bukan konsep, bukan slogan, bukan kenangan dari pidato Ki Hadjar—melainkan cara kita bernafas. Cara kita hadir. Cara kita mencintai dunia, apa adanya.











