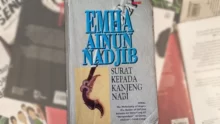Cannon dan Haji Tuyul:
Dialog di Surau Desa
Kita masih berada dalam struktur semacam itu — sementara yang dilakukan oleh “young generation” desa saya itu bukanlah gerak yang bertumbuh betul dari kesadaran akan dinamika inovatif atau paradigma kultur baru. Setidaknya di tempat rekreasi itu, di tempat pemandian, di gerumbul hutan kecil atau dalam gedung bioskop, mereka pasti merasakan suatu paradoks, terutama dalam konteks Idul Fitri itu.
Format tradisi yang berbeda itu juga memberi nilai yang berbeda. Persis, tapi dengan kadar yang berbeda, ketika saya menyempatkan diri berada di surau sepanjang malam selama beberapa hari sekitar Hari Raya.
“Bahwa Idul Fitri adalah suatu tonggak di mana setiap Muslim kembali jadi bayi; dan itu mesti diperjuangkan oleh masing-masing pribadi — masih belum merupakan tekanan yang sungguh-sungguh. Sebab itu, Idul Fitri belum lagi milik orang yang benar-benar kembali fitri, melainkan milik semua kaum Muslimin, siapa pun dan bagaimanapun kualitas kemuslimannya.”
Sudah makin sedikit kawan-kawan yang begadang di surau, sementara tema diskusinya pun sudah amat lain. Ini sebenarnya topik “klasik” baru nomor-nomor perubahan nilai dalam masyarakat kita. Tetapi, ia sendiri tidak akan berubah dengan seribu kali dibincangkan. Selalu terjumpa sela-sela lain dari masalah.
Saya dengar mereka mementaskan dalam benaknya Yenni Rachman dalam film Pahitnya Cinta Manisnya Dosa, yang diputar di bioskop Kecamatan Peterongan khusus hadiah Lebaran. ”Anunya Yenni tidak begitu besar” kata salah seorang, ”yang top itu punya Enny Haryono”. ”Tapi mbook mbok.. berani betul!” sahut lainnya, sambil berbaring di tikar di depan Imaman. Obrolan pun riuh, loncat dari bintang ke bintang.
Seseorang tiba-tiba terhenyak berdiri. ”Sekarang Bionic Woman filmnya!” katanya. Ia berjingkat, dan bersama teman lainnya ia berlari mendatangi TV tetangga. Malamnya film itu mereka review. Sampai jauh malam kemudian surau itu udaranya penuh dengan tokoh-tokoh film TV. ”Chase” yang dulu, ”Lucy” yang serba sedikit bisa juga bikin mereka tertawa, atau ”Cannon” si gemuk yang mereka bilang Jorono, itu pelawak ketoprak Siswo Budoyo dari Tulungagung, atau mirip juga dengan Edy Geol-nya Srimulat. Betapa modern sistem komunikasi zaman ini.
Si Kardu tukang angon kerbau itu, betapa pun tak punya kerangka referensi yang bisa dipakai untuk meng-“casting” Cannon dalam komputer otaknya, toh bisa nonton dengan asyik gambar hidup bikinan orang nun jauh di sana itu. Potret pertemuan antara dua dunia itu pasti adalah lukisan surealis terbesar yang dicapai abad ini.
Kurang tahu saya kenapa sekarang hampir tak ada lagi sastrawan surau yang ber-“story telling” sambil tiduran di gelap surau. Yang mendongeng tentang lakon-lakon konvensional ”Ande Ande Lumut”, ”Joko Kendil” atau ”Kinjeng Dom”, atau yang agak inkonvensional seperti ”Kasan Kusen” yang bukan Hasan Husen-nya Sayyidina Ali yang dibantai di Padang Karbala. ”Tak Bedondang”. ”Ontang-ontange Kali Gede” dan lain-lain yang mereka ciptakan sendiri. Yang mereka ’wayangkan’ sedemikian hidupnya sehingga sampai sekarang masih tetap tajam potretnya di benak saya. Lebih hidup dibanding Ophelia yang sinting atau Utay-nya Motinggo Boesye.
“Keindahan hidup itu terletak di alam batin, tidak di wajah seseorang, gemerlap, atau tumpukan ratna manikamnya.”
Dongeng-dongeng itu menjadi performen imajinatif. Menancapkan moralitas, sikap, orientasi hidup, percontohan-percontohan luhur yang konkret dibutuhkan oleh alam batin manusia, di ruang mana pun dan di waktu kapan pun. Joko Kendil yang implisit memberitahukan bahwa keindahan hidup itu terletak di alam batin, tidak di wajah seseorang, gemerlap, atau tumpukan ratna manikamnya. Ontang-anting Kali Gede yang menandaskan betapa kejahatan bersifat amat sementara. Kasan Kusen yang tegar kukuh tak tergoyahkan oleh badai atau keputusasaan apa pun. Alangkah sayang, estafet kesastrawanan surau seperti terputus. Idola-idola baru muncul: Roy Marten, Yenni Rachman, John Travolta, Six Million Dollar’s Man, yang substansi ketokohannya lebih terkait dengan kulit hidup yang glamor.
Inilah romantisme! Rasa sentimental terhadap sejarah masa silam. Terhadap nostalgia yang kosong. Marilah dikubur itu waktu yang telah lewat. Tetapi keluhurannya dan suara kemuliaan hidup tidak pernah bisa dikuburkan. Dongeng-dongeng bersambung tiap malam, yang sekarang tiba-tiba saya takjub bagaimana kakang-kakang itu mampu menciptakannya dan mampu mengisahkannya dengan begitu mencengangkan. Generasi terbaru sebaya saya ini kok amat jarang yang bisa berbuat seperti itu lagi. Waktu pulang ke desa itu saya agak panik: apakah ada yang hilang dari saya?
Tetapi, sudah barang tentu saya tak mau terkotak oleh soal dongeng itu belaka. Pertanyaan saya itu kemudian berkembang lebih secara subjektif. Saya mendadak cemas akan apa yang selama ini saya kerjakan serta teman-teman saya kerjakan? Apakah ada yang tak terolah dalam jiwa generasi saya? Apakah ada suatu perkembangan cara berpikir, cara bersikap, cara mengeksplor dunia batin, cara memahami dan menggunakan jaringan otak, cara mengoordinasi sekian aspek psikologis, cara mengaksentuasi masing-masing potensinya adaptatif dengan dunia eksternal seseorang; atau adakah semacam ketimangan dalam menggunakan, mendaya-upayakan keseluruhan potensi psikologis, yang mungkin disebabkan oleh suatu era kebudayaan baru, pendidikan baru, kecenderungan hidup baru, dalam masyarakat kita selama ini? Apakah ada bagian dari komputer batin kita yang macet atau justru over-active, atau dimacetkan, dimanjakan, sementara bagian lain yang hendak dibangkitkan belum juga menyala? Apakah ada pola kreatif tipe manusia masyarakat kita, sebutlah tipe Jawa, Batak, Bugis, atau katakanlah Indonesia, yang mulai dipadamkan sehingga gerak kreatif kita cenderung terbantu, atau minimal tidak bekerja secara prima?
Saya bingung sendiri, karena hanya karena soal dongeng saja mendadak timbul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tetapi, satu hal yang saya tahu persis: bahwa dongeng sebagai salah satu motor penanaman nilai hidup yang paling efektif, kini mulai macet. Bukan hanya karena subjeknya barangkali yang menipis, tetapi juga karena perubahan wadah dan mekanisme budaya yang terjadi. Sementara itu hook kiri Bionic Woman, Si Jaime Sommers yang simpatik itu, masuk ke tulang iga kita, ditampung oleh serudukan kepala Cannon: si Kasdu knocked down.
***
Sore hari, di gardu, sebelum main balbalan yang musiman di desa saya, orang sibuk ngobrol soal Haji Tuyul dan Haji Gatel. Haji Gatel ialah orang yang berpenyakit gatal kulit tak sembuh-sembuh dengan sekian dokter, lantas disarankan oleh seseorang dukun untuk naik Haji. Ia laksanakan, dan sembuhlah ia. Kalau Haji Tuyul, ialah orang yang naik Haji dengan biaya yang ia peroleh karena mempekerjakan seorang tuyul.
Takhayul? Khurafat? Tak Masuk Akal? Kepercayaan sesat? Tetapi itulah lakon hangat di desa saya. Orang makin kaya di sana, meskipun tak sedikit yang tetap atau bahkan makin miskin. Perlombaan rumah gedong model kota makin mencolok. Ditempuh dengan pelbagai cara. Ada yang pakai ilmu wiraswasta murni, ada yang pakai perusahaan tuyul.
Si Ksl itu sekarang sudah punya rumah tingkat dan mobil mewah di ibu kota Jawa Timur, berkat keterampilannya sebagai bos Martabak, sementara 30-an warga desa lainnya mulai menanjak dan mulai bikin rumah baru di desa. Si Tsm jadi sopir bis umum sambil tanam saham di unit prostitusi yang diusahakan oleh Arf yang juga sudah mulai memugar rumahnya dan punya Colt Station. ”Jangan sewa Colt dia, itu uang haram!” berkata Pak Haji Slm yang fanatik.
Sementara di jalur Pedukuhan SMP desa lebih dari 25 persen orang memelihara tuyul. Kok tahu? Inilah memang kadar kebenaran “pers desa”. Secara ilmiah-faktual memang sangat bisa diragukan. ”Tapi saya melihat Mbok Isn itu sedang menyusui dua tuyul di siang hari bolong!” kisah seseorang. Boleh percaya boleh tidak. Tetapi sang disiplin ilmu bisa juga menganalisis perbandingan absurd antara mata kerja penduduk itu dengan kuantitas penghasilannya. Absurditas itulah yang memberi peluang bagi kemungkinan adanya tuyul.
Apakah Anda pribadi yakin bahwa perihal tuyul itu hanya isapan jempol belaka? Tetapi, di perut gadis Chmt itu dulu ngendon sebuah keranjang hasil karya pemuda yang ditolak cintanya sehingga melakukan santet — semata-mata adalah sesuatu yang gampang masuk akal bagi penduduk desa saya.
***
Sementara pada Hari Raya ini desa saya mencatat suatu peristiwa “politik”. Orang desa tak kompak lagi. Yang ini sembahyang di lapangan sepak bola (dari sembilan kali salat Ied, delapan kali Nabi Muhammad shalat di lapangan), lainnya tetap di masjid (”wong ada masjid kok pakai lapangan, masjid kan baitullah”). Memangnya semua harus kompak di masjid atau di lapangan? Apakah harus begitu persatuan dan ukhuwah islamiyah itu diwujudkan?
”Itu hak setiap orang untuk memilih,” kata salah seorang. ”Itu risiko demokrasi,” sahut lainnya. Tetapi ada juga yang menganalisis secara politis, ”kini perpecahan antara golongan Islam mulai lagi,” katanya. ”Di DPR pusat memang sudah dimulai perpecahan itu, tapi seharusnya pimpinan di daerah mesti punya kebijaksanaan untuk tidak usah menyeret orang-orang desa yang tak ngerti apa-apa…”.
Apakah suhu udara Pemilu mulai berhembus? Ah, nasibmu wahai kelinci-kelinci. Belalai sang Gajah mulai bergerak-gerak.
Wallahua’lam bissawab. Hanya Tuhan yang tahu persis. Tetapi hampir semua gerak irama permasalahan desa yang terurai tadi, tidak bersumber dari diri desa sendiri, melainkan berasal dari atas.