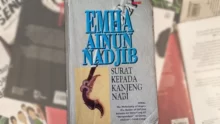Berburu Manusia di Provinsi Ekonomi

Pada suatu dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB, di tengah jalan Yogya selatan, kaki kanan saya mendadak mengalihkan dirinya dari gas ke rem. Jeep ‘perang’ saya terhenti dengan suara berkerenyit. Saya matikan mesin dan bergegas turun, menghampiri sejumlah orang — kebanyakan perempuan — yang berkerumun di tepi jalan.
Mereka sedang mengurusi salah satu Ibu (Simbok) anggota ‘rombongan’ mereka sendiri yang — katanya — kambuh darah tingginya. Wallâhu a’lam, saya tidak mengerti, tetapi Ibu itu memang setengah pingsan, berkerjat-kerjat tubuhnya, bergelepotan keringat, dan tampak sangat sengsara.
Singkat cerita, Jeep ‘perang’ segera mengangkutnya ke rumah seorang dokter terdekat — di desa Kasihan — membangunkan beliau dan memasrahkan si sakit kepada kearifan kemanusiaan dan kesanggupan kedokterannya.
Tentulah Anda pernah membaca puisi penyair Hartojo Andangdjaja yang berjudul “Perempuan-perempuan Perkasa”. Persis. Ibu-ibu inilah yang ia kisahkan. Ibu-Ibu pahlawan kita semua, dari wilayah jauh di selatan Yogya, sejak memasuki tengah malam berangkat menyerbu kota dengan sepeda-sepeda dan rengkek-rengkek pengangkut barang jualan mereka. Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Legi Patangpuluhan serta satu dua tempat lain merupakan tujuan meraka mencari nafkah. Sepuluh sampai lima belas jam mereka habiskan waktu untuk memperoleh laba seribu dua ribu rupiah.
Saya kira kita bersikap unfair kepada golongan masyarakat semacam ini. Saya kira pembangunan, yang kini sudah memasuki tahap jangka panjang kedua ini, bertindak kurang sopan kepada sebagian — tidak sedikit — Ibu-Ibunya sendiri. Saya kira, kita-kita kaum terpelajar di kota, kita para pemimpin kemajuan, terlalu banyak cakap. Segitu-segitulah tingkat ketidaksejahteraan mereka di zaman sebelum perang, di zaman sedang dan pasca perang, dan segitu-gitu jugalah ‘omset penderitaan’ mereka di zaman Orla dan Orba hari ini. Saya kira, seluruh gerak sejarah yang melalui mulut kita selalu mengumumkan ‘Development! Development!’ ini — telah berlaku kurang etis, kurang bermoral dan kurang tahu malu kepada Simbok-Simbok itu.
Mungkin saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di wajah mereka yang membisu:
“Ibu, tunggulah barang sebentar putra-putra Ibu sedang merundingkan kejelasan arah ekonomi kita. Pasti kita tidak ke kiri dengan alasan-alasan non-ekonomi yang bertumpuk-tumpuk. Kita pun ogah disebut sedang bergerak ke kanan, juga dengan alibi-alibi yang berasal dari kebudayaan, agama, psikologi, serta sejumlah romantisasi nasionalisme. Tunggulah, putra-putri Ibu sedang memperdebatkan jalan tengah. Ibu pernah mendengar Ekonomi Pancasila, bukan? Terhadap segala tagihan sejarah dari pancaran mata Ibu-Ibu, jawabannya belum, bukannya tidak. Bersabarlah, Bu.”
“Ini soal makro struktural, Ibu-Ibu. Kalau pada suatu siang dapur Ibu tidak berasap, jawabannya bukanlah beras. Melainkan — kami memohon kearifan Ibu-Ibu: tunggulah kami sedang memproses perubahan-perubahan besar, mendasar, struktural, sistemik, mungkin evolusioner, mungkin sedikit revolusioner untuk satu dua hal. Ibu-Ibu, nanti kita akan segera take off. Saksikan dan restuilah dari jauh, suatu kelompok dari anak-anak Ibu sedang menjajaki apakah tim masinis ekonomi nasional yang baru ini akan cukup punya kelapangan dan kekuatan untuk membuat keseluruhan perekonomian bangsa kita ini menjadi lebih Islami. Apakah niatan untuk memproses dekonglomeratisasi, untuk mengupayakan devalidasi korporasi antara birokrasi dengan kekuatan-kekuatan kuning, bisa jalan. Segala sesuatunya masih ‘belum’, Ibu: juga kalau Ibu berbicara tentang — umpamanya — ‘monopoli kok sampai segitu!’, ekstrem kesenjangan kaya-miskin, atau praktik keserakahan yang semakin jamak dan dianggap lumrah. Hidup ini ‘koma’. Janganlah Ibu terlibat dalam kecemburuan sosial….”
Tetapi yang menjadi permasalahan adalah yang kita temukan dalam realitas: ekonomi is ekonomi! There is nothing to do with etika, moralitas, social fairness, bahkan pun akidah-akidah keagamaan.
Ekonomi, ekonomisasi dan — pada akhirnya — ekonomisme, bukanlah human being activities. Melainkan pertarungan di antara laba dan rugi. Melainkan kemerdekaan untuk menumpuk dan untuk serakah. Kebebasan dan kenikmatan untuk mengeksplorasi modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahawa Jawanya: enake wudele dhewe.
Dan itu bukan kegiatan makhluk yang bernama manusia. Sebab tanda seseorang itu manusia adalah nurani dan keberbudayaan, atau lebih tepatnya: keberadaban. Keberadaban adalah kebenaran, kebaikan dan keindahan yang bermuara pada kesepadanan atau keadilan sosial. Maka tidak ada cultural animal, yang ada adalah economic animal dan political animal.
Baiklah, para pejalan ekonomi tentu adalah manusia. Namun dalam konteks itu, yang dijalankan tidaklah terlalu indikatif terhadap kemanusiaan.
Kalau seorang pengusaha menyelenggarakan santunan sosial, kalau seorang konglomerat tersentuh nuraninya untuk berbagi, kalau seorang pemanggul kekayaan terketuk perasaannya untuk berkeadilan sosial — maka yang santun, yang terketuk dan yang tersentuh bukanlah kepengusahaan atau kekonglomeratannya, melainkan manusianya. Ada dinding batas yang jelas antara kepengusahaan dengan kemanusiaan: ekonomi itu sendiri steril dari tanda-tanda kemanusiaan, kebersamaan sosial, kesantunan dan kasih sayang. Apakah di supermarket diperlukan Divisi Detektors yang menilai tingkat-tingkat kemampuan ekonomi para calon pembeli? Agar kepada mereka bisa dikenakan harga yang berbeda-beda? Apakah persaingan tender-tender didasarkan pada penilaian terhadap setting sosial masing-masing kelompok, kemudian dirundingkan bahwa yang akan memperoleh previlese adalah kelompok yang paling strategis untuk kesejahteraan makro?
Ingatan saya kembali ke kisah lama. Penjual Jagung bakar asal Madura itu menjawab pertanyaan calon pembelinya: “Harganya satu 100 rupiah, Pak. Kalau 125 rupiah, Sampeyan rugi. Kalau 75 rupiah, saya yang rugi. Harga 100 ini sudah Islam, Pak. Lha kalau Bapak Cuma punya uang 50 rupiah, ‘dak pa-apa silakan ambil satu. Tapi harganya tetap 100 rupiah…”
“Lho gimana sih?” si calon pembeli tak mengerti.
“Yang 50 rupiah kekurangannya, itu laba saya di akhirat takiye!” jawab si Madura.
Ini jelas bukan sosialisme model mana pun dari Albania sampai Kuba, bukan pula kapitalisme jenis apa pun, tapi ekonomi Pancasila juga tidak demikian.
Sebab, yang kita kenal: ekonomi, bisnis, itu hukum besi. Ekonomisme itu sebuah dunia absurd bagi manusia: naiklah bus, bawa uang maka Anda sampai ke tujuan. Naik bus, tak bawa uang maka Anda diturunkan di tengah jalan. Naikkan uang ke bus maka uang tak akan dibuang.
Absurd. Karena dari kisah bus ini tak bisa juga kita ambil kesimpulan bahwa harga manusia jauh lebih rendah dibanding uang naik bus.
Sangat tidak gampang menemukan manusia di Provinsi Ekonomi. Dan semakin hari semakin tidak gampang. Sehingga bengong juga tatkala mendengar Allah menggambarkan sebagian makhluk-Nya: “Alladzîna yasytarûnallâha bitsamanin qalîl”… mereka yang membeli Allah dengan harga yang murah….
(Diambil dari buku Emha Ainun Nadjib, OPLëS, Mizan, 1995)