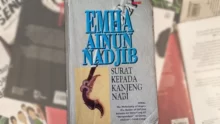Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, atau ‘Alikah Engkau?

Aku pernah bertutur tentang ingat kepada Allah di segenap ruang dan waktu yang kita libati. Aku ingat para sahabat sering bertanya, apakah Allah itu bagi kita merupakan hal yang mewah ataukah bersifat sehari-hari?
Kalau materi, ia disebut mewah jika sukar didapat, dan jika kita mendapatkannya selalu merasa sangat nikmat. Sedangkan barang yang sifatnya sehari-hari, yang bersifat “biasa”—itu gampang didapatkan dan rasa mempe-rolehnya juga tidak istimewa.
Di sinilah letak keagungan dan keindahan Allah. Ia bukan “barang” mewah, karena kapan saja kita bisa menghadap-Nya dan “memperoleh”-Nya. Namun, jika kita ber-muwajjahah dengan-Nya; jika kita memperoleh kehadiran-Nya—pasti terasa sangat mewah dan istimewa. Artinya, kapan saja dan di mana saja kita bisa bejumpa dengan Allah, tapi Ia tetap mewah.
Kuingat juga sahabatku, Wahyu Sulaiman Rendra—tatkala ia bersyahadat dan masuk Islam di Parangtritis Yogya—ia merasa begitu takjub. “Alangkah dekatnya seorang muslim dengan Allah. Kapan saja ia bisa menemui-Nya, tanpa birokrasi yang ruwet. Alangkah demokratisnya Islam. Setiap hamba Allah bisa —dalam waktu beberapa detik saja—menjadi muslim, karena langsung bersaksi di hadapan-Nya tanpa melalui perantara siapa pun atau apa pun saja. Islam mengantarkan setiap manusia untuk langsung berhadapan dengan Allah!”
***
Seorang aku bertanya kepada masing-masing kamu. Aku mengetuk pintu perenungan batinmu, karena mungkin pagi ini, siang itu, sore itu, sedang beri’tikaf. Maksudku dengan beri’tikaf tidaklah harus dalam keadaan bersila atau bersujud di atas tikar atau karpet masjid.
Engkau bisa beri’tikaf sewaktu-waktu. Bisa lima jam, bisa satu jam, bisa beberapa menit, bisa beberapa detik, dan nanti engkau ulangi lagi beberapa detik. I’tikafmu juga bisa tak dibatasi oleh di mana engkau sedang berada atau apa yang sedang engkau kerjakan.
Mungkin engkau sedang duduk termenung dalam taksimu karena menunggu penumpang yang akan memanggil jasamu. Mungkin engkau sedang meladeni pembeli di tokomu. Mungkin engkau bekerja di kantormu. Mungkin engkau sedang berjalan di trotoar atau duduk-duduk menunggu bus kota di tepi jalan. Dalam semua keadaan itu batinmu bisa saja beri’tikaf, jiwamu merenung, pikiranmu terkonsentrasi kedalamannya kepada Allah.
Engkau bisa tapa ngrame. Aku sendiri melakukannya tiap hari. Aku bekerja keras tiap saat, aku selalu dalam suasana perjalanan hampir tiap hari, aku selalu berada di tengah orang banyak hampir kapan saja. Bahkan ketika mengetik itupun berseliweran banyak orang di sekitarku. Tapi hatiku tetap bersedekap.
Jiwaku selalu merenung. Pikiranku insya-Allah selalu bersujud. Perasaanku selalu masuk ke relung-relung kedalaman nilai. Bahkan, tatkala engkau melihatku bergurau dan mungkin berteriak-teriak, engkau jangan lupa bahwa sesungguhnya jauh di dalam diriku aku bersila dan memejamkan mata.
***
Aku bertanya kepadamu bagaimana sifat pertemuan atau watak kesadaran dan ke-ingatanmu kepada Allah. Kapankah, pada situasi bagaimanakah, karena apakah, serta terdorong oleh apakah engkau menemukan Allahmu?
Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq, sebagai contoh, adalah jenis manusia kultural-moderat. Pola penghayatan keilahiannya biasa-biasa saja. Ia menjalani hidup dengan irama penuh kewajaran, ia memikirkannya, merasakannya, sampai akhirnya, ia menemukan inti nilai dan berjumpa dengan Allah dalam pengalaman-pengalamannya. Sayyidina ‘Umar Bin Khattab adalah manusia revolusioner-radikal. Ia tidak melalui proses dan irama penghayatan yang “wajar”. Merasuknya setiap ketersentuhan dan kesadaran nilai pada dirinya berlangsung radikal dan revolosioner. Ia mengalami dunia, maka ia menemukan Allah.
Sementara Sayyidina ‘Ali Ibn Abi Thalib adalah manusia mistis. Kalau Abu Bakar menghayati dunia dulu baru menemukan Allah, kalau ‘Umar menghayati dunia dan langsung menemukan Allah, maka ‘Ali tidak melihat dunia. ‘Ali sama sekali tidak melihat dunia, karena begitu ia menatap dunia, yang tampak di mata batinnya adalah Allah Swt.
‘Ali menatap langit, tampak Allah di mata batinnya. ‘Ali menyaksikan riuh rendah pasar, tampak Allah di mata batinnya. ‘Ali memandangi gelombang laut, dedaunan yang bergoyang oleh angin, manusia lalu-lalang di jalanan, burung-burung terbang, cacing melata dan kuda kuda berlarian —maka di mata batinnya yang tampak oleh ‘Ali adalah Allah. Bagaimana proses-proses pergaulan dan pertemuanmu dengan-Nya? Adapun Sayyidina ‘Utsman Ibn ‘Affan, meletakkan dunia di tangan kirinya, dan meletakkan Tuhan ditangan kanannya. Artinya, berpedoman kepada Allah dengan segala perintah dan larangan-Nya, ‘Utsman memerintah dunia, memanajemen kehidupan dan pengendalian sejarah di muka bumi.
Kita-kita ini, ada kemungkinan memiliki kecenderungan seperti Sayyidina ‘Utsman, tetapi dalam pola manajemen yang terbalik. Yakni, dunia kita genggam di tangan kanan, artinya kita utamakan. Lantas Tuhan kita genggam di tangan kiri kita, artinya kita pakai sebagai alat untuk kepentingan dunia kita.
Kita hidup, mencari nafkah, menjalani karier, mengejar martabat sosial dan kekayaan. Dan untuk semua itu Tuhan kita posisikan sebagai asset kemajuan dan sukses keduniaan kita. Kita dapuk ia sebagai pihak yang kita harapkan bisa mempermudah jalannya kejayaan kita. Kita pojokkan Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita yang umumnya berhubungan hanya dengan kehidupan pribadi kita di dunia. Bahkan kita pasang Tuhan sebagai alat politik, sebagai maskot suatu strategi sosialisasi dan mobilisasi, atau sebagai bagian penting dari merek dagang komoditas perusahaan kita.
Atau mungkin kehinaan kita tidak sejauh itu. Allah sekadar kita acuhkan. Kita nomorduakan. Tidak kita anggap penting. Tidak kita perlakukan sebagai sumber maha sumber dan tujuan maha tujuan segala sesuatu dalam hidup kita. Diam-diam kita bergumam tentang Tuhan: “Emangnya gua pikirin!” Sehingga kita jalankan apa saja, kita bangun apa saja, kita ekspansikan apa saja, kita putar roda kapitalisme, industrialisme, hedonisme, dan sebagainya dengan tidak usah mempertimbangkan eksistensi Tuhan.
Hanya saja, nanti kalau ada gejala bangkrut, ada kemungkinan kekuasaan kita terdesak oleh kekuatan lawan—baru Tuhan kita pindahkan ke genggaman tangan kanan. Mendadak kita jadi religius, bergaya saleh, rajin pariwisata ke tanah suci, ikut grup tarikat, atau tiba-tiba sangat peka terhadap nasib orang miskin, anak yatim dan kaum yang menderita.
Tetapi aja dumeh, karena gejala terakhir itu bisa jadi merupakan suatu jalan yang baik bagi proses pertobatan manusia yang bernama khusnul khatimah. Itulah sebabnya, aku senantiasa berdoa agar para pemimpin negeri ini dimurahi oleh Allah dengan anugerah khusnul-khatimah.[]
**Diambil dari buku “Tuhan Pun ‘Berpuasa’”, diterbitkan oleh penerbit Zaituna, 1997