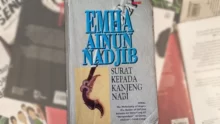A Man of Nothing to Lose

Keberlangsungan suatu institusi negara bisa terlalu terbiasa atau tergantung hanya pada metabolisme kekuatan-kekuasaan-kemenangan (bukan kepemimpinan-kebersamaan-keberimbangan) antar-kelompok. Itu pun dalam pengertian yang setelanjang-telanjangnya.
Di puncaknya, jika saat pergantian kekuasaan tiba, pergulatan yang terjadi tidak ada urusannya dengan gagasan-gagasan tentang perbaikan, dengan paradigma nilai-nilai, dengan ideologi atau kehendak-kehendak kemanusiaan luhur lainnya. Melainkan hanya berurusan semata-mata dan semena-mena dengan perebutan kekuasaan itu sendiri.
Maka, bisa jadi, pada suatu hari rakyatnya akan pusing tujuh keliling karena terpojok untuk terpaksa menentukan salah satu di antara dua ‘makhluk’ yang sama-sama belum tentu mereka kehendaki. Katakanlah misalnya: singa ataukah harimau.
Mungkin telah berpuluh tahun mereka memimpikan singa turun tahta. Tapi akhirnya datang suatu keadaan dan momentum di mana mau tak mau harus mempertahankan sang singa, sekadar supaya harimau — yang dianggapnya lebih berbahaya — tidak berkuasa.
Terserah bagaimana detail konstelasinya. Tapi satu hal yang jelas. Alangkah getir nasib manusia. Alangkah getir nasib rakyat semacam itu. Atau agar sepadan dengan metafor singa dan harimau: alangkah getir nasib kambing-kambing, pelanduk-pelanduk.
Singa tidak mau, atau pada saatnya, tidak berani, turun tahta. Dan selama itu ia tidak punya waktu sedetik pun untuk sekadar membayangkan — apalagi mempersiapkan — ‘wujud kehidupan’-nya jika tak berkuasa.
Sementara si harimau, atau potensi-potensi raja hutan lainnya try to get a power. Dengan cara merekayasa diri atau direkayasa oleh sejumlah elite kekuasaan sejarah lainnya yang bertentangan terhadap kedudukannya. Kepentingan itu mungkin didorong oleh kemungkinan sejumlah konsesi, atau bisa juga untuk justru menjadikan si harimau sebagai boneka yang digerak-gerakkan atau dibeo-beokan.
Sungguh betapa getir nasib manusia. Betapa getir nasib masyarakat hewan di hutan belantara. Juga betapa kelam nasib sang singa, si harimau, para dalang. Karena, sekali lagi, kepentingan di balik rekayasa itu tak bersentuhan dengan nilai-nilai “normal” kemanusiaan dan kebersamaan hidup. Tak bersentuhan dengan segala keluhuran yang tiap saat disebut-sebut: kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, idealisme, ideologi, cita-cita kebudayaan dan peradaban yang telah dikenal oleh manusia sebagai nilai-nilai purba.
Alangkah getir nasib manusia. Dipenjarakan oleh diri mereka sendiri. Oleh pelanggaran-pelanggaran atas sumber keselamatan mereka sendiri dari zaman ke zaman. Atas nilai-nilai yang telah mereka kenali sejak kurun sejarah yang paling dini.
Alangkah getir nasib manusia. Mungkin mereka sekadar menanti apakah singa akan bertahan ataukah harimau akan menang. Mungkin juga badan mereka akan terkena cipratan darah bertarung atau sebagian mereka harus terluka oleh cakaran kuku-kuku. Bahkan bukan tak mungkin mereka harus terpaksa ikut mencakar dan dicakar.
Dan ketika seorang manusia terkapar, mungkin muncul di benaknya: betapa masa silam terasa justru merupakan masa depan yang amat jauh tak terjangkau. Betapa Pendito Ratu di zaman kuno itu, ternyata, sungguh-sungguh pernah ada. Betapa kemajuan kekuasaan dari abad ke abad justru menempatkan realitas masa silam tentang Pendito Ratu itu menjadi cakrawala utopis di waktu mendatang yang seolah tak akan pernah bisa disentuh. Betapa kemajuan yang demikian pesat ini justru membawa manusia jauh melompat ke masa silam, yang toh juga tak kunjung bisa dicapai.
Seorang Pendito Ratu, adalah raja yang mengerti kapan harinya telah tiba untuk undur diri dari kekuasaan. Ia beringsut ‘masuk hutan’, menyelam, mengendap ke dalam dirinya sendiri, ke dalam hakikat kemenangan hidup yang sejati. Ia menjadi ‘orang tua’ yang memenjarakan diri secara ikhlas di dalam sel nilai kehidupan yang paling bersahaja: bahwa kemenangan yang benar-benar kemenangan tidaklah terjadi pada seseorang atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri.
Raja-raja modern pada umumnya adalah raja yang kuat kukuh atas banyak orang, tetapi sangat lembek lemah di bawah cengkeraman dirinya sendiri. Ia melakukan hal-hal yang semakin lama semakin membuatnya terancam. Ia menumpuk sesuatu yang kelak menimbuninya dengan ketidakamanan. Ia menghimpun apa saja yang akan menjadi bumerang. Serta menabung segala sesuatu yang pada akhirnya mengancam dirinya sendiri. Ia adalah manusia kalah.
Ia tak berani beranjak dari kursinya. Sedumuk bathuk harga diri dan kemerdekaan rakyatnya yang ia rampas, menjelma menjadi anak panah yang dekat mengarah ke jantungnya. Senyari bumi yang ia curi dari pemilikan rakyatnya adalah api yang siap menjilat dari alas kaki singgasananya. Ia takut mengangkat pantatnya dari singgasana, karena setiap butir kezaliman, ketidakadilan, dan kekejaman menjadi jari jemari malaikat pencabut nyawanya.
Kalau kita seorang maling, tak ada kans kita untuk menjadi Pendito Ratu. Sebab Pendito Ratu adalah pemimpin yang sanggup ber-sabda bukan hanya pada rakyat, tapi juga terutama kepada dirinya sendiri. Sejak hari pertama berkuasa, ia telah menyiapkan diri untuk tidak berkuasa. Pemimpin yang terbaik adalah yang paling memiliki penguasaan diri untuk dipimpin. Maka seorang Pendito Ratu haruslah a man of nothing to lose. Tak khawatir kehilangan apa-apa. Jangankan harta benda, simpanan uang, seribu perusahaan, tanah, gunung dan tambang. Sedangkan dirinya sendiri pun sudah tak dimilikinya, sebab telah diberikan kepada Tuhan dan rakyatnya.
Dalam khazanah agama, itu disebut konsep zuhud. Pelaksananya bernama zâhid. Seseorang yang mampu memerdekakan diri dari pemilikan yang semu atas hal-hal yang juga semu. Seseorang yang bukan hanya berhasil merebut kemerdekaan atau keselamatan hidup, tapi bahkan direbut dan diperebutkan oleh segala jenis makhluk Tuhan yang bernama kemerdekaan dan keselamatan sejati.
Tampaknya manusia harus terlebih dahulu hancur lebur dirinya dan menghancurleburkan orang banyak untuk tiba di medan tasawuf, yang berpuluh-puluh tahun disangkanya barang mewah. Padahal tasawuf adalah milik sehari-hari, yang berharga bagi para alim maupun maling.
Betapa naif dan utopis ini semua, namun tunggu dan saksikan, betapa nyata di depan hidung kita.