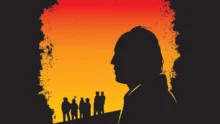Kapitayan: Jejak Spiritualitas Jawa Kuno dan Kritik atas Modernitas Barat

Secara etimologis, “Kapitayan” berasal dari akar kata dalam bahasa Jawa kuno: “Taya” berarti ketiadaan atau yang tidak tampak, tidak berbentuk, tidak terbayangkan. Ini merujuk pada konsep ketuhanan dalam Kapitayan, yakni Sang Hyang Taya, Tuhan yang Maha Ada justru karena melampaui semua bentuk keberadaan yang bisa dipersepsi oleh pancaindra. Awalan “Ka-“ dan akhiran “-an” dalam bahasa Jawa menunjukkan suatu keadaan atau sistem. Jadi, “Kapitayan” secara bahasa berarti sistem kepercayaan atau keadaan spiritual yang berporos pada konsep Sang Hyang Taya — Tuhan yang tak terlukiskan namun diyakini sebagai sumber dari segala yang ada — Kapitayan bisa diartikan sebagai ajaran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa bentuk, yang mendasari cara hidup dan pandangan dunia masyarakat Jawa kuno secara spiritual dan filosofis.
Kapitayan adalah suatu sistem kepercayaan atau agama asli masyarakat Jawa kuno yang diperkirakan telah ada sejak zaman batu, bahkan lebih dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Kepercayaan ini berkembang jauh sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, maupun Kristen ke Nusantara. Kapitayan mencerminkan spiritualitas tinggi masyarakat Jawa kuno yang sudah memiliki konsep ketuhanan yang monoteistik, bahkan beberapa praktik ibadahnya diyakini mirip dengan shalat dalam Islam.
Dalam Kapitayan, Tuhan disebut sebagai Sang Hyang Taya — suatu entitas yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan bentuknya, dan melampaui segala pencitraan. Kata “Taya” berarti “ketiadaan”, yang justru dimaknai sebagai eksistensi paling sejati — sebuah konsep yang sangat mendalam dan abstrak, sejajar dengan pengertian Tuhan dalam banyak teologi tingkat tinggi.
Beberapa ciri khas Kapitayan meliputi: Dalam ajaran Kapitayan, pemujaan kepada Tuhan dilakukan tanpa perantara simbol atau patung. Tuhan dipahami sebagai Sang Hyang Taya, suatu entitas transenden yang tak terbayangkan, tak terlukiskan, namun justru karena itulah menjadi sumber dari segala yang ada. Tempat beribadah dalam tradisi ini disebut Sanggar atau Padepokan, ruang hening untuk menyepi dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Gaib. Menariknya, arah sembahyang dilakukan menghadap ke timur—ke arah matahari terbit—yang dimaknai sebagai lambang pencerahan dan asal kehidupan.
Praktik spiritual Kapitayan sangat menekankan pendalaman batin dan penyucian diri melalui tiga jalan utama: sembah, yaitu doa dan meditasi; tapa, yakni menjalani hidup dalam laku prihatin dan pengendalian diri; serta samadi, yang merupakan bentuk kontemplasi mendalam untuk menyatu dengan kesadaran semesta. Laku-laku ini bukan sekadar ritual, tetapi jalan untuk memahami hakekat kehidupan dan menumbuhkan kejernihan batin.
Pandangan hidup dalam Kapitayan bersifat holistik, memandang manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Prinsip hamemayu hayuning bawana — menjaga dan merawat keindahan serta keseimbangan dunia — menjadi landasan etis dalam bersikap terhadap lingkungan dan sesama. Harmoni bukan tujuan akhir, melainkan jalan hidup sehari-hari.
Secara filosofis, ajaran ini menempatkan manusia dalam relasi batin yang intim dengan Tuhan melalui konsep manunggaling kawula lan Gusti, yakni penyatuan antara makhluk dan Sang Pencipta. Bagi orang Jawa kuno, Tuhan tidak jauh, tidak asing, tetapi hadir dalam setiap hembusan napas dan gerak laku. Bersamaan dengan itu, konsep sangkan paraning dumadi menjadi perenungan yang terus hidup — tentang dari mana manusia berasal, dan ke mana sesungguhnya ia akan kembali.
Dalam memahami kebudayaan Jawa secara mendalam, kita tidak bisa hanya berhenti pada warisan Hindu-Buddha, Islam, atau bahkan Kristen yang datang belakangan. Jauh sebelum semua itu hadir, bangsa Jawa telah mengenal sebuah sistem spiritual yang mapan, yang dikenal dengan nama Kapitayan. Ajaran asli Jawa ini diyakini telah lahir sejak zaman batu, lebih dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Keberadaan Kapitayan menunjukkan bahwa konsep Ketuhanan masyarakat Jawa purba telah mencapai tingkat kematangan yang luar biasa — tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi sebagai landasan hidup yang menyeluruh.
Menariknya, beberapa ajaran Kapitayan memiliki kemiripan mencolok dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal keesaan Tuhan (Tunggal), praktik sembahyang, dan laku spiritual. Hal ini menandakan bahwa spiritualitas bukanlah barang impor bagi masyarakat Jawa, melainkan sudah mengakar jauh sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Nusantara. Dalam kerangka ini, spiritualitas bukan sekadar pelengkap kehidupan, melainkan menjadi inti dari eksistensi manusia Jawa. Mereka meyakini bahwa hidup tidak bisa dilepaskan dari dimensi sangkan paraning dumadi — asal mula dan tujuan kehidupan yang menyatu dalam tatanan kosmis.
Jika kita menengok ke masa kini, dominasi modernitas dan pembangunan ala Barat yang bersifat materialistik, linear, dan antropocentris tampak seperti ironi bagi warisan kebudayaan Jawa yang sangat spiritual dan ekologis. Modernitas seringkali menawarkan kemajuan dalam bentuk fisik — jalan tol, gedung tinggi, dan industrialisasi — tetapi gagal menjawab kerinduan terdalam manusia akan makna, keseimbangan, dan kedamaian batin. Inilah mengapa banyak pemikir melihat bahwa paradigma modern Barat tidak selaras dengan ruh kebudayaan Jawa, bahkan kerap bertentangan.
Meski telah mengalami berbagai gelombang “penaklukan kultural” — dari Hindu, Buddha, Islam, hingga Kristen — jiwa asli orang Jawa tetap bertahan. Nilai-nilai seperti manunggaling kawula lan Gusti (penyatuan hamba dengan Tuhan), hamemayu hayuning bawana (menjaga harmoni semesta), dan cokro manggilingan (kesadaran atas dinamika hidup) menjadi bukti bahwa spiritualitas Jawa adalah fondasi yang lentur sekaligus tahan banting. Ia tidak sekadar menerima agama baru, tapi mengolahnya dalam kerangka nilai lokal yang lebih tua.
Menariknya, peradaban Jawa kuno juga menunjukkan kematangan dalam budaya politiknya. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak diukur dari kekuasaan atau struktur monarki, melainkan dari tingkat spiritualitas seseorang. Seorang pemimpin ideal bukanlah raja secara administratif, tapi orang sekti — tokoh yang telah menyatu dengan semesta dan mampu memancarkan tuah (rahmat) sekaligus tuwas (kemampuan menghancurkan kejahatan). Inilah bentuk politik berbasis karisma spiritual, bukan kekuasaan struktural. Sebuah konsep yang kontras dengan demokrasi modern yang lebih menekankan pada prosedur dan popularitas daripada kedalaman jiwa pemimpin.
Tak hanya itu, beberapa suluk dan babad Nusantara juga menyimpan narasi besar yang menyiratkan bahwa peradaban Jawa kuno adalah bagian dari peradaban global yang lebih tua, bahkan mungkin merupakan warisan dari peradaban Atlantis yang hilang. Penemuan artefak kapal pada lapisan gambut di kawasan Sundaland — yang terbentuk sejak 15.000 tahun lalu — menguatkan asumsi ini. Bahwa kita tengah berdiri di atas jejak-jejak peradaban besar yang tenggelam, namun meninggalkan nilai-nilai spiritual yang terus berdenyut dalam budaya Jawa hingga kini.
Memahami Kapitayan bukan sekadar mengungkap sejarah kepercayaan kuno, tetapi membuka mata terhadap akar spiritualitas Nusantara yang telah lama dilupakan. Ini adalah kritik diam namun tajam terhadap modernitas yang memuja kemajuan material, namun miskin makna. Kapitayan mengajarkan bahwa peradaban besar dibangun bukan hanya dengan teknologi, tapi juga dengan ketenangan batin, kesadaran kosmis, dan keharmonisan hidup.
Pemahaman terhadap Kapitayan sebagai ajaran asli Jawa bukan hanya penting untuk menelusuri akar spiritualitas Nusantara, tetapi juga relevan sebagai cermin reflektif terhadap arah kebudayaan dan pembangunan kita hari ini. Dalam era yang dipenuhi krisis makna dan kerusakan ekologis akibat modernitas yang serba materialistik, warisan nilai dari peradaban Jawa kuno — yang menempatkan spiritualitas sebagai pusat kehidupan — menawarkan alternatif paradigma yang lebih selaras dengan keseimbangan alam dan kedalaman batin manusia.
Alih-alih menganggap warisan tersebut sebagai mitos masa lalu, kita justru perlu menggali kembali kearifan lokal ini sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih beradab. Sebab di tengah pusaran globalisasi dan derasnya arus ideologi luar, identitas dan jati diri bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita meniru dunia, tetapi seberapa dalam kita memahami akar dan nilai-nilai luhur kita sendiri. Maka, mengenali Kapitayan adalah langkah awal untuk menyadari bahwa Indonesia, khususnya Jawa, pernah dan masih bisa menjadi pusat peradaban yang spiritual, adil, dan harmoni.[]
Nitiprayan, 5 Mei 2025