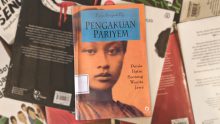“Hattā” dan Sinau Bareng: Ruang Dialog antara Manusia dan Tuhan

Melanjutkan tadabbur Ayat Perubahan, kita menemukan setiap ayat, susunan kalimat, hingga pilihan kata dalam Al-Qur’an, selalu menyimpan kedalaman makna dan nilai yang tidak pernah selesai untuk diselami. Semacam misteri yang ditelan oleh gemilang cahaya. Salah satunya terletak pada satu kata kecil namun sarat makna, yaitu: ḥattā pada QS. ar-Ra’d:11.
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ
Sekilas, ayat ini tampak sederhana: Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka. Kata ḥattā (hingga) menyimpan suatu makna tentang bagaimana manusia masuk ke dalam orbit kehendak Tuhan.
Ketika kita menelisik lebih dalam, ḥattā berfungsi tidak sekadar kata penghubung, tetapi penanda pola kerja bagaimana Allah Swt berkehendak. Hattā tidak sedang membatasi kekuasaan Tuhan, melainkan bentuk kehendak Tuhan itu sendiri. Allah tidak sedang menepi dan menyerahkan perubahan sepenuhnya kepada manusia. Allah justru berkehendak agar manusia menjadi makhluk yang sadar, bebas, dan bertanggung jawab.
Artinya, perubahan yang terjadi dalam jiwa manusia (mā bi anfusihim) adalah bagian dari rancangan Tuhan. Kesadaran untuk berubah, bahkan sekecil apa pun itu perubahan dalam jiwa kita, merupakan pancaran dari irādah Allah—kehendak ilahiah yang menuntun kita untuk berpartisipasi dalam karya ketuhanan di bumi.
Perubahan yang tampak berasal dari manusia sesungguhnya adalah pantulan dan perwujudan irādah Allah yang bekerja dalam kesadaran manusia. Manusia tidak menjadi pencipta perubahan, tetapi tempat terjadinya perubahan yang dikehendaki Allah—mazhar al-irādah al-ilāhiyyah (manifestasi iradah ilahiyah). Mbah Nun menegaskan, tidak ada perubahan, yang ada kita diubah oleh Allah Swt.
Maka, ketika seseorang merasakan dorongan untuk memperbaiki diri, memperluas kesadaran, atau menyeimbangkan cara berpikirnya, itu bukan sekadar keputusan psikologis, melainkan tanda bahwa sunatullah sedang bekerja di dalam jiwanya. Perubahan batin (mā bi anfusihim) adalah bagian dari proses kerja Tuhan. “Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah yang menghendaki” (QS. at-Takwīr: 29). Ayat ini tidak meniadakan kehendak manusia, tetapi menempatkannya dalam orbit kehendak Allah. Kita berkehendak karena dikehendaki untuk berkehendak.
Di sinilah kita menemukan dialektika yang indah: Tuhan meniscayakan kesadaran manusia. Ada sunatullah yang bekerja pada ranah kesadaran kita sebagaimana hukum alam bekerja di ranah fisika. Ketika kita bergerak menuju kebaikan, Allah membuka jalannya; ketika kita berpaling, Allah membiarkan kita tenggelam dalam pilihan kita.
Maka, kehendak Tuhan tidak meniadakan kebebasan manusia, tetapi justru melapangkannya melalui sunatullah. Hal ini menciptakan dialektika Rahman Rahim: kekuasaan Tuhan tidak menindas manusia, melainkan memanggilnya untuk turut serta dalam proses penciptaan perubahan.
Dengan demikian, ḥattā menandai titik temu antara “dua dunia”: dunia langit dan dunia bumi. Dunia langit penuh cinta, rahmat, dan kehendak tak terbatas; dunia bumi dipenuhi pilihan, kesadaran, dan tanggung jawab. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi menari bersama dalam harmoni kesadaran.
Manusia bergerak karena digerakkan, dan digerakkan karena memilih untuk bergerak. Dalam gerak itulah manusia menemukan martabatnya sebagai khalifah—bukan karena menandingi Tuhan, tetapi justru karena Tuhan mempercayakan sebagian dari kehendak-Nya kepada kesadaran manusia. Bahkan Tuhan pun berbagi kehendak dengan kita.
Ketika manusia tiba pada momentum ḥattā—yakni titik kesadaran dan perubahan—terjadilah perjumpaan “dua kehendak”: kehendak manusia yang ingin berubah, dan kehendak Tuhan yang sejak awal menghendaki perubahan itu terjadi.
Pemahaman ini melindungi kita dari dua kutub ekstrem yang sering menjebak cara berpikir keagamaan. Pada satu sisi ada fatalisme yang meniadakan tanggung jawab manusia karena menganggap segala sesuatu sudah ditentukan. Pada sisi lain ada antroposentrisme yang menuhankan manusia seolah seluruh perubahan bergantung pada dirinya. Al-Qur’an menuntun kita berada di jalan tengah: perubahan adalah inisiatif manusia yang berputar dalam orbit kehendak Tuhan. Manusia diberi kebebasan memilih mau berubah atau tidak.
Jadi, hattā adalah momentum sekaligus simbol pertemuan manusia dan Tuhan. “Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya” (QS. Al Kahfi: 110). Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak sekadar “memerintah dari langit,” tetapi “menunggu” di dalam diri manusia. Di ruang batin yang paling sunyi, kehendak Tuhan bergetar sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, dan menebar kebaikan.
Dalam konteks Sinau Bareng, Mbah Nun berperan sebagai pengungkit resonansi kesadaran. Beliau adalah individu yang sudah berubah karena diubah oleh Allah Swt, dan karena itu mampu menjadi wadah kerja Ilahiah dalam sejarah sosial. Tugasnya bukan memaksa, tetapi menghidupkan kesadaran. Bukan mengubah sistem dengan kekuasaan, tapi mengubah manusia dengan makna.
Melalui laku hidup beliau menyampaikan ayat: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum…” karena melalui kesadaran beliau Allah sedang mengubah banyak diri sekaligus—ya kita ini, para jamaah Maiyah. Dan di sana pula ruang bernama Maiyah dan Sinau Bareng mengejawantah menjadi tempat turunnya kehendak Tuhan secara nyata.
Tambakberas, 13 November 2025