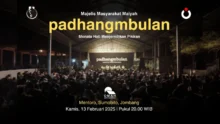Membincang Small is Beautiful di Masa Pandemi

Pada Reboan on the Sky pekan pertama Juni, Yai Tohar meminta peserta diskusi rutin mingguan Kenduri Cinta mencari buku Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered karya E.F. Schumacher. Ia meminta agar buku itu dibicarakan lagi karena relevan bagi gerakan kecil di masyarakat.
Reboan on the Sky minggu ini (10/06) topik diskusi yang diangkat adalah seputar Small is Beautiful, sesuai anjuran Yai Tohar. Ternyata buku yang berusia hampir setengah abad itu masih cocok dipelajari.
Buku yang konon sangat masyhur di era tahun 70-an itu ditulis seorang ahli statistik yang pernah menjadi salah satu penasihat ekonomi Negara Burma. Gagasan yang dibawa Schumacher dalam buku ini melawan arus utama perekonomian makro saat itu. Ketika slogan Bigger is Better digaungkan di mana-mana, Schumacher justru mengusung Small is Beautiful.
Sejenak kita kilas balik ke tahun 70-an. Saat itu dunia sedang berbulan madu dengan pembangunan. Di Indonesia sendiri, Soeharto sedang berbulan madu dengan kekuasaan, sehingga lahirlah konsep Repelita, yang kemudian diwujudkan dalam Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
Salah satu keresahan yang diungkapkan Schumacher di bukunya adalah di balik mega proyek pembangunan tersembunyi fakta pengeksploitasian sumber daya alam. Schumacher berpendapat bahwa ada problem sistemik yang muncul di balik layar pembangunan besar-besaran tersebut. Sementara itu, pada 1973, tahun ketika buku Small is Beautiful terbit, dunia sedang mengalami krisis energi.
Bagi Schumacher, ekonomi modern cenderung mengeksploitasi seluruh potensi yang ada dalam skala besar tanpa mempertimbangkan etika lingkungan dan sosial. Sekarang terbukti bahwa sistem ekonomi global justru melahirkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak salah kiranya jika ada ungkapan: yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena sistem ekonomi global begitu menghamba pada kerakusan.
Manusia memiliki kecenderungan konsumtif. Maka sangat berjodoh dengan sistem ekonomi neokapitalisme yang rakus. Pada titik ini teman-teman yang tergabung dalam diskusi Reboan on the Sky menemukan benang merah kenapa kemudian Mbah Nun pernah menulis buku Indonesia Bagian Sangat Penting dari Desa Saya (1983).
Sejalan dengan itu, nilai yang juga selalu dibawa Mbah Nun adalah konsep puasa yang menitikberatkan pada metode menahan diri, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai, tetapi harus dilakukan demi kebaikan. Bukan sekadar konsep puasa yang sebatas berhenti makan dan minum, atau menahan nafsu berhubungan seks. Bahwa konsep puasa demikian, jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu besar dampaknya.
Membedah Buku Small is Beautiful
Aditya Wijaya (penggiat Simpul Maiyah Mafaza) dan Rony K. Pratama (Jamaah Maiyah) didapuk menjadi pembahas karya E. F. Schumacher. Aditya menggarisbawahi masalah eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, seluruh Negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah pasti mengandung masalah. Baik dari sisi lingkungan, pemerataan kesejahteraan, maupun kehidupan sosial masyarakatnya. Papua adalah contoh nyata dari apa yang kita lihat betapa eksploitasi sumber daya alam itu begitu kejam dan sangat tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal itu akhirnya melahirkan gap.
Ketimpangan ini diperparah oleh tertinggalnya kemampuan teknologi yang dimiliki oleh suatu Negara dalam mengelola sumber daya alam yang ada, sehingga menjadi celah bagi negara lain untuk masuk dan kemudian mengekspolitasi sumber daya alam tersebut. Demikian pula ketika teknologi canggih yang masuk ke sebuah desa ternyata tidak ramah dengan masyarakat setempat. Kondisi ini membuat masyarakat teralienasi oleh teknologinya sendiri.
Pada konteks Indonesia kita melihat ada banyak jalur jalan darat yang sudah dibangun pada zaman penjajahan. Kemudian kita mendengar ada ungkapan Jalan Daendels. Nama ini diambil dari inisatornya: Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808-1810). Tujuan awalnya sangat jelas, yakni memudahkan laju mobilitas pemerintah kolonial dalam mengeksploitasi sumber daya alam.
Schumacher melihat eksploitasi sumber daya alam di dunia saat itu tidak sedang menuju pemerataan kesejahteraan sosial dan tidak berdampak maslahat bagi masyarakat kecil. Kalau demikian kenyataannya, menurut Schumacher, lebih baik industri pengelolaan sumber daya alam tidak perlu dibuka.
Karya Schumacher ini masuk kategori 100 buku penting setelah Perang Dunia II. Selain berisi kritik tajam terhadap neokapitalisme global, Small is Beautiful banyak mengulas prediksi masa depan. Pada tahun 70-an, ia telah melihat kelas pada tahun 2000-an jumlah penduduk bumi meningkat pesat. Laju peningkatan itu bersamaan dengan meroketnya konsumsi bahan bakar minyak. Kalau mengaitkan prediksi 40 tahun silam tersebut dengan hari ini, maka apa yang dikatakan Schumacher sangatlah tepat.
Jika saat ini kita menyaksikan bagaimana IMF, World Bank, dan Wallstreet sedang bertengkar, menurut Schumacher itu merupakan bagian dari fear industry. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, karena tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, cenderung menciptakan perang dagang transnasional. Hal itu membuat negara-negara yang kaya akan sumber daya alam ikut berdampak besar.
Rony K. Pratama sendiri memiliki sudut pandang lain mengenai buku karya Schumacher. Buku ini sebenarnya berisi kumpulan esai yang ditulis Schumacher sejak 20 tahun sebelumnya. Ia menjelaskan dari sudut pandang studi komparasi sejarah. Menurutnya, pada era 70-an, narasi yang digaungkan di seluruh dunia tidak jauh dari frasa pembangunan. Dalam salah satu tulisannya Schumacher mengkritik sistem tenaga kerja di negara-negara industri yang membuat para pekerja terasingkan oleh developmentalisme. Padahal, seharusnya pembangunan menghasilkan pencerahan, membuat masyarakat lebih sejahtera. Namun, fakta di lapangan justru sebaliknya.
Kemiskinan yang dialami manusia, khususnya di Dunia Ketiga, itu bukan merupakan nasib. Bukan karena masyarakat malas, tidak mau bekerja, sehingga mereka menjadi miskin. Rony mengutip paparan Schumacher di buku tersebut bahwa yang terjadi adalah pemiskinan. Ia mendekati masalah kemiskinan melalui teori ekonomi struktural.
Ada ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain yang dianggap sebagai patron. Biasanya negara yang dikategorikan Dunia Ketiga sengaja dikondisikan dependen. Negara ini dianggap perlu dibantu atau dimodernkan melalui mekanisme pembangunan. Tidak salah jika kemudian ada ungkapan bahwa Benua Afrika dibangun sebagai sekumpulan negara-negara miskin yang kemudian dimanfaatkan oleh elite filantropis di dunia untuk urusan kedermawanan sosial.

Rony melanjutkan, bahwa yang dipotret oleh Schumacher saat itu adalah hilangnya nilai kearifan suatu peradaban. Di tengah gegap-gempita pembangunan, kearifan sering ditinggalkan, bahkan dikubur karena tak seirama dengan modernisme. Masalah kearifan ini Schumacher dapatkan ketika tinggal di Burma sebagai penasihat ekonomi.
Seiring interaksinya dengan masyarakat setempat, ia mengelaborasikan pemikirannya lebih mendalam, sehingga lahirlah konsep sistem ekonomi Buddha. Pada ekonomi Buddha, masyarakat tidak boleh dijadikan objek neokapitalisme. Ekonomi harus memihak rakyat kecil. Kerakusan harus dibendung sebab tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritual. Sistem Ekonomi Buddha yang Schumacher tulis memosisikan manusia sebagai subjek berakal budi yang mesti berlaku harmonis. Baik terhadap sesama maupun alam di sekitarnya.
Sebuah pertanyaan muncul. Apakah pertumbuhan ekonomi yang berbasis PDB yang sering diacu pemerintah juga menjelaskan distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat? Ternyata tidak demikian pada kenyataannya. Di balik angka statistik, manusia hanya dimetaforkan sebagai nomor, namun sisi humanistiknya diabaikan.
Meskipun Schumacher merupakan ahli statistik di bidang ekonomi, ia selalu kritis terhadap bangunan keilmuannya yang belakangan dianggap parameter pertumbuhan ekonomi. Baginya, pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan peningkatan kesejahteraan serta ketersebaran keadilan bagi rakyat kecil. Di tangan Schumacher, ekonomi harus berpihak kepada mereka yang tertindas oleh tatanan neokapitalisme.
Relevansi Buku bagi Maiyah
Mas Ian L. Betts turut menambahkan sudut pandangnya mengenai buku Schumacher. Mas Ian membenarkan bahwa pada 1970-an, dunia sedang gandrung dengan pembangunan. Menurutnya, buku ini sangat penting dan cocok untuk diadaptasikan di era yang serba digital. Di tengah pandemi Covid-19, internet mendapatkan penetrasi cukup tinggi, karena dimanfaatkan oleh banyak orang untuk banyak hal.
Ditambahkan Mas Ian, saat ini orang tidak harus memiliki toko atau menyewa kios di tempat yang strategis untuk berjualan. Konsep perdagangan dalam skala mikro sudah berubah, bahkan bisa dillakukan tanpa kita memiliki kios, toko, atau lapak di mal yang biaya sewanya sangat mahal. Ada marketplace yang memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk berjualan, bahkan dengan modal yang sangat minimal sekali pun.
Benang merahnya dengan Maiyah, menurut Mas Ian, adalah karena Jamaah Maiyah bisa melangkah dan bekerja di akar rumput, melakukan kreativitas-kreativitas dalam skala yang kecil sekali pun. Mas Ian menggarisbawahi buku Indonesia Bagian dari Desa Saya yang ditulis Mbah Nun sebagai salah satu bentuk tanggapan yang kurang lebih sama seperti Schumacher merespons zaman pada tahun 70-an dan 80-an.
Dalam buku tersebut, yang awalnya cukup sulit dipahami Mas Ian, setelah beberapa tulisan ia baca, baru kemudian Mas Ian memahami bahwa Mbah Nun sedang menceritakan kisah di Menturo yang merupakan fakta empiris bagaimana kehidupan pedesaan saat itu mulai rusak ketika terkontaminasi dengan kehidupan kota. Misalnya, bagaimana pesawat televisi ternyata dapat mengubah sudut pandang masyarakat desa saat itu.
Menurut Mas Ian, Solusi Segitiga Cinta Maiyah yang digaungkan oleh Mbah Nun sangat relevan dengan kandungan buku Schumacher. Mas Ian kemudian merefleksikan bagaimana Rasulullah Saw melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketidakharmonisan suasana di Mekah memaksa Rasulullah Saw berhijrah ke tempat lain, yang kemudian memilih Madinah (Yatsrib) sebagai tempat tujuan.
Setelah Rasulullah Saw hijrah, kita mempelajari bahwa Rasulullah Saw datang ke Madinah tidak untuk melakukan eksploitasi, tetapi berkolaborasi. Merangkul semua pihak, menyepakati aturan main bersama, sehingga kemudian kerukunan masyarakat tercipta, dan distribusi kesejahteraan sosial masyarakat pun dirasakan semua pihak. Tanpa pandang bulu. Kontrol sosial dibangun bersama melalui Piagam Madinah.
Salah satu nilai yang bisa kita petik bersama dari peristiwa hijrah ini menurut Mas Ian adalah bahwa tidak selamanya escape itu berkonotasi negatif. Rasulullah Saw membuktikan itu. Bahwa meninggalkan Mekah menuju Madinah bukan sesuatu yang buruk. Rasulullah Saw melihat bahwa Mekah tidak kompatibel dengan nilai yang diusung saat itu. Maka demi keberlangsungan perjuangan dakwah Islam, Rasulullah Saw memilih hijrah.
Pada sesi akhir Yai Tohar merespons. Menurutnya, yang terjadi di tahun 70-an adalah pertarungan pemikiran-pemikiran yang sudah mengkhawatirkan mengenai kerusakan akibat pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

E. F. Schumacher sendiri memang sangat dipengaruhi gagasannya oleh Mahatma Gandhi, Buddha, dan Karl Marx. Buku Small is Beautiful merupakan hasil keresahan Schumacher melihat fakta dunia saat itu.
Bagi Yai Tohar, dengan adanya Pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa kekhawatiran yang muncul di era 70-an itu muncul kembali. Bahwa eksploitasi benar-benar menghasilkan peradaban yang penuh dengan kerusakan dan kehancuran. Menurutnya, buku Small is Beautiful waktu itu menjadi salah satu buku rujukan bagi Non-Governmental Organization (NGO) di Indonesia.
Alasan mengapa Jamaah Maiyah perlu mempelajari buku ini karena sebuah perubahan selalu diawali dengan gerakan kecil. Selama 3 bulan terakhir ini teman-teman penggiat Simpul Maiyah melakukan banyak kreativitas untuk tetap survive menghadapi Pandemi Covid-19. Banyak hal sudah dilakukan, bahkan sudah istiqomah. Semangat ini yang perlu ditularkan dalam skala yang lebih luas.