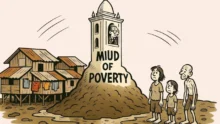Risalah Kebajikan di Era Scopus

Di negeri ini, universitas negeri mulai berwacana men-swastakan diri. Katanya: demi otonomi, daya saing global, efisiensi. Namun siapa yang tak mencium bau pasar dari kata-kata itu? Ilmu kini bukan lagi dicari—ia dijual, dengan kurs dolar per sitasi.
Rektor berbicara seperti CEO yang sedang menutup laporan tahunan. Dekan berubah jadi manajer unit bisnis. Dosen sibuk membuat proposal yang “layak jual.” Mahasiswa, kini disebut “stakeholder utama”—sebuah istilah yang menghapus kata murid dari kamus kemanusiaan. Dan Tri Dharma, yang dulu sakral, menjelma jadi Tri Target: publikasi, peringkat, pendapatan.
Di zaman Socrates, filsafat tak punya funding scheme. Ia mengajar di pasar, bukan di ruang rapat internasional. Ia tak mengejar Q1 journal, karena yang dicari adalah percakapan: api yang menyalakan pikiran. Namun kini, api itu padam pelan-pelan di bawah tumpukan laporan IKU, impact factor, dan rapat yang berputar seperti kipas listrik tua di musim panas.
Ia pernah berpesan: “Pendidikan bukan mengisi bejana, tapi menyalakan api.” Kini universitas sibuk menghitung skor global, melupakan nyala itu. Kampus menjadi pabrik sertifikat, bukan rumah berpikir. Ia kehilangan jiwanya: logos tergantikan oleh branding.
Ranking global, QS atau THE, sejatinya bukan untuk perguruan tinggi negeri—
institusi yang hidup dari uang rakyat dan seharusnya mengabdi kepada anak bangsa, bukan pasar dunia. Ranking itu relevan bagi kampus swasta, yang memang hidup dari daya tarik dan reputasi. Namun kini, PTN justru ikut berlomba, mencetak brosur internasional, mengejar visibility index, dan menulis “World-Class University” di setiap baliho, seolah ilmu bisa diiklankan seperti minuman energi.
Al-Farabi dulu menulis tentang al-madīnah al-fāḍilah—kota utama, tempat ilmu melahirkan kebajikan. Namun universitas hari ini justru mendekati madīnah al-korporāt: sebuah kota akademik yang hidup dari APBN di pagi hari dan swakelola di sore hari. Ia memiliki dua sumber napas: uang rakyat dan uang pasar. Sementara di seberang jalan, perguruan tinggi swasta harus bertahan dengan UKT mahasiswa dan sumbangan yayasan yang makin tipis.
PTN-BH kini seperti pelari yang disponsori: bersepatu mahal, bernafas dengan oksigen dari negara dan industri sekaligus. Sedangkan PTS, pelari telanjang kaki, tetap ikut lomba yang sama, dengan lintasan yang licin. Namun ketika garis finis diumumkan, yang disorot kamera tetap sang pelari bersponsor—karena “berhasil naik 10 peringkat QS.” Dan suara lirih rektor PTS—“Bagaimana mungkin kami berdaya saing global kalau negara memberi oksigen lebih banyak kepada yang sudah punya tabung sendiri?”—tenggelam di antara tepuk tangan para pejabat.
Sementara itu, di ruang-ruang kelas sederhana, masih ada dosen yang menyalakan api pengetahuan tanpa honor publikasi. Mereka mungkin tak punya laboratorium canggih,
tapi punya kejujuran berpikir—barang langka di kampus negeri yang sibuk berdagang wacana. Gedung bertambah, tetapi jumlah dialog berkurang. Ilmu dijadikan aset, bukan jalan menuju kebajikan.
Socrates, andai ia lahir di abad ini, mungkin akan dikeluarkan karena “tidak memenuhi target publikasi.” Dan Al-Farabi, andai masih menulis, barangkali menamai kitab barunya: Risalah Kebajikan di Era Scopus. Negara boleh memberi otonomi kepada universitas, tapi jangan memonopoli kesempatan. Kampus negeri boleh punya dua sumber dana, tapi jangan kehilangan satu sumber nilai: integritas ilmu. Sebab universitas tanpa keadilan adalah laboratorium tanpa cahaya; dan ilmu tanpa kebajikan hanyalah investasi jangka pendek dalam bursa reputasi dunia.
Barangkali kelak, anak-anak muda akan menulis kembali makna “kampus negeri.”
Bukan sebagai korporasi ilmu, tetapi sebagai taman tempat pikiran tumbuh liar dan bebas— di mana kebijaksanaan, bukan ranking, menjadi ukuran kejayaan.
Inilah saatnya kita bertanya kembali: sejak kapan universitas berhenti menjadi ruang sunyi tempat manusia mencari dirinya, dan berubah menjadi panggung bising tempat reputasi dijual seperti saham? Kita dulu percaya ilmu adalah jalan menuju kebajikan; kini ia menjadi komoditas simbolik di tangan para birokrat pengetahuan.
Bahwa pengetahuan, seperti puisi, tak bisa diukur dengan angka; ia hanya hidup sejauh manusia mau berpikir dan mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi kita justru menukar tanya itu dengan formulir, mengganti percakapan dengan akreditasi, dan menjadikan pikiran sebagai KPI.
Barangkali, di suatu senja nanti, kita akan menyadari bahwa yang hilang bukan sekadar idealisme kampus, tapi roh kebudayaan yang dulu menjadi alasan kenapa bangsa ini mendirikan universitas: untuk melahirkan manusia merdeka, bukan operator mesin peringkat global.
Dan pada saat itu, kita mungkin akan kembali mencari—bukan ranking, bukan insentif, bukan gelar—melainkan makna yang pernah sederhana: belajar karena ingin tahu, bukan karena harus terlihat tahu.
Di sanalah universitas akan menemukan dirinya kembali—bukan di ruang rapat, tapi di hati mereka yang masih percaya bahwa ilmu adalah cara manusia menebus ketidaktahuannya dengan kejujuran.[]
Nitiprayan, 1 November 2025