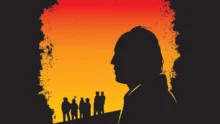Buzzer itu Kyai Dadakan, Influencer itu Nabi Instan

Ada orang bilang, “Hati-hati dengan konten di medsos. Itu propaganda.”
Tapi ada juga yang nyeletuk: “Lha, terus tulisan sampeyan ini propaganda juga apa ora?” Nah, bingung kan?
Memang begitulah nasib kita di zaman medsos. Buzzer dan influencer itu kayak dalang yang nggak pernah kelihatan wajahnya, tapi tangannya sibuk nggerakno wayang. Bedanya, wayang itu jelas fiksi, sementara konten mereka dikemas seolah-olah kebenaran. Lalu kita yang jadi penonton, kadang ikut ketawa, kadang ikut ngamuk, tapi jarang yang sadar kalau sedang dipentaskan.
Di sini lah pentingnya perspektivisme. Jangan buru-buru percaya, jangan juga buru-buru menolak. Ingat, tidak ada kebenaran yang final. Yang ada itu interpretasi—kayak orang lihat Gunung Merapi dari sisi Kaliurang dan dari sisi Boyolali: sama-sama Merapi, tapi beda wujudnya.
Propaganda itu bisa dikenali kalau kita belajar bertanya: “Siapa yang ngomong? Apa kepentingannya? Dari posisi mana dia melihat persoalan?” Kalau kita nggak pakai perspektivisme, kita gampang sekali jadi boneka emosi. Disulut sedikit, langsung marah. Dipuji sedikit, langsung percaya.
Tapi jangan salah. Perspektivisme itu bukan berarti semua serba relatif terus kita jadi apatis. Bukan. Justru dengan sadar bahwa semua adalah interpretasi, kita bisa lebih rendah hati: bahwa pandangan kita pun bukan satu-satunya kebenaran. Dan kita bisa lebih waspada: bahwa propaganda selalu menyelinap lewat pintu “sudut pandang tunggal” yang dipaksakan.
Jadi, kalau ada konten medsos yang bikin sampeyan langsung panas atau langsung baper, coba tarik napas dulu. Ingat, mungkin itu bukan fakta, tapi pancingan. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi seperti kambing dituntun ke pasar: jalan dengan semangat, tapi tidak tahu dirinya mau dijual.
Maka, ketika belajar jadi manusia perspektifis: ngerti bahwa dunia ini kaya dengan interpretasi. Nggak gampang kemakan agitasi. Nggak gampang ikut arus. Dan yang paling penting: tetap bisa ketawa meski sedang diprovokasi. Soalnya, ketawa itu kadang lebih subversif daripada marah-marah.
Kalau kita bicara perspektivisme, gampangnya begini—Sains melihat matahari sebagai bola gas panas dengan fusi nuklir di dalamnya. Seniman memandang matahari sebagai simbol kehidupan, inspirasi, bahkan kadang cinta yang membara. Petani melihat matahari sebagai berkah, sumber kesuburan tanah dan penentu musim tanam. Lha wong kuli bangunan pun mungkin melihat matahari sebagai “atasan galak” yang bikin keringatnya banjir sebelum jam istirahat.
Apakah ada yang salah? Semuanya benar, tapi juga semuanya terbatas. Kita nggak bisa memaksa petani untuk paham rumus termonuklir, sama seperti kita nggak bisa maksa ilmuwan untuk menulis puisi romantis tiap sore.
Di dunia medsos, buzzer itu sering berpura-pura jadi “sains”: seolah-olah dia yang paling tahu kebenaran mutlak. Padahal, ya sebenarnya cuma dagangan pesenan. Kontennya ditata biar kayak “matahari”—terang, jelas, nyinari semua orang. Padahal kalau diteliti, cahayanya cuma lampu LED murah yang bisa padam kapan saja kalau sponsornya berhenti bayar listrik.
Perspektivisme ngajari kita supaya jangan gampang keseret satu tafsir. Biar kita sadar bahwa apa yang kita lihat itu selalu dari sudut tertentu, dengan kacamata tertentu, sesuai kepentingan tertentu. Dan kalau kita bisa ngerti itu, kita jadi lebih tahan terhadap propaganda.
Karena, jangan-jangan yang kita kira “matahari” di medsos itu sebenarnya cuma senter yang dipasang di depan wajah kita. Beda tipis antara pencerahan dan pencitraan.
Kita musti paham bahwa konten-konten yang berseliweran di medsos itu jangan buru-buru dianggap kebenaran mutlak. Yang ada hanyalah propaganda dan agitasi yang sudah di-order sesuai pesanan. Kayak orang pesan sate kambing: jumlah tusuknya jelas, sambelnya jelas, dan yang makan ya si “user” yang bayar paling mahal.
Influencer dan buzzer itu bukan nabi, bukan ilmuwan, bukan wali. Mereka pekerja serabutan digital yang tugasnya bikin kita ikut menari mengikuti gendang yang dibayar. Kalau kemarin narasinya “A”, ya kita diajak percaya A. Besok kalau order baru masuk, ganti jadi “B”, ya tiba-tiba A dianggap dosa besar.
Kebenaran di medsos itu sering kayak harga cabe di pasar: naik-turun tergantung cuaca, musim, dan siapa yang lagi kuasa. Perspektivisme bikin kita sadar: jangan mau ditarik ke satu sudut seolah-olah itulah satu-satunya wajah kenyataan. Sebab di balik layar, ada produser yang sedang ngitung laba, bukan ngitung nurani.
Maka, tugas kita bukan menelan bulat-bulat apa yang lewat di timeline, tapi belajar memilah, bertanya, dan menertawakan. Karena kalau tidak, kita bisa jadi korban agitasi murah meriah. Padahal, lucu juga: yang bikin konten dapet transferan rekening, yang baca malah dapet darah tinggi.
Pembuat konten itu kalau sudah dapet order dari si user, langsung berubah jadi “tukang sulap digital.” Kalau pesannya bikin konten anti-Anu, ya jadilah seluruh dunia maya tiba-tiba penuh dengan konten anti-Anu. Caranya? Jangan bayangin rumit-rumit: cukup pakai ilmu potong-sambung, cut and stick, crop sana-sini, tambahin musik dramatis, lalu kasih narasi yang menyesatkan. Jadilah pamflet digital yang bisa bikin orang marah sambil merasa sedang menemukan kebenaran.
Padahal, yang mereka lakukan nggak lebih beda dengan pedagang bakso yang tahu cara nambahin micin biar pelanggan ketagihan. Bedanya, kalau bakso bikin kenyang, propaganda malah bikin lapar emosi.
Video dimanipulasi, gambar dipotong, teks dicuplik sepotong, lalu digoreng rame-rame di dapur medsos. Hasilnya? Rakyat yang lagi lapar keadilan bisa langsung “overdosis kemarahan.” Semua itu demi mempropagandakan tuntutan politik yang sudah dirancang rapi oleh si user.
Nah, problemnya: rakyat sering nggak sadar kalau dirinya sedang dimobilisasi. Kita merasa sedang “berjuang demi kebenaran”, padahal kita cuma sedang jadi “massa bayaran” tanpa amplop. Yang ketiban amplop ya si pembuat konten sama user-nya. Kita? Cuma dapat warisan stres, caci-maki, dan hubungan retak antar tetangga.
Makanya, perspektivisme itu penting. Biar kita nggak gampang dikelabui. Karena kebenaran sejati nggak pernah lahir dari crop foto atau editan video. Ia lahir dari hati yang jernih, dari akal sehat yang mau memeriksa sebelum percaya.
Sedangkan pembuat konten yang dipesan oleh si user untuk bikin konten pro-Anu, ya tentu saja resepnya sama: manipulasi, agitasi, propaganda. Bedanya, kalau yang anti-Anu pakai musik latar yang bikin kita tegang, yang pro-Anu pakai musik heroik yang bikin kita merinding bangga. Kalau yang anti-Anu nge-crop foto biar keliatan buruk rupa, yang pro-Anu nge-crop biar mukanya kinclong kayak habis facial di salon politik.
Semuanya sama-sama jualan narasi, sama-sama bikin rakyat ikut hanyut, marah atau bangga, tanpa sadar sedang jadi pasar. Bedanya cuma di branding: satu jadi musuh bersama, satu jadi pahlawan bersama. Padahal bisa jadi, dua-duanya cuma tokoh dalam iklan—yang penting siapa yang bayar iklan lebih mahal.
Agar lebih mudah memahami cara kerja para pembuat konten ini, bayangkan saja mereka seperti tukang dagang di pasar malam. Kalau orderan datang untuk jualan sate kelinci, ya mendadak suaranya lantang: “Sate kelinci paling enak, bikin kuat semalam suntuk!” Besok ada orderan jualan gelang kesehatan, langsung berubah narasi: “Pakai gelang ini, semua penyakit sembuh, jodoh pun datang!”
Di medsos pun sama: hari ini mereka jualan kebencian, besok jualan pujian. Hari ini Anu digoreng gosong, besok Anu dipoles jadi malaikat. Kita penontonnya—seperti orang lewat di pasar malam—tinggal pilih: mau ikut beli dagangannya, atau sekadar senyum-senyum melihat akrobat para pedagang retorika.
Bahasa yang dipakai dalam konten propaganda itu biasanya penuh diksi emosional: “raib,” “runtuh,” “luka,” “hancur lebur,” “bangkit atau binasa.” Kata-kata itu sengaja ditembakkan ke ranah afektif kita, biar kita nggak sempat mikir pakai akal sehat. Kita langsung digiring untuk simpati, atau lebih gampang lagi: untuk marah.
Padahal, kalau konten itu dipreteli, isinya sering biasa saja. Tapi begitu dibungkus dengan kata-kata dramatis, pembaca jadi ikut deg-degan, seolah-olah dunia mau kiamat. Sama seperti penjual obat kuat di pasar malam: suaranya bikin kita yakin kalau tidak beli hari itu, hidup kita tamat.
Itulah seni agitasi. Ia tidak peduli fakta, tapi peduli efek. Tidak soal benar atau salah, yang penting “kena di hati.” Propaganda tidak ingin kita berpikir, tapi ingin kita bereaksi. Marah, panik, atau bertepuk tangan.
Maka, perspektivisme menolong kita untuk menjaga jarak. Kita bisa bertanya: “Ini berita, atau ini cuma drama? Ini fakta, atau sekadar efek kata?” Karena sering kali, luka yang mereka teriak-teriakkan hanyalah lukisan di papan reklame, bukan luka asli. Tapi anehnya, kita bisa ikut nangis dan ngamuk, padahal perban dan obatnya tidak pernah sampai ke kita.
Masalah besar kita hari ini adalah ketika “kebenaran” di ruang publik tidak lagi lahir dari fakta objektif, tapi dari konstruksi influencer dan buzzer. Mereka itu seperti tukang make-up: wajah yang sebenarnya jerawatan bisa disulap jadi mulus kinclong, atau sebaliknya, wajah yang sehat bisa dipoles jadi tampak menyeramkan.
Influencer dan buzzer tidak sedang memberi kita fakta. Mereka memberi kita propaganda kelompoknya. Mereka tidak sedang menyalakan lampu penerang, mereka malah sedang memasang lampu sorot yang diarahkan ke panggung tertentu, biar kita fokus pada yang mereka mau.
Dan rakyat lugu? Dengan polosnya mengonsumsi propaganda itu seakan-akan fakta. Sama seperti anak kecil nonton sulap di pasar malam: kaget, kagum, ternganga, padahal kalau mau mikir sebentar, itu cuma trik ilusi.
Kebenaran publik akhirnya jadi mirip panggung ketoprak murahan: dialognya penuh teriakan, alurnya dipaksakan, lakonnya berubah sesuai siapa yang bayar lakon itu dipentaskan. Kita para penonton menonton serius, padahal sebagian besar hanyalah karangan.
Maka, perspektivisme penting bukan untuk bikin kita sinis, tapi untuk bikin kita waspada. Supaya kita tahu bahwa “kebenaran” yang berseliweran bisa jadi hanyalah propaganda yang kelihatan faktual. Dan supaya kita tidak buru-buru menelan bulat-bulat, lalu ikut marah atau ikut bangga, padahal sebenarnya kita sedang dipermainkan. Karena sejatinya, kebenaran itu bukan apa yang ditulis buzzer, tapi apa yang masih berdenyut di hati nurani kita.
Akhirnya kita mesti sadar, “kebenaran” di medsos itu rapuh, penuh manipulasi, dan gampang dibeli. Yang sejati hanya satu: kebenaran milik Gusti Allah. Perspektivisme boleh membantu kita memahami bahwa manusia hanya mampu menafsir, tapi tafsir kita selalu terbatas dan bias. Maka, jangan jadikan buzzer sebagai nabi, jangan jadikan influencer sebagai kitab suci. Pegang teguh hati nurani, karena di situlah Allah menitipkan cahaya kebenaran.
Kalau ada yang bilang “kebenaran itu jelas, sudah viral kok,” ya ketawa saja. Kebenaran sekarang bisa dipesan lewat invoice, dicetak di konten, lalu dikirim kilat ke timeline. Influencer jadi nabi instan, buzzer jadi ulama darurat, dan kita semua disuruh ikut sujud di depan “fakta editan.” Kalau kita nggak sadar, besok-besok kebenaran bisa kayak jualan bakso: siapa yang bayar lebih, dialah yang punya rasa.[]
Nitiprayan, 5 September 2025