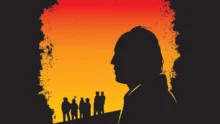Penguasa Takut Sama Nota Bon

Demonstrasi yang kini sedang meledak-ledak itu penting. Penting seperti jerawat di wajah remaja — kadang bikin minder, kadang bikin pamer, kadang bikin orang sadar bahwa tubuh memang sedang bergolak. Tapi, jangan buru-buru percaya bahwa jerawat ini akan mengubah wajah kita jadi bercahaya. Sejarah sudah kasih cermin: 1998 lebih dahsyat, lebih luas, lebih lama, lebih mengguncang. Jalanan penuh tubuh. Gas air mata jadi oksigen. Orde yang katanya abadi runtuh. Tapi, setelah itu, apakah benar kita berubah?
Waktu itu yang retak segera disemen dengan kompromi. Yang jatuh hanya nama, bukan watak. Yang tumbang hanya rezim, bukan kebiasaan. Itu mirip orang ganti baju, tapi tetap mandi dengan cara yang sama — malah sering tidak mandi. Maka, bagaimana kita menaruh harapan pada demonstrasi hari ini? Seperti menaruh lilin di tengah badai. Nyala ada, tapi ringkih. Cahaya ada, tapi sebentar.
Namun lilin itu tetap penting. Sebab lilin bukan cuma soal terang, melainkan ingatan. Ia mengingatkan bahwa rakyat pernah menolak tunduk. Bahwa di negeri yang sering pura-pura tuli, suara rakyat pernah jadi dentuman. Tapi ingatan juga kadang menipu. Dari 1998 kita belajar: euforia bisa lebih cepat daripada perubahan. Janji reformasi bisa lebih berisik daripada hasilnya.
Jangan-jangan kita ini bangsa yang lebih suka pesta daripada kerja bakti. Lebih rajin teriak “Hidup Rakyat!” daripada belajar membedakan mana rakyat, mana pejabat yang pura-pura rakyat.
Jadi, apakah demonstrasi ini sia-sia? Tidak. Ia tetap sakral, walau kadang terasa karnaval. Ia tetap tanda, walau kadang jadi dagelan. Sebab bangsa ini mungkin tidak pernah benar-benar berubah, tapi rakyat selalu menemukan cara untuk mengingatkan: “Hei, jangan seenaknya. Kami masih ada. Kami bisa marah.”
Dan siapa tahu, di antara lilin-lilin ringkih itu, ada satu nyala yang kelak tidak padam — yang bisa menyulut obor. Tapi, sambil menunggu itu, jangan lupa siapkan payung. Karena badai masih panjang, dan lilin tidak suka kehujanan.
Kini, apa yang berbeda? Atau jangan-jangan ini hanya ulangan? Fragmen yang sama diputar ulang, dengan aktor baru, dengan jargon baru, tapi dengan panggung yang tak berganti. Reformasi kemarin sudah seperti drama kolosal di TVRI tahun 80-an — penuh musik latar, penuh heroisme, tapi ujungnya penonton pulang dengan perasaan kosong. Maka pertanyaannya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah babak baru, atau sekadar encore dari sebuah sandiwara lama?
Sandiwara itu kadang menghibur, kadang bikin geram. Bayangkan: kursi yang sama, lampu sorot yang sama, hanya kostum yang ganti. Hari ini disebut “reformasi jilid dua,” besok mungkin “transisi emas,” lusa bisa “era keterbukaan 5.0.” Kita disuguhi poster baru, tapi tiketnya tetap dibayar dengan uang rakyat.
Padahal, yang paling ditakuti penguasa bukan bom. Bukan peluru. Bukan teror. Yang paling ditakuti penguasa justru tiga hal yang sederhana, lahir dari rakyat biasa.
Pertama: kata-kata. Kata bisa jadi arus. Bisa mengalir lewat spanduk, lewat status Facebook, lewat mulut ibu-ibu penjual sayur. Kata yang dibisikkan di warung kopi bisa lebih menusuk daripada makalah profesor.
Kedua: keteguhan. Satu orang bisa dibeli, sepuluh orang bisa ditakut-takuti, tapi ketika ribuan orang tetap duduk di jalan, tak bergeser meski hujan turun, itu lebih menakutkan daripada pasukan bersenjata.
Ketiga: ingatan. Rezim bisa membangun gedung tinggi, bisa membuat jalan tol panjang, bisa meluncurkan jargon secanggih apapun. Tapi kalau rakyat ingat bahwa mereka pernah ditipu, pernah diperas, pernah dijanjikan lalu dikhianati, ingatan itu lebih tajam dari pisau dapur.
Jadi, kalau hari ini kita masih melihat orang-orang turun ke jalan, itu artinya tiga hal itu belum mati. Kata masih bisa hidup, keteguhan masih bisa tumbuh, ingatan masih bisa diwariskan. Dan mungkin, justru karena itulah penguasa selalu tampak panik — karena sandiwara lama ini bisa jadi suatu hari tidak sekadar encore, tapi benar-benar tamat.
Kata-kata. Itu senjata pertama. Sebab kata bisa menjelma arus. Satu kata bisa jadi percikan, sepuluh kata bisa jadi nyala, seribu kata bisa menjelma banjir. Kebobrokan yang dibuka ke ruang publik, diviralkan, didengungkan, membuat penguasa kehilangan wajah. Rezim bisa bertahan dari krisis ekonomi, tapi sulit bertahan dari krisis legitimasi.
Lalu tubuh-tubuh di jalan. Aksi massa yang benar-benar masif, bukan sekadar simbolis, selalu membuat negara gemetar. Dari jaman Yunani kuno, revolusi Perancis, sampai Tahrir Square di Mesir 2011, sejarah memberi bukti: kekuasaan apa pun bisa runtuh ketika rakyat beramai-ramai berkata tidak. Satu tubuh bisa ditangkap, seratus bisa dipukul mundur, tapi ribuan yang terus berdatangan akan selalu lebih besar daripada aparat manapun.
Dan ada senjata ketiga — yang justru paling sederhana, tapi paling ditakuti. Kesadaran sebagai pembayar pajak. Bayangkan bila rakyat membentuk organisasi yang bukan partai, bukan ormas, tapi perkumpulan independen para warga yang membiayai negara. Mereka bisa berkata: kami ingin audit, kami ingin transparansi, kami menolak membayar sebelum uang kami jelas ke mana.
Sebuah gerakan “boikot pajak” — itulah hantu paling menakutkan bagi negara modern. Bukan demo, bukan makar, bukan kudeta. Tapi sebuah pembatalan kepercayaan terhadap pondasi paling dalam kekuasaan: kas negara. Sebab seluruh bangunan kekuasaan berdiri di atas pungutan itu.
Bayangkan: negara berdiri di atas uang yang bisa setiap saat ditahan, diawasi, diboikot. Untuk pertama kalinya, rakyat punya senjata — bukan senjata api, melainkan senjata fiskal. Senjata yang lebih tajam dari peluru, karena ia menyentuh jantung negara modern: neraca keuangan.
Maka, di balik senjata, aparat, dan regulasi, justru ada ketakutan yang sunyi: ketakutan menghadapi rakyat yang bersuara, berkumpul, dan menyadari dompetnya. Sebab uang rakyat itu ibarat urat nadi: kalau rakyat menekan sebentar saja, kekuasaan bisa sesak napas.
Demokrasi tanpa hak rakyat atas uangnya hanyalah demokrasi difabel — cuma suara tanpa gigi. Kita boleh berteriak di jalan, boleh memaki di media sosial, boleh bikin meme yang lebih kejam dari satire Yunani, tapi selama negara tetap bebas memungut dan membelanjakan uang rakyat tanpa kontrol langsung, kekuasaan tetap satu arah: dari mereka yang bersenjata lengkap kepada kita yang hanya berbekal poster, spanduk, dan pekik.
Itulah mengapa gagasan organisasi rakyat pembayar pajak adalah yang paling radikal. Ia membalik logika demokrasi: dari sekadar hak memilih, menjadi hak mengaudit. Dari sekadar partisipasi prosedural, menjadi partisipasi finansial yang menentukan.
Bayangkan: rakyat bilang, “Kami menunda setoran, sampai laporanmu jelas. Kami boikot, sampai anggaranmu transparan. Kami audit, sampai kursi-kursi empukmu tidak lagi cuma tempat tidur siang.” Itu bukan makar. Itu cuma logika sederhana: kalau uang ini dari kami, maka kami yang berhak menentukan.
Mungkin kedengarannya utopis. Tapi jangan lupa, sejarah manusia sering bergerak dari utopia. Demokrasi dulu dianggap utopia, kemerdekaan juga utopia, bahkan listrik pernah dianggap sihir. Jadi, siapa tahu, utopia fiskal rakyat ini bisa jadi realitas besok.
Dan kalau hari itu tiba, para pejabat mungkin akan lebih takut pada kwitansi daripada demonstrasi. Lebih gentar pada nota rakyat daripada bom molotov. Karena rakyat akhirnya menemukan senjata baru: kalkulator.
Senjata Fiskal dan Ruang Hidup
Bayangkan: negara berdiri di atas pungutan yang bisa setiap saat ditahan, diawasi, diboikot. Maka untuk pertama kalinya rakyat punya senjata — bukan senjata api, melainkan senjata fiskal. Senjata yang lebih tajam dari peluru, karena menyentuh jantung negara modern: kas keuangan.
Maka mungkin inilah yang paling ditakuti: rakyat yang sadar bahwa suara hanya lima menit, tapi pajak adalah sepanjang tahun. Suara bisa dilupakan, bisa ditukar dengan sembako, bisa dikubur dengan baliho. Tapi pajak — itulah denyut yang tak bisa dipalsukan. Tanpa itu, demokrasi hanyalah panggung dengan tirai warna-warni: ramai, berisik, tapi rapuh.
Namun senjata fiskal, betapapun radikalnya, tak bisa berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh sesuatu yang lebih dalam: pengorganisasian rakyat di ruang hidupnya sendiri. Sebab apa arti boikot pajak bila ruang-ruang lokal tetap dikuasai elite? Apa arti audit independen bila rakyat bahkan tak punya kedaulatan atas sawahnya sendiri, pasarnya sendiri, sekolah dan masjidnya sendiri?
Maka yang dibutuhkan adalah penguasaan ruang — spasial, sosial, sektoral, bahkan spiritual. Desa yang tahu ke mana aliran airnya, bukan menunggu izin dari pabrik semen. Pasar yang tahu siapa mengendalikan harga, bukan pasrah pada algoritma e-commerce. Komunitas yang tahu siapa bicara atas nama mereka, bukan sekadar “influencer” dengan suara yang dipelihara sponsor. Dan iman yang tidak mudah digadaikan dengan slogan politik atau amplop Jumat pagi.
Tanpa itu, demokrasi tetap menjadi pesta formalitas: suara dihitung, tapi hidup tetap ditentukan orang lain. Kita boleh ikut lomba pidato tentang kedaulatan, tapi nasi di piring tetap bergantung pada siapa menguasai pupuk. Kita boleh ikut pemilu lima tahun sekali, tapi anak-anak kita tetap duduk di kelas yang plafonnya bocor. Demokrasi tanpa ruang hidup hanyalah dekorasi. Cantik di brosur, elegan di seminar, tapi rapuh di dapur rakyat.
Pendidikan kritis adalah urat nadi dari semua itu. Ia mengajarkan rakyat bukan hanya cara membaca, tapi cara membaca dunia. Membaca siapa di balik proyek pembangunan. Membaca siapa di balik pinjaman luar negeri. Membaca siapa yang tersenyum paling lebar ketika rakyat diminta “bersabar demi stabilitas.”
Maka, bila demokrasi hari ini terasa difabel, itu bukan semata karena undang-undangnya pincang. Tapi karena kita berhenti belajar. Kita biarkan rakyat tetap jadi penonton, bukan aktor. Dan penguasa tahu itu. Karena rakyat yang tak terdidik kritis lebih mudah dipimpin dengan hiburan dan ketakutan. Disuguhi konser gratis, lupa harga beras. Ditakut-takuti dengan kata “radikal,” lupa bahwa korupsi jauh lebih radikal daripada demo mahasiswa.
Bayangkan, sebuah organisasi para pembayar pajak. Rakyat sebagai donatur negara, bukan sekadar pemilih musiman. Setiap rupiah yang mereka setorkan, punya hak untuk ditanya: ke mana perginya? siapa yang menikmatinya? mengapa hasilnya tak kembali?
Organisasi ini bukan partai, bukan ormas. Ia bukan wadah untuk rebutan kursi, melainkan perkumpulan yang menuntut transparansi fiskal. Senjata mereka bukan bom molotov, melainkan audit independen. Dan di negara modern, itulah sebenarnya titik paling rawan kekuasaan: kas negara.
Lalu, apa salahnya bila di saat yang sama lahir pula “DPR tandingan”? Sebuah representasi rakyat yang betul-betul diisi suara bawah, bukan kuota partai. Mungkin tanpa kursi megah, tanpa ruang sidang ber-AC, tanpa payung hukum. Tapi punya legitimasi moral — dan kadang legitimasi moral jauh lebih menakutkan ketimbang legitimasi formal.
Apakah ini utopis? Tentu. Tapi bukankah reformasi 1998 dulu juga tampak utopis ketika mahasiswa pertama kali turun ke jalan? Bukankah kemerdekaan 1945 juga tampak utopis ketika hanya segelintir orang di Jakarta membaca proklamasi dengan mikrofon pinjaman?
Pertanyaan kuncinya bukan: apakah mungkin? Tapi: apakah rakyat siap mengorganisasi dirinya? Karena negara modern adalah Leviathan yang bernafas lewat pajak. Dan satu-satunya cara rakyat bisa benar-benar punya gigi adalah dengan menyentuh aliran darah itu.
Maka, gagasan ini bisa jadi momentum. Bisa jadi tonggak. Tapi juga bisa jadi ilusi — jika rakyat berhenti pada retorika, tanpa membangun basis nyata di lokal: ruang sosial, ruang spasial, ruang sektoral, bahkan ruang spiritual.
Sebab pada akhirnya, demokrasi itu bukan apa yang ditulis di konstitusi, melainkan apa yang hidup di sawah, di pasar, di sekolah, di mushola, di warung kopi. Kalau di sana rakyat berdaulat, maka di istana pun rakyat tak bisa diabaikan. Tapi kalau di sana rakyat hanya jadi penonton, maka di istana rakyat hanya akan jadi penonton yang lebih jauh — menyaksikan sandiwara, membayar tiket, tanpa pernah ikut menulis naskah.[]
Rumah Sawah, 1 September 2025