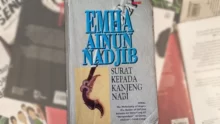Dari Make Up ke Make Up

Krisis ekonomi ini merupakan salah satu produk dari krisis yang sudah berlangsung puluhan tahun. Apa itu? Yakni krisis politik dan krisis kebudayaan.
Krisis politik yang saya maksudkan adalah, ketika kita bicara demokrasi, yang kita lakukan ternyata feodalisme, yang kita kerjakan jebul peternalisme. Kita ngomong ndakik-ndakik tentang republik, tapi yang kita lakukan bersama mensemukan lembaga-lembaga demokrasi. Kita bikin lembaga seperti MPR/DPR sebenarnya tidak punya eksistensi yang independen, dia tergantung pada puncak pimpinan eksekutif. Jadi Trias politika akhirnya hanya performa, hanya cat, make up, didandani ben kaya republik, begitu berwudlu, cuci muka, jebul kerajaan. Itu yang saya sebut krisis politik.
Untuk mengatasi krisis moneter, kita harus mendata kembali semua kekayaan terutama yang berada di kantongnya kelas kakap. Setelah itu, kalau saya jadi pemerintah, saya bikin peraturan nasional: semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar prosentase yang harus dia berikan untuk menyelamatkan negara ini. Kalau nanti Anda hitung-hitung betul, Anda kasih stratifikasi tentang prosentase tingginya pendapatan, akan Anda dapatkan ternyata rakyat miskin, menengah ke bawah, kaum proletar itu tidak perlu dilibatkan untuk mengatasi krisis.
Sing ora cinta iku sopo? Promosi cinta rupiah itu ke mana arahnya? Kalau Anda mengiklankan sesuatu kan harus tahu betul arahnya. Metode promosinya, metode dakwahnya harus disesuaikan betul arahnya, sasarannya siapa itu? Kalau sasarannya konglomerat, tidak bisa mereka itu diinsafkan dengan himbauan cinta rupiah, mereka harus dipaksa oleh peraturan pemerintah. Metode sasaran cinta rupiah itu selama ini sasarannya kan wong cilik, masyarakat umum. Masyarakat umum itu tidak bisa apa-apa, rupiah, rupiah yang tidak begitu cinta sama mereka, bukan mereka yang tidak cinta rupiah. Mereka direwangi hidup tidak karu-karuan, tapi rupiahnya tidak cinta sama mereka. Jadi promosi cinta rupiah yang ada di TV, di jalan-jalan itu menurut saya, sebagai metode dia tidak efektif, dia juga tidak kondusif. Tidak akurat dalam menentukan sasarannya,segmen yang akan dia promosikan.
Kalau politiknya sehat gampang itu mengatasinya, seperti Malaysia, Korea, lumayanlah. Kita tidak bisa bikin peraturan seperti itu, tidak bisa melakukan pembatasan-pembatasan seperti itu, karena ada tabu-tabu feodalisme politik. Anak ratu dilawan brata, karena tabu politik dan tabu budaya tidak bisa diungkap. Lha wong sinetron menggambarkan camat jelek saja tidak boleh, paling lurah yang boleh. Lha kalau camat saja sudah tidak boleh diobyektifikasikan eksistensinya, ya apalagi bupati, gubernur, menteri dan presiden, lebih tabu lagi.
Krisis budaya dan krisis politik ini bukan satu-satunya penyebab krisis. Ada peta global, ada gelombang ideologi, ada political will dari jaringan-jaringan tertentu yang bersifat internasional yang — kalau saya kutip pernyataan Mahathir — yang memang tidak menghendaki ada pemimpin-pemimpin Asia yang tidak dikehendaki AS memegang kekuasaan. Kalau mau lebih transparan, tidak boleh terjadi perkawinan antara dua faktor: faktor pertama adalah kekuatan ekonomi, faktor kedua adalah besarnya ummat Islam. Ummat Islam ini boleh banyak boleh besar tapi jangan pegang kekuatan ekonomi, ekonomi Indonesia boleh kuat, boleh menjadi macan di Asia tapi jangan dipegang ummat Islam. Ummat Islam kere saja, kalau kere diijinkan untuk hidup. Kere dan bodoh.
Saya bilang, yang harus dijadikan acuan oleh Pak Harto untuk mengatasi semua ini adalah acuan Khomeini atau Saddam Husain. Dengan belajar dari kasus di Aljazair, dan menghindari jangan sampai terjadi seperti di Turki. Turki boleh ummat Islamnya banyak, tapi Islamnya sudah sekuler. Dan Indonesia ini kan negara yang sangat-sangat sekuler. Orang baca al-Qur’an di mana-mana, adzan di mana-mana, bikin acara Ramadhan di televisi, dari pagi sampai pagi, semarak, tapi alam pikiran mereka dalam menyikapi dan memandang acara-acara semacam itu sangat sekuler. Jadi sekuler tidaknya kehidupan itu tidak tergantung pada produknya, tapi tergantung pada bagaimana sikap Anda terhadap produk itu. Anda boleh saja ngaji tiap hari, tapi kalau pandangan Anda terhadap ngaji itu sekuler, ya ngaji itu jadi tidak religius.
Kalau orang punya banyak priuk di rumah, bukan merupakan tanda bahwa ia punya banyak nasi. Jadi tidak tergantung pada bendanya apa, peristiwanya apa, tapi anggapan dan konsep dia terhadap benda dan peristiwa itu. Sama seperti pelajaran agama atau pelajaran umum. Anda tidak bisa menyebut tarikh Islam, tafsir, hadis Rasul, sebagai pelajaran agama. Aljabar, biologi, matematika, tidak otomatis pelajaran umum. Bersifat religius atau sekuler tergantung bagaimana kita mensikapinya. Kalau saya belajar Aljabar untuk berproses menemukan ketakjuban saya pada hitungan Allah, pada hisbullah, religius kan itu. Saya belajar Biologi untuk membuktikan ayat ya Allah tidak sia-sia Engkau menciptakan ini semua, religius itu biologi. Saya melihat teropong dengan gairah spiritual. Tapi sebaliknya, saya belajar tafsir, belajar segala macam, tapi cara saya melihat tafsir itu tidak religius, kan menjadi pelajaran umum, pelajaran sekuler, bukan pelajaran agama. Sama dengan orang sholat, belum tentu religius, niat dia bagaimana, konsep dia dalam sholat bagaimana? Bisa saja sholat itu merupakan representasi dari sekurelisme. Berdoa juga belum tentu religius, wong berdoa kok dia kotor. Kalau sholatnya untuk tujuan, bukan untuk cara, ya sekuler itu. Akhirnya Orang banyak menyembah sholat, “Wah dia rajin sholatnya, dia tidak pernah sholat, titik.” Itu pertanda kita menyembah sholat. Sholat itu thariqah bukan ghoyah. Keislaman seseorang tidak ditentukan oleh kerajinan dia sholat, tapi oleh produk yang dihasilkan dari sholat itu.