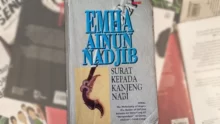Manusia Pasca Ibrahim

Kata orang arif, kebanyakan kaum muslimin dewasa ini maqam ilmu hidupnya ‘masih Hindu’, ada juga gejala ‘sudah Budha’ atau bahkan ‘sudah Kristen’, namun kondisi rata-ratanya adalah ‘belum Islam’. Jadi masuk akal kalau pengetahuan mengenai kesempurnaan Islam atau kepamungkasan kenabian Muhammad lebih diterima sebagai dogma gelap dari pada hasil internalisasi. Tidak diketahui dan kurang dipelajari oleh kebanyakan kaum muslimin tanjakan-tanjakan kualitatif ilmu kehidupan yang diperankan oleh urutan-urutan ’25 aktor’ Rasul menuju al-ufuq al-mubin yang bernama Islam. Orang Islam tiap hari berpuluh-puluh kali mengucapkan ‘Allahu Akbar’ tidak karena takjub oleh setiap terminal penghayatan ilmu, melainkan karena “setiap serdadu harus apel di setiap Parade Senja”.
Peluang untuk tholabul ‘ilmi secara jujur juga makin sempit peluangnya oleh politik misalnya oleh konsep SARA yang ndeso. Tidak popular bagi kita progressi dari ‘Adam Balita’, ‘Nuh TK’, ‘Ibrahim Remaja’, ‘Ismail DO’, ‘Musa Sarjana Anyaran’, ‘Isa Doktor GR’ dan — ’Muhammad Paripurna’. Kita tidak memiliki kebebasan akademik dan tidak bersikap historis terhadap proses pertumbuhan ilmu di bumi, karena agaknya Musa, Isa, Budha, dan Muhammad itu berasal dan hidup untuk planet sendiri-sendiri.
Maka kata orang arif pula makin tak tahulah kita betapa besar dan dahsyat bias-bias sejarah yang termanifestasikan kedalam pemikiran, ideologi serta segala pekerjaan pembangunan peradaban ummat manusia—yang diakibatkan oleh pemakaian kesadaran pra-Isa dimana Tuhan di-Dia-kan, atau periode Isa dimana Tuhan di-Aku-kan, dan betapa tawaran kreatif Muhammad yang meng-Engkau-kan Tuhan masih merupakan barang amat langka.
Mudah-mudahan saya diberi anugerah kesanggupan untuk sedikit menjelaskan apa yang dimaksud oleh orang arif itu.
***
Proses-proses sejarah ‘menyuruh’ kita di suatu soal turun merangkul substansi benda, di soal lain substansi turnbuh-tumbuhan, mempopularkan tata-nilai hewan terutama di bidang politik dan ekonomi; kemudian ‘kualitas manusia’ tidak kunjung kita temukan karena substansi dan sistematika keilmuan kita terletak beberapa langkah di belakang kesadaran untuk menerjemahkan maqom abdullah meningkat lagi khalifatullah. Kita belum tahu apa integritas daun pepaya atau seekor cicak dalam kerangka keabdullahan dan kekholifahan.
Proses internalisasi itu tentu saja seret karena kualitas kemanusiaan yang belum mengandalkan penghayatan pribadi, tradisi riset dan ‘membaca gejala alam semesta’. ‘Remaja’ Ibrahim memulai disiplin itu. (Ismail hingga Muhammad adalah derajat empiris ilmu-ilmu yang lebih tinggi dan complicated lagi).
Tiba-tiba kita hidup di hadapan sebuah meja makan besar dalam suatu acara prasmanan di mana kita tinggal memilih makan-makanan jadi. Kita mengambil kue serabi, lantas mengerahkan lidah, perasaan dan tenaga untuk merasakannya, bukan untuk menelusuri sejarah serabi. Kita tidak memiliki imaji tentang pati, tungku pemasak, sumber api, gerabah pencetak, bagaimana wajah pembikin kue serabi dan bagaimana bau keringatnya. Kita juga baru ingat gula kalau duduh serabi itu terlalu manis atau kurang manis.
Dengan kata lain, untuk ‘menjadi’ Muhammad, kita tidak terlebih dahulu ‘berperan’ sebagai Adam dan seterusnya hingga Isa sambil pusing oleh panggung penah bias hasil terjemahan-terjemahan parsial setiap tahap itu kedalam upaya penyusunan peradaban ummat manusia termasuk sejak St. Paul hingga NKK BKK atau Index Prestasi (IP) brengsek itu.
Kita tidak berangkat dari Muhammad balik ke Adam sampai Muhammad kembali. Kita pemeluk Islam cukup dengan menuhankan Muhammad, menuhankan syariat, menuhankan iman, menuhankan Islam, menuhankan apa yang kita sangka Tuhan.
Kita tidak mengambil hikmah dari ke-ummy-an Muhammad. Kita lebih mengandalkan informasi melalui kalimat-kalimat di buku-buku sebagai ‘kue serabi’ yang siap disantap bulat-bulat. Kita ingin menghayati api dengan cara pergi ke perpustakaan dan mengobrak-abrik seratus buku tebal. Padahal mestinya sundutlah jidat ini dengan rokok menyala, baru buka buku untuk tambahan bahan nomenklatur.
Masalahnya pegangan kita bukan Qur`an Hadist, melainkan penghayatan dari kitab suci kita pakai untuk mencocokkan, mengontrol, meng-ishlah, meluruskan. Alif Laam Miim tak kau temukan melalui membacanya: hayati hidup, baru kau ketemu rahasianya. Lebih gawat lagi karena sesudah buku-buku pandai menyebar jutaan jumlahnya lebih dari dasawarsa terakhir ini, belum tampak juga tanda-tanda bahwa ia memiliki peranan dalam memperbaiki sejarah. Begitu banyak buku Islam dijual dan dibaca, namun belum tahu apa yang meningkatkan pada kualitas kaum muslimin. Mungkin haruskah kita tunggu hingga sekitar tahun 2010 ketika generasi pembaca buku saat ini naik memimpin sejarah. Atau barangkali dibanding sosialisasi buku-buku pintar, ‘perbaikan zaman’ lebih dimungkinkan justru buku-buku baik serta oleh uswatun hasanah yang disistematisasi oleh lembaga pendidikan khususnya dan lembaga politik dan lembaga kebudayaan pada umumnya.
***
Saya kira untuk tahap ini marilah berangkat seperti Ibrahim, menuntaskan disiplin penghayatan yang mandiri buku-buku simpan dulu di tas, sewaktu-waktu saja kita butuhkan untuk komparasi, legitimasi, atau ishlah.
Juga menyangkut buku-buku sastra. Saya belum melihat bahwa ia sudah pantas diandalkan untuk segala macam tujuan luhur itu. Secara teoritis sastra adalah kartu penting untuk merangsang dialektika penghayatan Ibrahim. Namun sayangnya basil karya sastra kita sampai saat ini, terutama sastra modern Indonesia termasuk karya-karya Emha masih dekaden dibanding karya para leluhur kita beberapa abad silam. Karya sastra modern kita masih berada pada tingkat ‘boleh tidak ada’. Taraf kualitasnya masih ‘mubah’, belum pada tingkat sunnah apalagi wajib. Kita hanya mengembangkan dan memang sanggup menggapai kecanggihan estetik; tapi muatan isinya, makrifat keilmuannya serta kearifan yang ditawarkannya — terus terang kita masih kanak-kanak atau paling jauh masih dibanding maqam Syekh Madekur, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan lain-lain. Dalam soal-soal yang menyangkut ilmu diri kemanusiaan, kita telah sukses untuk maju ke belakang.
Namun sebaiknya kita jangan percaya kepada asumsi-asumsi tersebut.
Kita adalah Ibrahim yang bertanya-tanya. []
(Diambil dari buku Emha Ainun Nadjib,
Nasionalisme Muhammad: Islam Menyongsong Masa Depan,
Yogyakarta: Sipress, 1995)