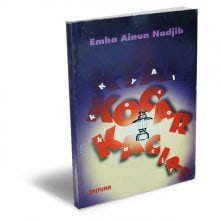Yang Terhormat Nama Mereka

Judul: Mereka yang Tak Pernah MatiPenerbit: BentangTahun: April, 2022Tebal: X + 262 hlm.ISBN: 978-602-291-894-3
Buku baru Cak Nun berjudul Mereka yang Tak Pernah Mati (2022) ini berisi persaksian yang menghimpun sejumlah obituari dan fragmen hidup orang-orang yang memperoleh bilik tersendiri di hati Cak Nun. Mereka adalah mata air sumur kearifan, ketulusan, dan keteladanan. Lewat sebanyak 51 esai yang terbagi dalam tujuh bagian ini Cak Nun mengajak pembaca, khususnya anak-cucu Maiyah, untuk berziarah kepada sosok-sosok yang telah mendahului kita maupun yang masih hidup bersama kita.
Hidup dan mati sering dimengerti sebatas ruang antara. Mas Sabrang pernah mengemukakan perbedaan antara rentang-hidup dan rentang-nyawa. Rentang-hidup adalah fase biologis yang dibuka dan ditutup dengan tirai kelahiran serta kematian. Sebaliknya, rentang-nyawa merupakan perjalanan jiwa, psike, atau roh yang melampaui tabir fisik-biologis. Sebuah perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan. Nyawiji. Maka pilihan judul buku ini sangat tepat. Mereka yang Tak Pernah Mati.
Bukan mengherankan pula kalau bagian pertama buku langsung menyuguhkan delapan esai di bawah kata Nyawiji. Esai pertama membahas Bulan Purnama Rendra (hlm. 2-8). Satu paragraf yang segera kita ingat adalah adegan Rendra tersedu-sedan saat bertanya apa bedanya Ahad dan Wahid. Lalu Cak Nun menjawab, “Mas, Ahad itu Allah yang Tunggal. Yang Satu. Yang Gagah Perkasa dengan Maha Eksistensi-Nya. Wahid itu Allah yang Manunggal. Yang Menyatu. Yang Integral, yang Merendahkan Diri-Nya, Mendekat ke Hamba-Nya. Nyawiji...” (hlm. 3).
Keintiman Rendra pada kata nyawiji kelak dinyatakan Cak Nun bahwa dia tak pernah pergi sebab dia sudah menyatu dengannya. “Mungkin Rendra memang telah pergi meninggalkan kita, jauh sebelum detik kematiannya, karena kita meletakkan diri semakin jauh dari titik ‘nyawiji’ — yang Rendra sudah lama menikmatinya,” lanjut Cak Nun. Makna nyawiji yang termuat di sana tak sekadar hubungan vertikal kepada Sang Pencipta tapi juga melukiskan kedekatan Cak Nun dan Si Burung Merak itu.
Kedekatan itu juga kita temukan dalam salah satu penggalan alinea di dalam obituari Bilik Cinta Kwangwung: Selamat Jalan, Mas Darmanto Jatman (hlm. 9-15). Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro ini merupakan “kakak” yang senantiasa memancarkan senyum keteduhan bagi Cak Nun sejak dikenalnya pada 1969. Mas Dar, begitu sapaan Cak Nun kepada beliau, pernah menampung “adiknya” saat demam tinggi tahun 1972. Waktu itu Cak Nun hampir terkulai lemas di trotoar Malioboro. Hanya “Mas Dar” yang memapah dan menuntun Cak Nun ke rumahnya di kawasan Taman Siswa.
Berkat kemurahan hati Darmanto Jatman itu Cak Nun menyatakan, “Andaikan ternyata kelak saya lulus masuk surga dan mendapat jatah rumah tidak terlalu kecil — dengan halaman depan dan samping yang cukup luas, serta kebun buah di belakang — insya Allah akan saya bangun paviliun di sisi kanan rumah untuk Mas Darmanto Jatman” (hlm. 11).
Ketulusan orang-orang yang telah purna tugas di kehidupan dunia itu masih dilanjutkan dengan obituari “manusia puisi” seperti Umbu Landu Paranggi (Mikraj Sang Guru Tadabur) dan Iman Budhi Santosa (Keindahan Namanya Adalah Kemuliaan Hidupnya). Termasuk pula dua sosok dalang yang dipanggil Allah pada titimangsa pandemi dua tahun belakangan: Ki Dalang Seno Nugroho (Tujuh Langit Manusia Jawa) dan Ki Manteb Sudarsono (Madhep Mantep Ki Sudarsono). Dan masih banyak lain seperti Syaikh Nursamad Kamba, Bunda Cammana, Yai Muzammil, keluarga Koeswoyo, Danarto, Beben Supendi Mulyana (Beben Jazz), dan lain sebagainya.
Selain obituari, buku ini memberikan porsi yang relatif seimbang dengan menyuguhkan tulisan-tulisan khusus untuk Cak Fuad, Novi Budianto, Ian L. Betts, bahkan jamaah Maiyah. Dalam rangkaian tulisan Mata Air Maiyah (hlm. 237-251), misalnya, Cak Nun secara khusus menunjuk “untuk anak cucu Maiyahku” sebagai “mereka” yang bukan hanya merupakan orang ketiga jamak, melainkan kesatuan keluarga yang dipertalikan oleh “getaran bersama” (hlm. 238): fid-dunya wal-akhirah dan kholidina fiha abada. Sebagaimana diutarakan Cak Nun sebagai berikut ini.
“Para pereguk mata air Maiyah diantarkan dan dihimpun memasuki suatu jagat kejiwaan di mana mereka mengalami kenikmatan bertauhid, ketakjuban ber-Islam, kesegaran silaturahmi, kemurnian ukhuwah, keseimbangan mental, kejernihan olah akal, keadilan berpikir, ketenteraman hati, kebijaksanaan bersikap, serta secara keseluruhan semacam keterbimbingan hidup.”
Kutipan paragraf ini menyiratkan suatu bentuk peneguhan kekeluargaan di dalam diri Maiyah. Pesan Cak Nun kepada jamaah karena itu sekaligus mengandung ikatan nyawiji yang pada dasarnya merupakan bagian dari keutuhan yang lebih besar. Buku ini berpusar pada kesadaran hulu-hilir semacam itu yang setidaknya mewartakan kepada sidang pembaca walau “ … di sini semakin tidak berarti, padahal senja makin meremang, Malaikat Izrail berkelebat-kelebat keluar-masuk semak-semak. Pendekar Bayangan mengendap-endap di antara tidur dan jaga” kita tetap donga-dinunga supaya selamat, disayang, dan dicintai oleh Sang Pencipta. Pada titik itulah sosok-sosok yang Cak Nun tulis dalam buku ini sesungguhnya adalah suri tauladan bagi kita semua.