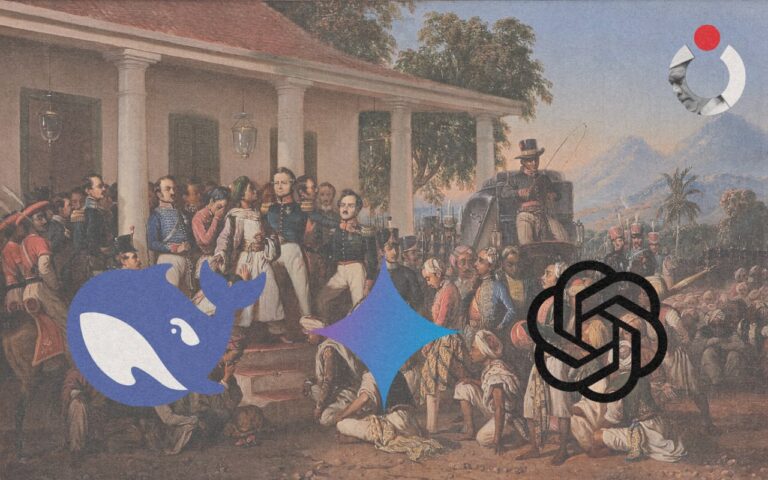Universitas dan Dosa Asal Pengetahuan
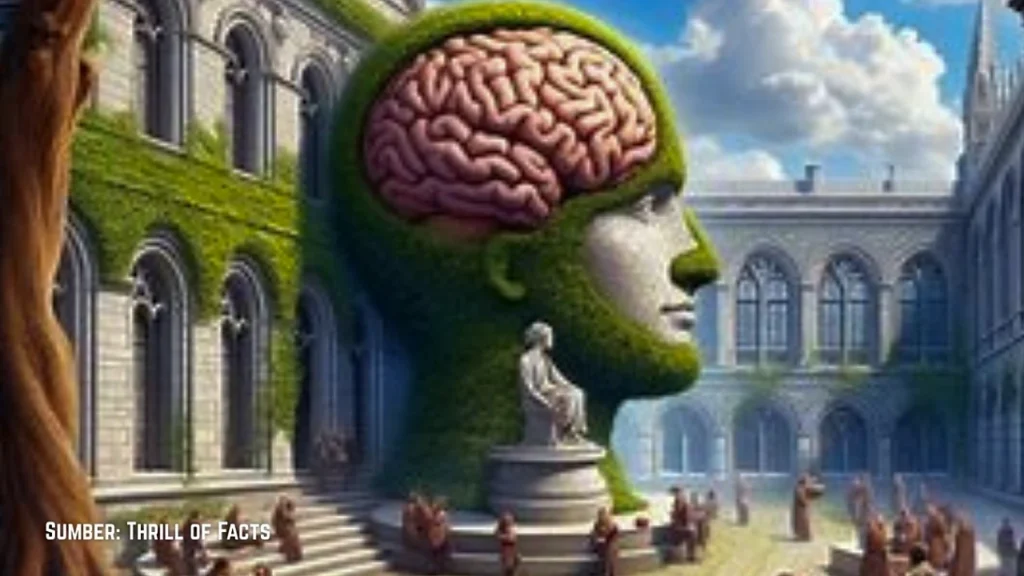
Perguruan tinggi, seperti juga manusia, punya dosa asal. Ia lahir bukan dari ruang hampa, melainkan dari pertengkaran—bahkan dari luka. Menelisik sejarah universitas di Amerika Serikat berarti membuka kembali arsip konflik iman yang tak pernah benar-benar selesai. Di sana, pengetahuan tidak tumbuh dari ketenangan, tetapi dari kegelisahan.
Di Inggris abad lampau, ketika agama masih menjadi poros kehidupan—termasuk pendidikan—gereja bukan sekadar rumah doa, melainkan penjaga gerbang ilmu. Katolik, Anglikan, dan Protestan saling mengunci pintu kebenaran. Siapa yang berhak mengajar, apa yang boleh diajarkan, dan kepada siapa pengetahuan diwariskan, ditentukan oleh tafsir iman yang sering lebih keras daripada akal sehat. Universitas menjadi semacam mimbar, dan ruang kuliah tak jarang berubah menjadi arena dogma.
Kaum Protestan, yang merasa terjepit oleh kekuasaan gereja dan mahkota, memilih eksodus. Mereka menyeberangi samudra, membawa kitab suci di satu tangan dan kecemasan di tangan lain. Amerika, tanah yang kala itu masih berupa janji dan mitos, menjadi halaman kosong tempat mereka menulis ulang takdir. Di sanalah Harvard berdiri—bukan sebagai menara gading, melainkan sebagai pos misi. Ia didirikan untuk mencetak pendeta, menyebarkan iman, dan menanamkan Tuhan ke dalam bahasa Latin dan Yunani.
Ironisnya, justru dari rahim misi inilah lahir universitas-universitas yang kelak mengklaim diri sekuler, netral, dan rasional. Ivy League—yang kini identik dengan elitisme pengetahuan dan kekuasaan global—bermula dari semangat yang sangat teologis. Seperti anak yang menyangkal orang tuanya, universitas modern kerap lupa bahwa darah iman mengalir di nadinya. Ia menyangkal asal-usulnya sambil menikmati warisannya.
Hari ini, kampus-kampus itu berdiri sebagai simbol kebebasan berpikir. Namun kebebasan itu, bila ditelisik, adalah hasil sublimasi konflik lama. Dogma diganti metodologi, iman diganti teori, mimbar diganti podium akademik. Tapi hasrat untuk “menyelamatkan dunia” tetap ada—hanya saja kini lewat indeks sitasi, riset kebijakan, dan legitimasi ilmiah.
Sejarah ini mengingatkan kita: pengetahuan tidak pernah sepenuhnya suci. Ia selalu membawa bekas-bekas pertarungan masa lalu. Universitas bukan kuil netral, melainkan medan tafsir yang terus berubah. Dan mungkin, di situlah maknanya—bahwa ilmu pengetahuan, seperti iman, selalu lahir dari konflik, dan hanya hidup jika berani mempertanyakan asal-usulnya sendiri.
Ketika peran gereja perlahan surut, kampus—khususnya Ivy League—tidak serta-merta menjadi ruang emansipasi. Ia hanya berganti tuan. Dari mimbar ke ruang makan malam para donor. Dari doa ke jejaring. Dari iman ke kekuasaan. Sejarah menunjukkan: kekuasaan jarang benar-benar pergi; ia hanya pindah alamat.
Ivy League lalu menjelma melting point para elite. Politisi, pengusaha, dinasti-dinasti lama bertemu di lorong yang sama, bukan untuk bertukar gagasan, melainkan memastikan satu hal: kesinambungan. Kampus menjadi sekolah warisan, tempat anak-cucu diajari bukan bagaimana berpikir, melainkan bagaimana berkuasa. Bukan bagaimana menguasai ilmu, tapi bagaimana menguasai orang lain—melalui relasi, simbol prestise, dan jaringan yang diwariskan lintas generasi.
Di sanalah secret society tumbuh subur. Ia bukan sekadar klub rahasia, tapi mekanisme seleksi sosial. Mahasiswa direkrut bukan karena paling cakap, melainkan paling “layak” masuk lingkaran. Mereka dididik untuk saling mengenal lebih dulu sebelum mengenal dunia. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan menjaga kerajaan—bukan membangunnya dari nol, apalagi mempertanyakannya.
Ironisnya, justru negara Amerika membaca kebutuhan lain. Menghadapi tantangan pertanian dan industri, pemerintah memberi land grant, mendirikan kampus “plat merah” seperti Texas A&M. Di sini, universitas bukan salon elite, melainkan bengkel. Ia mencetak insinyur, agronom, teknokrat—manusia yang dibutuhkan zaman. Mirip dengan politik pendidikan etis kolonial: ITB, UI, IPB didirikan bukan demi kebebasan berpikir, tetapi demi kepentingan negara dan mesin produksi. Bahkan kampus riset didorong lahir untuk menyaingi industri Jerman. Maka jelaslah: setiap kampus punya watak, dan watak itu ditentukan oleh siapa yang membutuhkannya.
Ketika kampus-kampus baru ini melesat dalam kualitas, Ivy League yang kaya justru tertinggal. Jawabannya bukan reformasi nilai, melainkan belanja besar-besaran: merekrut dosen dan mahasiswa terbaik dari seluruh dunia. Namun seleksi tetap kabur. Transparansi bukan prioritas, karena sejak awal misinya bukan mencetak manusia unggul, melainkan manusia berpengaruh. Kompetensi penting, tapi jaringan lebih menentukan. Kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan mengamankan status quo—bagi politisi maupun taipan.
Inilah ironi pendidikan kepemimpinan yang selama ini kita teladani dan banggakan. Ia terinspirasi dari Harvard dan kawan-kawan: merekrut pribadi-pribadi dengan latar tertentu—ambisius, berani ambil risiko, siap mengorbankan banyak hal demi puncak. Tak mengherankan bila alumninya selalu menemukan jalan ke kursi kekuasaan, tak hanya di Amerika, tetapi di panggung global. Dunia dikelola oleh jejaring, bukan oleh keutamaan.
Penurunan “daya hidup”—kata yang terasa tepat—ini bukan sekadar analisis, melainkan pengalaman. Ia dibagikan oleh mereka yang pernah berada di dalamnya, seperti pengalaman kuliah di Yale, yang kemudian diceritakan kepada calon mahasiswa di Tiongkok: bahwa Ivy League bukan surga meritokrasi, melainkan mesin reproduksi elite.
Fenomena itu terasa akrab. Seleksi beasiswa ke luar negeri—baik sponsor dalam maupun luar negeri—tak hanya mencari yang paling kompeten, tapi yang paling “berpotensi menjadi elite”. Dan tanpa disadari, pola ini merembes ke kampus-kampus besar di Indonesia. UGM dan kawan-kawan mulai terwarnai. Program mandiri membuka pintu lebar bagi latar elite. Temu alumni sering lebih mirip rapat pembagian pengaruh, meski dibungkus jargon kebangsaan. Cinta almamater dan jejaring kuat ditanamkan sejak ospek—sebuah loyalitas yang lebih mirip sumpah feodal ketimbang etika akademik.
Padahal, UGM—universitas negeri yang dulu lahir untuk melawan elite kolonial—dibangun atas spirit meritokrasi. Saya masih ingat masa mahasiswa: anak PNS golongan rendah, petani, UKM, duduk setara di bangku kuliah. Kampus menjadi tangga sosial, bukan pagar sosial.
Mungkin di sinilah pelajarannya. Kampus elite di Amerika, yang menjadikan jejaring sebagai agama baru, justru berkontribusi pada eksploitasi dunia—dan kini peran globalnya merosot. Kekuasaan yang terlalu lama diwariskan, kehilangan imajinasi. Dan pendidikan yang lupa pada merit, cepat atau lambat, akan kehilangan masa depan.