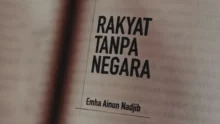“Gus Dur” di Rumah Sakit
Saya doakan semoga Allah berkenan meningkatkan rasa sayangnya kepada bangsa Indonesia, sehingga selama masa kampanye dan pemilu ini korban nyawa, harta, tenaga, pikiran, biaya dan ati kepangan tidak usah membengkak ke tingkat yang terlalu sia-sia.

Umat manusia di negeri zamrut wa yakut katulistiwa ini sedang kungkum dan bergelut dalam kotak-kotak kecil sempit berisi cairan tiga warna. Saya memilih bagian yang mendoakan tetap hidupnya ukhuwah kemanusiaan, tetap terawatnya nasionalisme, akal sehat kebangsaan, serta nurani dasar sebagai makhluk ciptaan Allah.
Nanti kira-kira tiga hari sebelum masa kampanye habis, kalau Allah memperkenankan — semoga mampu saya utarakan pendapat transparan saya sebagai warga negara Indonesia tercinta mengenai bagaimana sebaiknya orang kecil atau rakyat umum ngringkes wawasan dan membersahajakan gagasan agar menemukan pilihan yang terbaik di antara semua yang belum tentu baik.
Tapi hari-hari ini saya berdoa saja, meskipun tidak bisa dijamin bahwa doa saya lebih maqbul dibanding teman-teman lain yang hidupnya lebih sengsara dibanding saya, misalnya, kawan-kawan tukang angkut barang, kuli, pemulung, serta yang lain-lain.
***
Saya merasa sedang “disuruh mengantarkan barang” yang banyak orang semakin tidak membutuhkannya, padahal gratis.
“Barang” itu adalah kepercayaan terhadap doa, manajemen barokah, produk la-azidannakum yang tak tersangka-sangka dari setiap kejujuran hati kita, keadilan pikiran kita, serta kemurnian sikap dan perilaku kita. Juga sebaliknya: produk inna ‘adzabi lasyadid yang juga tak terduga-duga dari kecurangan pikiran, kotornya kalbu, atau adigang adigung adiguna-nya sikap kita kepada sesama manusia.
Di atas semua itu, benar-benar semoga Allah jangan sampai memaparkan di langit ayat “wallahu khoirul makirin”, gara-gara kita makar terhadap kebenaran, kefitrian, ketulusan, dan kejujuran hidup.
Demikianlah pengajian ndeso seorang mudin tiban dan darurat….
Seminggu lebih saya menunda kepulangan dari Jakarta ke Yogya gara-gara mendapatkan tugas-tugas mendadak menjadi mudin. Awalnya, Galang rambu Anarki, putra sulung Iwan Fals, dipanggil Allah. Besoknya, pada dini hari, menurut keluarga Iwan, datang tiga lelaki dari Jombang tak dikenal, tapi wajah-wajah mereka mirip saya semua. Datang entah pakai kendaran apa di rumah yang begitu keslempit dan susah dicari. Datang jauh-jauh dari Jawa Timur untuk mendoakan Galang dan menenangkan hati keluarganya.
Muncul sangkaan yang aneh-aneh, sehingga besoknya saya datang untuk tahlilan. Tapi, kedatangan saya yang juga tak mereka sangka-sangka itu malah menyempurnakan sangkaan mereka, padahal tiga lelaki itu sekadar mirip saya.
Sudahlah, yang penting saya ikut bertahlil. Pada tujuh harinya saya datang tahlilan lagi. Dan ternyata, tiap malam tugas saya di sekitar itu: tahlilan, yasinan, ta’ziyah. Kemudian diajak merintis “terbangan”. Kemudian ngaji al-Hasyr untuk nyonya sutradara sinetron yang kandungannya sudah lewat hampir tiga minggu, tapi bayinya belum turun juga. Esok malamnya dimasukkan ke acara nyleneh: shalawatan bareng-bareng pakai keyboard. Esok malamnya lagi saya “rampok” Gus Mustafa Bisri agar mengimami sebuah jamaah badan usaha, agar perusahaannya bermanajemen horizontal-vertikal alias kalkukasi dunia akhirat.
Lantas, kalau siang berjam-jam di rumah sakit. Ada kawan lama yang enak-enak melangkah ke luar pintu rumahnya mendadak ada colt nyelonong. Ia terlempar, ambruk, kepala retak, darah mengucur — alhamdulillah cuma gegar otak ringan — dan selama dalam keadaan “koma” terus memanggil-manggil saya. Ya Allah, segala puji bagimu, ada juga orang yang mengasihi saya, meskipun hal itu baru mereka sadari kalau sudah tak berdaya.
Kawan yang sakit ini berhari-hari belum sadar. Tapi, syukur bawah sadarnya bisa saya ajak bercanda. Kemurnian isi hati dan pikirannya saya tampung dengan kelakar-kelakar yang menggembirakan. Ia mengigau “Pancasila Yes! Pancasalah No!”
Saya tanya, apa itu pancasalah?
Ia menjawab “Keuangan yang mahaesa, kemanusiaan yang serakah dan tidak beradab, perseteruan Indonesia….”
***
Ketika saya asyik bercanda dengan sang pasien, tiba-tiba seorang sahabat masuk dan lapor: “Cak, Gus Dur ingin ketemu!”
“Lho Gus Dur?”
“Ya! Beliau ngamar di sebelah sana! Dia harus disuplai darah terus, dan sekarang sedang kesulitan cari darah….”
Saya langsung cium pasien sahabat kita itu dan loncat berlari. Sampai di kamar yang dimaksud, ternyata memang bertuliskan “Abdurrahman Wahid”. Saya masuk. Puluhan orang ngumpul dalam suasana penuh keprihatinan.
Ketika saya lihat ke ranjang, saya menghela napas panjang. Tapi saya tidak mau banyak cincong. Langsung saya cium kedua pipi dan kening beliau, kemudian mengangkat tangan, ber-washilah doa. Saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah salah satu debu hasil ciptaan-Nya, yang sekecil apa pun diberi hak oleh-Nya untuk Ia dengarkan dan siapa tahu Ia kabulkan.
Saya berdoa panjang. Tangis meledak. Kemudian sampai lama saya tidak tega meninggalkan ruangan itu, meskipun Abdurrahman Wahid yang terbaring di situ bukan yang ketua PBNU, melainkan seorang kiai kecil asal Gresik yang sudah 18 tahun di Jakarta.
Teman saya si pelapor itu benar-benar prima aktingnya.
Arsip dan dokumentasi Progress. Tulisan pernah dimuat di Harian Jawa Pos, 8 Mei 1997.