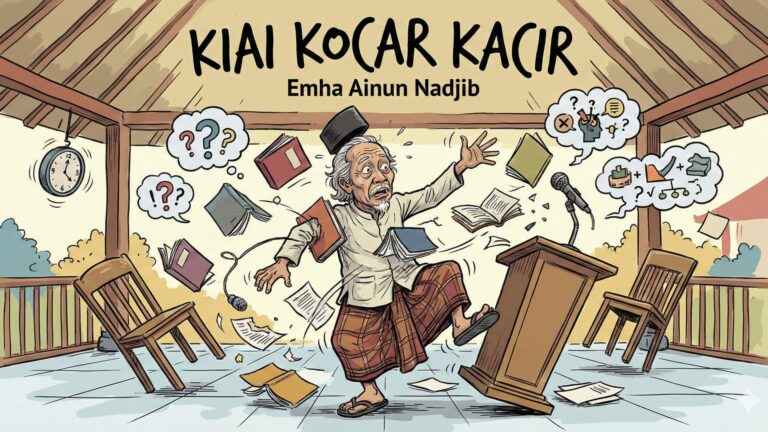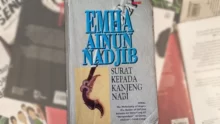Wartawan tanpa Kamera, Intelektual tanpa Kekudusan, Ulama tanpa Keberanian
Selama sekitar sepuluh hari [pada akhir bulan Nopember 1997] saya melakukan perjalanan panjang yang gegap gempita, riuh rendah, berjejal-jejal, namun sepi. Sungguh- sungguh sepi.
Dengan segala kerendahan hati saya menggunakan hak saya untuk menyebut perjalanan itu sebagai perjalanan kerakyatan. Argumentasi saya sederhana saja: saya ini rakyat, dan dalam perjalanan itu saya bertemu dengan rakyat dalam jumlah yang sangat banyak.
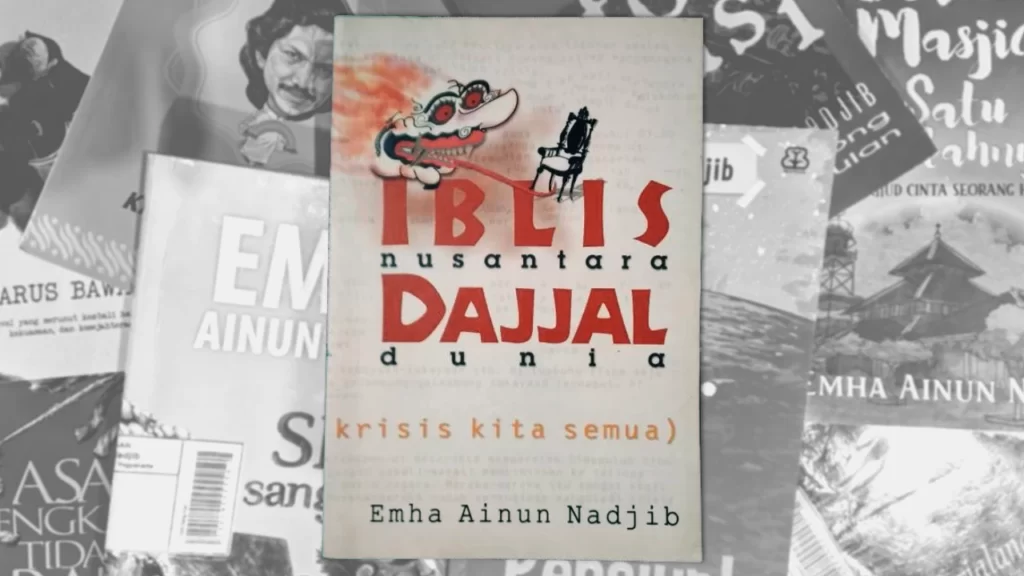
Benar-benar rakyat. Dari potongan pakaiannya, ekspresi wajahnya, sorot matanya, cara berpikirnya, kandungan hatinya, kesunyian batinnya, kelaparan dan kehausannya, sampai simpanan potensialitasnya — yang, masya-Allah, bagaikan gelombang dahsyat samudera besar — yang demi Allah kalau mereka bergerak, tak akan bisa dihalangi oleh 400.000 anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia.
Serta demi Allah jika gerakan itu dipimpin dan diakurasikan, sesungguhnya tidak sukar untuk sanggup menggulingkan kekuasaan sebesar apapun di negeri ini.
People Power di Nusantara ini sama sekali bukan hal yang mustahil. Yang masih mustahil dan tidak menentu adalah kepemimpinan atas mereka. Yang tidak pernah tegak adalah pemuka-pemuka mereka di strata menengah masyarakat kita ini.
Saya sendiri, masya Allah, hanya bisa berprihatin. Hanya sedih dan getir. Terutama karena saya bukan seorang pemimpin. Bukan ulama, bukan tokoh masyarakat, bukan pimpinan organisasi massa, bahkan bukan siapapun kecuali hanya seorang yang berusaha berada bersama mereka, dan syukur-syukur bisa bercengkerama dan menemani hati mereka. Suatu keajaiban yang diwasilahkan oleh Allah Swt. kalau seandainya sesekali saya diperkenankan ikut mengobati sakit mereka, turut mencarikan jalan keluar bagi mereka, bagi kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi, psikologi, hukum, politik atau spiritual.
Di stadion Gasibu Banyuwangi, penonton yang tak bisa masuk karena kehabisan tiket, biasanya bersikap destruktif, bikin ‘pentas’ sendiri, lempar batu ke dalam stadion, atau riuh rendah sendiri di antara mereka. Tapi malam itu dua ribuan orang yang tak bisa masuk stadion, duduk tertib memenuhi jalan raya, bersila, khusyu mendengarkan segala suara yang mengalir dari dalam stadion: puisi-puisi tentang kekecewaan politik mereka sendiri, musik-musik yang menggambarkan situasi hampir putus asa namun juga semangat untuk mengubah hari depan, serta kasidah-kasidah tentang kesunyian hati kerakyatan mareka.
Yang tampil di panggung mengatakan, “Saya tidak mementaskan apa yang saya maui atau saya rancang. Yang saya ungkapkan adalah isi hati orang-orang di depan saya sehingga yang mereka soraki dengan gemuruh adalah harapan hidup mereka sendiri, yang mereka tertawakan dengan riuh adalah nasib malang mereka sendiri, dan yang mereka tangiskan adalah kejumudan situasi kesejahteraan mereka sendiri.”
Di sebuah lapangan kampung di Malang lebih-lebih lagi. Muatan batin mereka tidak hanya diwakili oleh para penampil di panggung, melainkan mereka teriakkan sendiri. Puluhan ribu kepala berjajar memenuhi lapangan hingga tak berbatas dengan pinggir panggung, juga sampai ke atap-atap rumah dan dahan-dahan pepohonan. Atau sebagian lain yang hanya mendengarkan suara dari kejauhan karena sudah tak ada tempat lagi.
Mereka berdatangan dan berkumpul di situ tidak sebagai “fans” dari seorang idola atau artis. Mereka hadir tidak untuk berjoget dan besenang-senang. Mereka bergerombol tidak untuk melakukan kemewahan-kemewahan dan memasuki histeria hedonisme. Mereka berjamaah di situ untuk mempertemukan isi hati kerakyatan mereka, kesepian hati mereka, kegelisahan sejarah mereka.
Mereka menciumi tangan, pipi, badan atau apapun bukan untuk mengidolakan, melainkan menunggu wasilah entah dari mana, menanti jawaban-jawaban mengenai beribu kegelisahan dan pertanyaan hidup mereka: Akan bagaimana nasib kita besok ini? Apakah kita akan bisa menjadi manusia yang dimanusiakan? Apakah kita akan menjadi warganegara yang berpeluang memegang hak-hak sebagai warganegara? Apakah ada harapan yang lebih baik bagi nasib kami dan keluarga kami? Apakah milik kami akan tetap dicuri. dirampok, dan dimonopoli? Apakah akan ada pemimpin yang menyayangi kami? Apakah akan ada pemimpin yang merasa bersalah kalau hati kami bersedih, merasa berdosa kalau kami kesulitan mencari makan, serta takut kepada Allah kalau hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan kami diabaikan?
Di lapangan lain, di Bandungsari, Grobogan, betapa lebih dahsyatnya. Hampir lima belas ribu ummat berkumpul sejak sesudah maghrib. Yang ditunggu baru tiba sepuluh menit sebelum tengah malam. Namun mereka tak bergeming. Kemudian selama dua jam penuh mereka saling menumpahkan isi nasib mereka, berteriak-teriak, terkadang memekik-mekik.
Makan tak boleh terlalu kenyang. Lewat pukul 02.00 harus usai, namun mereka tidak mau beranjak. Mereka masih duduk diam berdesak-desakan. Mereka seoalah-olah menunggu janji dan harapan. Mereka seakan-akan tidak mau bergerak dari tempat itu sebelum ada sedikit kejelasan bahwa nasib mereka akan sedikit berubah.
Mereka bukan ummat pengajian, yang datang berkumpul untuk menunggu nasehat dan fatwa dari kiai jauh yang tak mereka kenal.
Mereka adalah rakyat Indonesia, yang kebetulan beragama Islam, yang menantikan sesuatu yang nyata bagi kehidupan mereka, bagi ekonomi mereka, bagi rumah tangga mereka, bagi nasib mereka, bagi kesejahteraan dunia akherat mereka.
Dan sungguh, manusia sejumlah itu bisa berkumpul di manapun di negeri ini. Dan sungguh, mereka sangat gampang untuk Anda ajak mengamuk, membakar dan menghancurkan apa saja, melindas dan menggulingkan siapa saja. Apakah tentara akan menembaki seribu orang, sepuluh ribu orang, dua puluh ribu orang di setiap kota sebagaimana Nazi dan Wasterling?
Sungguh mereka bisa menjadi gelombang pembanjiran sejarah yang detik ini juga siap mati untuk menjadi pilihan lain dari ketidakmenentuan nasib dan kesengsaraan hidup mereka sehari-hari.
Juga massa yang di Ponorogo itu, yang di Bungurasih, Surabaya, itu. Atau lihatlah bagaimana Kapolwil Pekalongan mencari Anda untuk mengemukakan kecemasannya atas kasus di Bojong, Kajen, Pekalongan hari itu. Beredar — di kalangan penduduk — isyu bahwa ada seorang karyawan (Jawa) dibunuh oleh juragannya (Cina). Pak Dandim pun mencari Anda meskipun tak ketemu karena perjalanannya dari Semarang ke Pekalongan dimacetkan oleh kecelakaan lalulintas di jalur pantura.
Rakyat sudah hampir mengamuk, karena secara nasional-struktural mereka memang punya argumentasi global untuk mengamuk.
Sampai akhirnya keresahan itu reda sesudah bisa kita buktikan bahwa yang meninggal bukannya si karyawan, melainkan si juragan. Sampai akhirnya tatkala malam tiba dan ribuan orang berkumpul, bisa kita tawarkan fenomena sikap yang lebih sehat namun memenuhi rasa keadilan. Kita tawarkan solusi-solusi yang lebih rasional. Solusi bagi ummat Muslimin yang harus memenuhi “bil-hikmah wal-mau’idhatil hasanah”. Solusi yang memaparkan bahwa yang terutama bersalah adalah pemimpin-pemimpin di atas, di mana aparat-aparat di tingkat lokal dan regional 50% merupakan pengikut kesalahan-kesalahan pusat dan 50% sskadar menjadi bemper akibat kesalahan pusat.
Tetapi sungguh, demi Allah yang hidup kita di tangan-Nya: ratusan ribu, jutaan rakyat itu benar-benar siap untuk berubah. Siap untuk menjadi gelombang yang mengubah sejarah.
Namun kita-kita di kota, kita-kita kaum intelektual, budayawan, tokoh masyarakat, wartawan, budayawan dan priyagung-priyagung lain — sedang terus-menerus sibuk dengan keasyikan kita sendiri. Sibuk dengan batas pengetahuan dan sangkaan kita sendiri atas apa saja, juga atas bagaimana sebenarnya kondisi rakyat.
Kita sibuk meng-headline-kan obsesi-obsesi lokal subjektif kita sendiri-sendiri. Kita sibuk mencari narasumber dan tokoh yang kita sangka paling penting untuk kemajuan Indonesia, kemudian kita yakini bahwa memang itu benar-benar yang terpenting, tapi kemudian kita kecele dan tidak pernah sadar bahwa kita kecele.
Pers tidak pernah punya keinginan sepercik pun untuk mengetahui apa isi hati rakyat Indonesia. Rakyat tidak punya nama. Bukan ‘names’, sehingga dianggap tidak ‘make news’ — bukan bahan berita.
Pers Indonesia tidak boleh kita impikan lagi untuk berpikir progresif dan menggabungkan diri dalam perjuangan bersama mendayagunakan segala aset dan fenomena perubahan yang sesungguhnya sangat dikandung oleh rakyat.
Wartawan kita hanya punya tape recorder untuk merekam “menurut Pak Anu” dan “Kata si Polan”. Wartawan kita tidak punya kamera untuk membaca fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat, tidak membawa alat pemotret untuk meraba, menyentuh apalagi mendalami dan menganalisis apa sesungguhnya yang sudah berkembang dalam kehidupan rakyat, serta apa yang sebenarnya bisa dilakukan dengan itu.
Kaum intelektual juga berlaga tidak dengan mementingkan kekudusan.
Kaum ulama terseok-seok tanpa keberanian.
Yang canggih kita lakukan bersama hanyalah sebagaimana kalbun yalhats.
Maafkanlah saya. Qulil-haqqa walau kana murran.