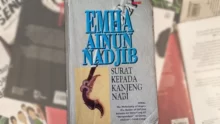Lebaran di Oro-Oro Ombo dan Senyum Kapitalisme

Kalau lebaran hampir menjelang, koran-koran biasanya memuat aktivitas khas sejumlah artis yang menyangkut kaum lemah. Seperti juga kalau tahun baru tiba, mereka menyempatkan diri untuk mengekspresikan cinta kasih sosial. Mungkin mengundang anak-anak yatim, gelandangan, atau para pemulung, untuk makan-makan bersama. Mungkin cukup dengan menyumbangkan sejumlah uang. Atau mungkin memilih bentuk-bentuk lain.
Kini saya menguakkannya kembali, karena momentum Idul Fitri memberi perspektif nilai yang berbeda dengan tahun baru. Juga karena salah satu firman Allah yang menjadi favorit saya adalah Fa-amma bini’mati rabbika fahaddits! Artinya: Dan adapun segala anugerah dari Tuhanmu, selalu insyafilah dan perkatakanlah!
Bagi mereka yang di hari Idul Fitri menyumbangkan harta bendanya untuk pamer, bagi siapa saja yang mengeluarkan uang dari koceknya untuk show atau ‘membeli reputasi’ atau demi ‘taktik bisnis’—kita bersumpah untuk tidak meremehkan, mencurigai atau apalagi mengutuknya. Lebih afdlal bagi kita untuk memilih untuk mendoakan mereka saja: semoga sesudah menikmati ‘terminal nilai’ pamer, show dan taktik bisnis, Allah membukakan lubuk kemuliaan hati mereka, agar beranjak menuju ‘terminal nilai’ motivasi yang lebih luhur, lebih mengandung karomah atau ketinggian derajat.
Kalau kita menjadi pelayan di supermaket, dan selalu tersenyum kepada para pengunjung karena memang demikian profesional approach kapitalisme mengharuskan: semoga ada sebagian pengunjung mendoakan agar senyum kita bukan hanya senyum kapitalisme, melainkan sungguh-sungguh senyum tulus kemanusiaan.
Demikian juga terhadap aktivitas para artis atau siapa saja yang “mengakrabi orang kecil” ketika Lebaran, kita doakan agar itu adalah lebih dari sekadar senyum kapitalisme. Manusia selalu memuai, dari kesempitan ke keluasan. Manusia senantiasa bergerak dari kerendahan ke ketinggian. Manusia selalu mengembangkan diri dari kehinaan menuju kemuliaan.
Memperbesar amal sosial pada Idul Fitri, antara lain berarti membersihkan harta. Pertama karena kita tidak pernah bisa menjamin bahwa seluruh uang yang kita miliki pasti halal, karena putaran uang kita semua ini secara sistematik banyak mengandung syubhat atau kontraversi secara hukum.
Kedua, karena kita amat jarang menyadari bahwa pada hakekatnya kita semua ini tidak punya apa-apa. Hak milik yang kita genggam dan dijamin oleh tata hukum formal suatu masyarakat, hanyalah perjanjian diantara manusia. Sedangkan di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatupun yang benar-benar milik kita. Dari nyawa, bulu hidung, energi kerja, batu bata rumah kita, logam-logam mobil kita, kecerdasan otak dan kotoran sapi perabuk tanaman kita—sungguh-sungguh merupakan produksi Allah yang kita sama sekali tidak punya saham apa-apa.
Maka dengan mendarmabaktikan sebagian harta kita kepada orang-orang lemah di Hari Raya, setidaknya mencerminkan bahwa kita ini cukup tahu diri sebagai makhluk Allah. Kita tidak bisa terus menerus, juga tidak akan kuat dan betah, tidak selalu bermental Fir’aun, yang merasa bahwa dirinya adalah produser, inisiator dan pemilik dari segala yang ada di genggamannya.
Kesadaran dan bukti untuk tahu diri itu, merupakan bentuk dari kemenangan orang-orang berpuasa. Hanya orang-orang yang menang yang berhak dan mampu memasuki perspektif nilai Idul Fitri. Setiap orang bisa melakukan puasa dan ikut pesta Hari Raya, namun tidak setiap mereka benar-benar mencapai kemenangan seperti yang dimaksudkan oleh makna Idul Fitri.
Kita sibuk kirim kartu bertuliskan Minal ‘Aidin Wal Faizin. Itu pernyataan harapan semoga kita, sesudah menggulati makna pengalaman puasa, diperkenankan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang kembali fitri dan mencapai kemenangan.
Orang yang menang, paralel dengan orang yang beruntung. Allah menuturkan term tentang menang dan beruntung melalui istilah ‘penghuni sorga’. “Penghuni sorga adalah mereka yang menang”, firman-Nya. Orang yang menang; pertama-tama menaklukan dirinya sendiri, mengalahkan kesalahan anggapan-anggapan tentang siapa dirinya dan apa yang dimilikinya. Orang yang berhasil mensorgakan dirinya, akan punya kemungkinan untuk mensorgakan lingkungannya. Mensorgakan diri bukanlah sukses menumpuk dan mempertahankan harta benda, kekuasaan dan perusahaan-perusahaan; melainkan tercapainya kesadaran tentang fitrah, bahwa itu semua milik, melainkan pinjaman dari Allah. Bagi mereka yang tak memperoleh bukti bahwa Allah meminjaminya delapan ratus perusahaan—sebab mereka memperolehnya dengan mencopet dari gudang rakyat, kemenangan ialah kesanggupan untuk memerdekaan dirinya dari keserakahan itu. Kalau tidak, ia tidak mengalami Idul Fitri.
Jadi, kalau Allah merangsang kita dengan “Capailah sorga!”, artinya adalah; jadikan dirimu, jiwamu, akal dan mentalmu, lingkungan masyarakatmu, menjadi sorga bagi kalian semua.
Seorang artis meminta saya mengantarkannya—menjelang lebaran—ke Kedungombo. Bertemu dengan sekelompok masyarakat yang kehidupannya tercecer di pinggiran waduk raksasa itu.
“Kenapa ke sana?”, saya bertanya.
“Nggak tahu ya…”, jawabnya bersahaja, “tapi rasanya mereka lebih fitri dibanding saya. Saya bisa belajar dari mereka tentang hidup yang apa adanya, yang murni. Dan saya dengar hidup mereka sangat ‘puasa’ hampir di segala bidang”.
Ia tidak bisa menjelaskan kemauan dan gagasannya sebagaimana orang intelektual yang articulated. Tetapi kita tahu maksudnya adalah suatu kesadaran betapa kita-kita orang kota terlalu banyak menyandang hal-hal yang tidak fitri. Di lain pihak kita pulalah yang punya kepandaian untuk merasa paling fitri. padahal orang Kedungombo setiap saat ‘berpuasa’ sehingga memperoleh ‘Idul Fitri’ berulang-ulang kali dalam setahun.
Saya sendiri merasa bahwa Kedungombo akan mengantar kami ke makna Oro-Oro Ombo, semacam Padang Mahsyar: di mana miliaran ruh manusia menghampar menyesali kesia-siaan hidupnya yang dihabiskan untuk menumpuk hal-hal yang tidak diangkutnya ke kekekalan.[]
**Diambil dari buku “Tuhan Pun ‘Berpuasa'”, diterbitkan oleh penerbit Zaituna, 1997.