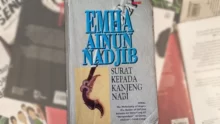Imunitas Kultural

Sang Tuan akhirnya percaya bahwa ia seorang tuan.
Si Budak akhirnya percaya bahwa ia seorang budak.
Padahal mereka manusia.
(Kiai Sudrun)
Di Yogya, ada kampung yang diiris oleh sebuah sungai. Orang menyebut sungai itu sebagai “WC Terpanjang se-Asia Tenggara” karena penduduk di sepanjang pinggiran sungai itu membangun tempat buang air besar yang berderet-deret.
Tak selamanya air memenuhi sungai. Sehingga tak selamanya pula the tinja bisa langsung diangkut oleh arus air sehingga berlomba seperti tatkala Abu Nawas dulu melakukannya dengan Khalifah Harun Al-Rasyid.
Maka kalau air surut, tak ada aliran air yang membawa pergi aroma produksi rutin manusia—salah satu sunnatullah alias hukum alam yang setia memelihara kesehatan badan manusia.
(Maksud saya, buang air besar itu hukumnya wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, setidaknya sehari sekali. Kalau hajat itu tak dipenuhi, sakitlah manusia. Meskipun di tengah sidang Kabinet Terbatas dan Darurat, kalau sang hajat kasih order, harus saat itu juga dipenuhi. Buang air besar itu posisinya sama dengan kewajiban terbitnya matahari tiap pagi, sel-sel memperkembangkan diri, tetumbuhan memuai meninggi, atau manusia hamba Allah memanifestasikan perbuatan baik dengan akal sehat dan hati nurani).
***
Alhasil sang aroma akan terakumulasikan dan mewarnai atmosfer. Kalau Anda melintasi tepian sungai itu, dalam beberapa menit peninglah kepala Anda, sebab ada rangsangan-rangsangan esktra kurikuler yang overdosis terhadap kerja saraf-saraf Anda.
Akan tetapi, para penduduk yang telah terbiasa dengan situasi lokal semacam itu, imun sudah hidungnya, kebal sudah saraf pembauannya. Kalau Anda tinggal di sana barang seminggu, insya Allah imunitas itu akan Anda peroleh juga.
Artinya, sesudah jangka waktu tertentu, Anda tak lagi membaui aroma itu. Dan sesudah sang waktu berlangsung lebih memanjang lagi dalam metabolisme pengalaman hidup Anda, pada akhirnya Anda akan percaya bahwa di sekitar sungai itu memang tak ada bau busuk apa pun yang perlu Anda cemaskan.
Adapun yang ingin saya tuliskan di sini ialah bahwa imunitas semacam itu tak hanya dialami oleh hidung dan saraf-saraf biologis. Melainkan bisa dialami juga oleh saraf-saraf psikis, spiritual, mental, bahkan intelektual dan kultural.
***
Misalkan saya ini putra seorang camat. Semua pegawai di kantor kecamatan bukan saja sangat sopan dan hormat kepada saya, tapi bahkan saya bisa menyuruh-nyuruh mereka. Bahkan saya juga bisa berbuat banyak hal kepada lurah-lurah bawahan ayah saya.
Mungkin saya tidak tahu bahwa penghormatan mereka kepada saya dikarenakan pamrih-pamrih tertentu kepada ayah saya, sehingga orang menyebutnya sebagai penjilat. Tetapi yang penting pada akhirnya saya yakin bahwa segala sesuatunya memang wajar demikian. Saya percaya bahwa karena saya adalah putra camat, maka semua bawahan ayah saya adalah juga bawahan saya, meskipun tidak dalam semua soal. Saya percaya bahwa saya bukan rakyat biasa sebagaimana rakyat pada umumnya. Saya adalah orang spesial dan sewajarnya memperoleh perlakuan spesial. Dan bagi saya yang namanya birokrasi memang demikian. Nothing wrong with it.
Nilai-nilai yang terbangun adalah pengertian dan kesadaran seseorang bergantung pada jenis informasi dan pengalaman yang diterimanya. Kalau saya dikurung dalam sebuah kompleks taman bonsai, maka bagi saya pohon beringin memang hanya satu-dua meter tingginya. Kalau orang bilang pohon beringin itu besar dan setinggi rumah, maka saya akan merasa itu aneh dan tidak benar.
Kalau pemahaman dan pengalaman hidup saya hanya ada informasi bahwa mencari kerja itu harus menggunakan uang pelicin, maka yang selain itu saya anggap tidak wajar. Kalau dalam lalu lintas uang selalu ada “talang bocor” alias ada pencatutan sistemik, maka bagi saya itulah yang wajar dan benar.
Kalau pegawai-pegawai teras di tingkat kotamadya atau kabupaten terkena demonstration effects khas manusia negeri dunia ketiga dalam bentuk perlombaan beli mobil BMW dan rumah-rumah luks, dan referensi itu mendominasi wilayah kesadaran saya, maka bawah sadar dan atas sadar saya akan selalu mengatakan bahwa “memang demikianlah kehidupan”.
Pada sisi lain, barangkali saya memperoleh juga informasi ideal dan konseptual tentang apa yang wajar dan apa yang tak wajar atau apa yang benar dan apa yang tak benar—saya akan mendidik diri saya untuk memilih di antara dua: mau ideal atau mau realistis. Kalau saya mengikuti arus, saya realistis. Kalau saya melawan arus, saya idealis dan utopis.
“Tuhan” saya adalah segala sesuatu yang saya anggap realistis, karena saya adalah manusia biasa, yang berpijak di bumi dan hidup “normal” di dunia biasa-biasa saja. Yang selain itu, saya sebut gila.
***
Sampai tingkat atau stadium yang saya yakin tak bisa disebut tidak parah, bangsa kita telah mengalami imunitas terhadap problem-problem korupsi, pencatutan, manipulasi, pembocoran, penyelewengan, kemunafikan, dan lain sebagainya.
Standar nilai kita tentang moralitas, kejujuran, kebenaran, keadilan, atau segala sesuatu yang pada saat-saat tertentu kita sadari sebagai yang terbaik untuk kehidupan telah mengalami penurunan yang serius.
Dosa, kecurangan, kepura-puraan, adalah barang jamak dan rutin dalam kehidupan kita. Sedemikian rupa sehingga kita tak lagi merasa berdosa, curang, dan pura-pura.
Saya jadi sedikit paham kenapa agama mengharamkan Ilmu Kebal. Kekebalan membuat kita tak bisa menangis. Tak bisa merasakan sakit. Tahu-tahu kanker sudah merambahi seluruh tubuh.
(Diambil dari buku Surat Kepada Kanjeng Nabi, Emha Ainun Nadjib, Mizan, 1996)