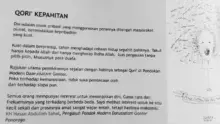Emha ke Amerika

Ditinggal ke Amerika, Patangpuluhan tetap saja bersinar. Seperti biasa banyak sahabat silih berdatangan. Kalau ada surat datang dari Amerika, seorang membaca keras-keras. Lainnya mendengarkan membayangkan Emha bicara.
Tapi sudah beberapa bulan tak ada berita. Harap-harap camas apakah Emha sakit. Tidak bisa makan. Kekurangan uang. Atau sedang berhadapan triple K (Ku Klux Klan) yang sangat menakutkan.
Kalau tidak punya uang itu pasti. Punya apa dia. Bayar kontrak saja tak pernah ada. Hanya satu kepercayaan. Dia adalah seorang sufi (dalam pandangan kami). Dalam keadaan apa pun mampu survive. Kemanunggalannya dengan Tuhan, kecintaannya dengan kekasih Allah yang menggembalakan langit dan bumi menguatkan keyakinan kami bahwa Emha tak kehabisan minyak. Isih urip. Durung mati. Ada dalam genggaman Sang Maha Rahman dan Rahim.
Datanglah beberapa peti terbuat dari kayu berukuran besar dari biro travel. Beratnya minta apun. Rasa ingin tahu mengundang hasrat. Ini oleh-oleh Amerika. Cuilan patung liberty ataukah merchandise bintang film Hollywood. Beramai kami membukanya dengan linggis pinjaman tetangga. Semua kotak ternyata isinya buku. Sampai kemringet ternyata isinya buku. Impian Hollywod lenyap.
“Siji wae ra mungkin dibaca Cak Nun”, seloroh kawan. Ya. Cak Nun tak mungkin baca. Berapa tahun kita hidup sesrawungan pernahkah ada melihat Kenun atau Markenun baca buku…..? Langganan koran juga tidak. Jika ada, paling hanya membolak balik thok sambil cengar cengir seperti tidak percaya. Kalau kirim artikel essei atau cerpen juga tidak pernah sama sekali ingin tahu apakah dimuat atau tidak.
Ya. Emha tidak pernah baca buku. Barangkali Al-Qur`an ketika mondok di Gontor. Dan tak mungkin sampai “ngelothok” karena menurut kabar dia dikeluarkan melakukan pemberontakan. Buku tentang ilmu awan jingga, gatholoco. Sama sekali tak disentuh. Saking kagumnya sama Emha, ada Ustadz muda yang kondang sak paran-paran bilang bahwa Emha itu kalau baca buku cukup dengan menempelkan telapak tangannya ke buku itu.
Siapa gurunya? Ilmunya dimana?
Alam semesta adalah gurunya. Dedaunan. Bebatuan. Asmuni Srimulat (almarhum), Basiyo, tukang becak. Mbok mbok penjual sayur yang pagi-pagi buta menggendong dagangannya ke Bringharjo dan entah apa lagi.
Beratus ratus judul essei, cerpen, dan entah berapa judul puisi jumlahnya tak terbilang ia kanvaskan di mesin ketik. Ia menulis seperti merokok. Kapan saja. Dimana saja ia mau. Tak terikat oleh lingkungan. Di tengah teman-teman bermain gaple, senda gurau tidak masalah baginya. Sambil menimpali kicauan mereka Emha duduk bersila di atas tikar sambil mengetik. Tak ada jarak antara yang ia tumpahkan dengan mesin ketik.
Emha bukan profesor, bukan pula doktor yang butuh ketenangan. Emha tidak terikat oleh keheningan, kesunyian. Emha tak bisa diikat dan mengikat.
Alhasil ketika tiba di Patangpuluhan — ia seperti baru saja mengalami perang brubuh. Carut marut dan banyak luka-luka merobek jiwanya. Betapa njomplangnya perbedaan yang ada. Betapa banyak pelacur bangsa yang menjual negara berlenggang seenaknya di Amerika. Silahkan bicara sekeras-kerasnya sampai robek mulutnya. Tapi jangan jangan menjelek-jelekan dan menginjak-injak negaramu di rumah bangsa lain. Kawan-kawan yang datang ditinjunya agar mampu melakukan perubahan. Indonesia tidak cukup hanya dicinta. Tapi harus dijaga dan dibela. Jika tidak cukup dengan keringat dan air mata. Jiwa raga taruhannya.
Ungaran, 1 Juni 2017